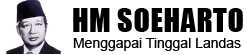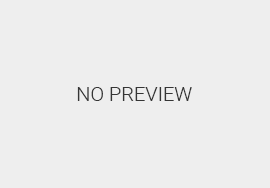KOLONG LANGIT
Tajuk Rencana:
KOLONG LANGIT [1]
Jakarta, Pelita
“Saya mendengarkan dengan tekun. Memasukkan baik-baik dalam hati. Dan menyaring dalam pikiran. Apa yang disuarakan dengan keras dan lantang. Apa yang disampaikan dengan lemah lembut dan halus. Juga apa yang tidak terucapkan. Semuanya itu membantu saya. Memahami segala, pikiran dankeinginan rakyat yang berkembang dalam Majelis ini”.
Itulah beberapa untaian kata-kata anak desa, Soeharto, ketika berdiri dimimbar MPR kawasan Senayan. Saat ketika bocah Kemusuk Godean yang kini tersepakati kembali untuk memimpin Republik ini, mengucapkan pidato sumpahjabatannya.
Kalau saya boleh mem-“puisikan” baris kalimat tersebut, dengan baris dan kuplet diatas yang memanjang, maka ekspresinya barangkali merentang dan berlabuh dalam lautan sebuah prosa politik. Komposisi, pilihan, dan penempatan kata dan kalimatnya mengedepankan sebuah orbit “upaya”.
Upaya adalah ikhtisar sopan. Jauh dari demagog, sepi dari pekik. Lengang dari sorak-sorai. Untaian kata-kata diatas mengungkapkan janji. Ada kesediaan yang tersedia dalam deposit sanubari. Dan karena ia janji dan upaya, ia punya risiko tagihan nanti dramatis atau tidak, tapi nanti setelah kurang lebih 60 buah purnama melintas katulistiwa republik ini, maka untaian itu akankita lihat gigitannya pada orbit itu. Upaya segan ditagih. Janji berakhir tagihan. Pesan, adalah awal dari amanah.
Kerinduan yang terbungkus rapi dalam elusan bangsa bemama UUD 1945 – Pancasila, telah nyaris 13 tahun disentuh, digenggam Soeharto, bocah dari Kemusuk Godean itu. Konstitusi toh harus disujudkan kepada keadilan, kebenaran dalam kebersamaan. Kekayaan segelintir bertahta, sementara kemelaratan masih saja mendukung keperihan nasional. Sementara kata tidak, walk-out, beda pendapat dalam persatuan kesatuan, baru dapat terucap dalam MPR kini setelah kegetiran Gestapu 1965, dengan hilangnya nyawa lima jenderal dalam semalam, yang susah ditemukan dalam sejarah manapun.
Sementara gerimis hujan merintik perjalanan Orde Baru, sang pelangi merentangkan warna warni kemilau yang menerobos dinding tata-surya. Pohon menggeliat terkantuk-kantuk, dan bumi basah digenangi banjir. Air mata dan napas sesak resah, masih saja cukup terpetik didahan dan reranting bingkai orbit dan silasila konstitusi.
Bagaikan puncak gunung yang biru kehitaman seolah menembus jagat, sementara lereng dalam tubuhnya mencair salju putih yang bemoktah hitam mengalirkan bau kesedihan dari raksasa yang perkasa. Apalah arti sang raksasa yang sedih?
Padanya tak ada harapan, hari esok. Padanya hanya butir airmata. Padanya hanya lereng dan tebing yang menunggu. Maka upaya atau pesan apapun pada raksasa seperti itu, hanya mudah dicari pada lembaran-lembaran komik. Sedapg komik, jarang mengedepankan ketuntasan. Karena ia selalu bersambung dan bersambung. Tak pernah usai.
Namun apapun dan bagaimanapun yang tetap aktuil dan sebagai kebenaran yang benar adalah bahwa dibawah kolong langit tak ada yang aneh. Manusia toh bisa hidup dan bisa mati. Seseorang naik, dan akan turun. Ada awal dan akan ada akhir. Kehidupan toh bakal lenyap juga. Bukankah kolong langit memang tidak ada yang aneh?
Keresahan juga komponen hidup. Komponen dunia, dimana aneh dankeanehan pada galibnya tak ada dibawah kolong langit. Kita hidup dan harus menerima semua itu. Hanya ada satu dan yang itupun sederhana amanah.
Barangkali ia akan bernama keputusan. Barangkali ia tersembul dalam kabut kebijaksanaan. Barangkali ia ada dalam instruksi. Iajuga ada disekitar operasi. Ia dalam evolusi. Ia ada dalam upaya. Sebab ia tentu saja bermula dari napas kehidupan.
Saudaraku, barangkali Sosok & Pokok kali ini hilang bentuk, hilang rasa. Barangkali anda benar. Kita sedang meniti minggu transisi. Kita sedang meniti ungkapan Presiden Soeharto diatasi juga apa yang tidak terucapkan.
Banyak yang ingin terucapkan. Tapi ”ada yang tetap tak terucapkan”, seperti kata penyair Chairil Anwar. Juga yang dititi oleh harian inisemenjak ia terbit 1 April 1974 lalu. Dikolong langit inimemang sungguh tak ada yang aneh.
Namun bersukalah saudaraku. Karena saudara-saudaramu telah mengatakan:
“tidak” dan”merela-ikhlaskan” agarjalur demokrasi inidigelarkan. Barangkali 1978 ini titik awal dari kebersamaan dalam beda pendapat. Kalau ada mahkota dibawah kolong langit, dimana tak ada keanehan, maka “upaya tidak”, adalah noktah puisi konstitusi yang juga tidak aneh. Allah Rabul Izzati sendiri tidaklah aneh apa pula kita. Doakan kami. (DTS)
Sumber: PELITA (04/04/1978)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 624-626.