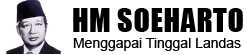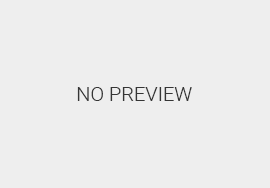MENGIKIS DAERAH KUMUH
MENGIKIS DAERAH KUMUH[1]
Jakarta, Media Indonesia
TEKAD Pemerintah untuk menangani daerah kumuh semakin dipertegas Presiden Soeharto. Saat meresmikan Rumah Susun Bidaracina Jakarta Timur kemarin, Kepala Negara menegaskan penanganan daerah kumuh harus mendapat perhatian dan menjadi tanggungjawab bersama, tanggungjawab pemerintah serta seluruh golongan dan lapisan masyarakat.
Menunjuk contoh, daerah aliran Sungai Ciliwung perlu dibenahi. Sebab daerah itu menurut Presiden merupakan salah satu daerah kumuh di Ibu Kota. Daerah-daerah kumuh sepanjang sungai itu dinilai telah mengotori sungai, menghambat aliran sungai, menurunkan mutu lingkungan dan banyak hal lain yang merugikan kita semua.
Salah satu jalan keluarnya, menumt Kepala Negara lingkungan kumuh yang padat penduduknya dan sulit diperbaiki melalui usaha perbaikan kampung hendaknya diganti dengan rumah susun yang lebih memenuhi syarat. Para pengusaha diminta untuk turut membangun rumah susun bukan hanya mewah saja, tapi juga yang sederhana.
Pernyataan Presiden Soeharto tentang perlunya penanganan daerah kumuh di Ibu Kota itu perlu menjadi perhatian kita, setidaknya untuk menghilangkan ironi yang terus terjadi di Kota Metropolis yang terus membangun dan diperlebar ternyata masih terdapat kantung-kantung daerah kumuh di tempat yang sama. Terasa amat mencolok dan timpang. Secara jujur kita sempat malu saat berlangsungnya Sidang APEC di Bogar, tempo hari, tiba-tiba istri Presiden Amerika Ny. Hillary Clinton meninjau daerah kurnuh di tepi Kali Ciliwung.
Benar kita tidak perlu menutup-nutupi realitas, akan tetapi walaupun persentasenya kecil, adanya kawasan kumuh dapat saja dinilai orang luar sebagai noda di tengah pembangunan. Orang luar bisa saja berlogika, kalau di Jakarta saja masih terdapat daerah kumuh, bagaimana dengan daerah-daerah lain.
Logika itu pun tidak salah. Kenyataannya memang demikian. Karena itu ajakan Presiden untuk bersama-sama menangani daerah kumuh, utamanya di Jakarta, kita nilai sangat tepat. Dan ini tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, pengusaha dan segenap warga mempunyai tanggungjawab yang sama.
Munculnya daerah-daerah kumuh selain karena ketidakmampuan sekelompok warga tertentu untuk merniliki nunah-rumah yang layak huni, juga karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada. Larangan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal di kawasan tepi sungai dianggap sepi. Demikian juga sisi rel kereta api didirikan bangunan tanpa izin. Sementara aparat pemerintah sendiri juga membiarkan berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Jalan keluar untuk mengatasi banyaknya daerah kumuh dengan mendirikan rumah susun seperti yang dikemukakan Presiden Soeharto kiranya perlu mendapat perhatian. Rumah susun merupakan bangunan yang membutuhkan lahan relatif sempit namun mampu menampung penghuni cukup banyak. Disaat tanah untuk bangunan di Ibu Kota yang semakin menyempit, efisien penggunaan lahan sangatlah diperlukan. Disamping itu, harga per unit rumah susun jatuhnya lebih murah dibandingkan dengan rumah rumah biasa, sehingga terjangkau oleh kelompok masyarakat kurang mampu.
Dengan rumah susun kesehatan bisa dipelihara, sehingga membangun rusun tentunya sama dengan meningkatkan martabat rakyat terbanyak.
Sudah barang tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah-rumah susun, apabila memang kebijakan itu menjadi pilihan.
Beberapa contoh tentang banyaknya pembangunan rusun kurang memenuhi standar seyogyanya juga menjadi pertimbangan. Misalnya keberadaan rumah susun sewa di Jakarta dengan tipe 18 yang saat ini cukup banyak dibangun Pemerintah Daerah ternyata dinilai kurang layak untuk dihuni keluarga. Bisa diperluas menjadi tipe 22 misalnya.
Tapi terlepas dari kondisi dan berbagai kendala yang ada komitmen untuk mengikis secara sistematis daerah kumuh di Jakarta patut mendapat dukungan semua pihak.
Sumber : MEDIA INDONESIA (25/03/1995)
_________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 719-721.