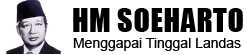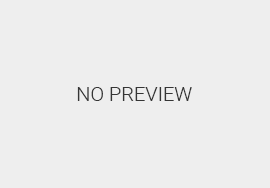MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI NASIONAL
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI NASIONAL
Oleh : Bambang Eka Wijaya
PRESIDEN SOEHARTO di depan DPR 9 Januari menegaskan :
"Kita harus mengerahkan segala kemampuan yang ada, agar mampu melalui rintangan yang sulit. Semua sektor dari bidang hams terus menerus kita benahi sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi nasional sebesar-besarnya".
Penegasannya dengan "semua sektor dan bidang" tersebut cenderung lebih mengarah pada Iingkungan pemerintah. Tetapi dalam kerangka tujuan mencapai "efektivitas dan efisiensi nasional", maka semua sektor dan bidang itu dengan sendirinya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat nasional.
Untuk itu, upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi nasional, berarti harus berlangsung klop tiga-dimensi, yaitu : dalam lingkungan pemerintahan dalam hubungan setiap organ pemerintah dengan masyarakat; dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian hanya apabila proses dalam ketiga dimensinya ini berlangsung seksamalah efektivitas dan efisiensi nasional akan bisa tercapai dengan baik.
Tulisan ini ingin melihat kemungkinan peningkatan dalam masing-masing dimensinya tersebut, dengan lebih dahulu coba mendekati apa efektivitas dan efisiensi dimaksud.
Efektivitas dan Efisiensi
Terpenting dalam efektivitas dan efisiensi adalah aspek idealnya. Efektifitas adalah bagaimana mencapai tujuan dengan terlaksananya segala sesuatu dalam prosesnya sesuai menurut ketentuan-ketentuan, aturan-aturan maupun hukumhukum yang ada.
Ini berarti bahwa dalam efektivitas, aspek idealnya lebih bersandar pada pendekatan sosio-kultural di mana; orientasi terhadap "apa yang seharusnya terjadi" (das Soffen) merupakan dasarnya. Jadi efektivitas adalah mencapai tujuan dengan melaksanakan kaidah-kaidahnya.
Sedangkan efisiensi, sandaran aspek idealnya adalah sosio-ekonomis dengan "apa yang seharusnya terjadi" adalah: bagaimana mencapai tujuan lewat jalan yang terdekat atau biaya yang termurah.
Orientasi tindaknya dengan demikian adalah usaha yang terus menerus sebagai proses untuk menekan risiko sampai yang sekecil-kecilnya.
Dalam prosesnya, efektivitas dan efisien harus dipandang sebagai sepasang kata manifest sesuai terminologi Merton, saling mensifati yang terpadu dalam tujuan. Jadi dalam prosesnya, efektivitas dan efisiensi harus seperti dua sisi sebuah jalur rel kereta api yang harus tetap sejajar sampai ke tujuan, sehingga efektif harus bersifat efisien dan sebaliknya efisien harus bersifat , efektif.
Dengan demikian pantas disadari bahwa dalam proses, keduanya merupakan kesatuan ideal yang tak bisa dan tak boleh dipisahkan. Memisahkannya akan sama dengan mencopot sebelah rel kereta api, yang bisa mengakibatkan kereta terguling dan gagal mencapai tujuan.
Contohnya: untuk efektivitas bendungan dibangun agar bisa berusia lebih lima puluh tahun dengan campuran semen 4 : 1, tetapi demi efisiensi dalam proses pembangunannya untuk memperoleh harga termurah dilakukan dengan campuran semen 10 : 1.
Akibatnya baru dalam usia 10 tahun bendungan sudah jebol, sehingga tujuan efektivitas untuk mencapai usia bendungan yang semula tidak tercapai. Makanya efektivitas dan efisiensi harus tetap sejajar dalam setiap tahapan proses mencapai tujuan. Hingga tak boleh asal ketentuan terlaksana tapi boros atau tidak efisien, sebaliknya tidak boleh pula asal murah tapi ketentuan tidak terlaksana secara efektif.
Dalam Lingkungan Pemerintah
Dengan terminologi efektivitas dan efisiensi seperti itu, dalam lingkungan pemerintahan sebenarnya sudah cukup hangat selama ini dengan program penertiban aparatur negara untukefektivitas dan program penghematan untukefisiensi. Jadi yang penting tinggal bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan programnya itu sendiri.
Untuk peningkatan tersebut dengan sendirinya harus semakin merasukkan fokus pengawasan pada proses pelaksanaan tugas sehari-hari setiap aparatur pemerintah. Sebab bagaimanapun juga, peningkatan tersebut hanya akan terjadi apabila prosesnya itu sendiri meningkat dalam efektivitas dan efisiensinya.
Pengawasan pada proses sebenarnya sudah merupakan isi pokok tugas pengawasan oleh atasan langsung. Tetapi karena justeru menurut pengalaman dalam pelaksanaan program efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah pertama-tama dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan mobil dinas untuk "lapisan atasan" ini, mungkin disebabkan penggunaannya di luar dinas lebih dari maksimal hingga resiko depresiasi kendaraan dengan biaya perawatannya menjadi lebih tinggi harus ditanggung dinas, menunjukkan kecenderungan orientasi "lapisan atasan" ini untuk sebagiannya terhadap efektivitas dan efisiensi masih kurang. Sekaligus berarti, dosis pengawasan terhadap proses ini masih perlu ditambah.
Untuk itu yang paling efektif dan efisien barangkali adalah dengan memperluas ‘job description" kelembagaan inspektorat dengan fungsi pengawasan operasional, dari fungsi pengawasan teknis-administratif sebelumnya.
Dengan begitu penampilan pegawai kelembagaan inspektorat akan lebih berwibawa lagi, sekaligus merehabilitir praanggapan yang pernah ada bahwa inspektorat hanya sebagai tempat "buangan" belaka.
Sebab kehadirannya di setiap bagian lain menjadi lebih efektif dengan bekal kewenangannya yang bersifat operasional. Sudah tentu, pengaturan mobilitasnya sehingga kehadirannya terasa konsisten di setiap bagian tersebut akan menentukan berhasilnya tekanan terhadap proses dimaksud. Dengan sendirinya pula pegawai inspektorat justru harus kualifikatif terdiri dari orang-orang pilihan dalam disiplin dan mentalitasnya.
Di lain pihak pengawasan terhadap proses yang kuat sekaligus akan bisa menutupi kemungkinan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan teknisadministratif yang lebih berorientasi pada pemeriksaan pembukuan apalagi yang hanya dilakukan sekali dalam setahun seperti pemeriksaan serentak Inspektur Jenderal Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Ini memperkuat asumsi bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemerintah diantaranya dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tugas seharihari setiap bagian atau kelompok aparaturnya.
Dalam Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat
Kondisi yang merupakan pemantul pancaran semangat peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam kubu pemerintahan ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap masyarakat, dalam proses saling-hubungan setiap organ pemelintah dengan unsur masyarakat. Saling-hubungan tersebut adalah proses yang harus atau dengan sendilinya terjadi dalam prinsip bahwa eksistensi pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat.
Pengaruh semangat tersebut dalam proses saling hubungan itu diperkirakan akan kuat sekali, karena justru adanya semangat tersebut "menguntungkan" pihak masyarakat akibat setiap ketentuan itu secara ideal efektivitasnyajusteru untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat di mana aparat pemerintah justru sebagai pelayannya.
Tetapi karena pada dasamya kompetisi dalam masyarakat senantiasa ada untuk mencapai tujuan masing-masing, prosesnyajuga bisa membawa arus-balik ke arah lingkungan pemerintah justru dengan kekuatannya untuk mengendurkan semangat tersebut.
Kekuatan arus-balik ini terletak pada acungannya yang lunak untuk suatu pemuasan tertentu sebanding dengan kepuasan yang bisa diperoleh pihak unsur masyarakat melalui proses tersebut.
Pengawasan terhadap prosesnya dalam hal ini mungkin cukup sulit karena kadang-kadang berlangsung secara halus sekali, hingga untuk "menangkap tangan" apalagi membuktikan secara formal tak bakalan bisa dilakukan. Paling hanya bisa disimak kemungkinan adanya keganjilan-keganjilan dalam prosesnya.
Karena sejak semula dan yang paling efektif serta efisien adalah pemancaran semangatnya dari dalam tubuh pemerintahan, maka tetap dari dalam tubuh pemerintahan pulalah pembendungan aliran prosesnya dilakukan. Dan itu paling efektif dengan petugas-petugas inspektorat yang merupakan orang-orang pilihan tadi membuat daftar keganjilan secara teratur dalam proses yang berlangsung untuk tempat-tempat tugasnya masing-masing, dengan akumulasinya dalam waktu tertentu mencapai jumlah tertentu diberi tindakan tertentu.
Dengan itu yang diharapkan adalah terjadinya proses yang semakin mengurangi keganjilan-keganjilan dalam saling-hubungan antara organ pemerintah dengan unsurunsur masyarakat, yang sekaligus sebagai bagian proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Sebab kedua sisi tersebut nampaknya seperti ayunan jungkat-jungkit di halaman sekolah taman kanak-kanak, kalau keganjilan-keganjilan naik berarti efektivitas dan efisiensi menurun, hingga sebaliknya kalau keganjilan menurun maka dengan sendirinya efektivitas dan efisiensi naik.
Dalam Masyarakat
Pengaruh semangat efektivitas dan efisiensi dari kubu pemerintahan tadi melalui saling-hubungan organ pemerintah dengan unsur-unsur masyarakat bagaimanapun akan merambat dalam masyarakat itu sendiri. Tetapi karena pengaruh itu hanya akan berkaitan dalam aspek keadministratoran pemerintah terhadap masyarakat, sedangkan untuk bagian kehidupan lainnya yang lebih luas dengan keleluasaan dalam kehidupan masyarakat justru merupakan pencerminan dari keberhasilan pemerintah mewujudkan kemerdekaan warganya, maka proses di dalam mekanisme dan struktur sosial itu sendiri yang akan lebih menentukan.
Dalam hal ini esensi persaingan dalam kehidupan masyarakat itu sendirilah yang mendorong, efektivitas dan efisiensi justru menjadi pilihan. Tetapi sebagaimana, pengertian efektivitas dan efisiensi yang kita maksudkan tadi, di mana pelaksanaan kaidah-kaidah yang ada justru sebagai sarana idealnya, maka yang harus terjadi adalah sejenis persaingan terbatas dalamkaidah-kaidah tersebut. lni sekaligus berarti bahwa persaingan yang berlangsung di luar kaidah-kaidah tersebut tidak efektif dan efisien.
Maka kalau dalam realitas esensi persaingan itu justru sebagai dasar proses bekerjanya mekanisme sosial dengan ciri-ciri strukturnya tertentu, pada proses bekerjanya mekanisme sosial menurut struktur masing-masing masyarakat itulah efektivitas dan efisiensi harus disuntikkan. Tetapi kalau dilihat pandangan para empu kita, mulai Kuntjaraai orientasi tindaknya.
Menurut pengalaman di negeri kita sejak medio dasawarsa 70-an, masalah ini sudah mulai mendapat penjabaran cukup menarik. Menyangkut struktur sosialekonomis peninggalan kolonial di mana "enclavisme" terjadi atas perkebunan besar dari kehidupan masyarakat lingkungannya, ditembus dengan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di mana keunggulan teknologi dan efisiensi pihak perkebunan besar disuntikkan kepada masyarakat sekitarnya.
Demikian pula dengan struktur sosial-ekonomis peninggalan feodal di mana petani kaya menjadi "patron" dengan petani miskin sebagai "klien", ditembus dengan Intensifikasi Khusus (Insus) di mana petani kaya dan miskin digabung dalam satu kerja sama yang mekanisme pembagian hasilnya cukup sebanding dengan partisipan petani miskin di dalamnya. Di sini juga, peran teknologi pertanian mendukung dengan inovasinya yang gemilang.
Dari situ terlihat bahwa model serupa masih perlu diperluas dalam semua sector dan bidang kehidupan, terutama dalam bidang industri hingga buruh juga bisa menjadi pemilik saham misalnya.
Pokoknya efektivitas dan efisiensi dalam masyarakat tergantung pada adanya kelembagaan substitusi di mana semangat gotong royong ditopang teknologi dan menejemen berada dalam kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Medan, 12 Januari 1984. (RA)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber : SUARA KARYA (19/01/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 521-526.