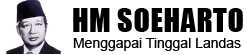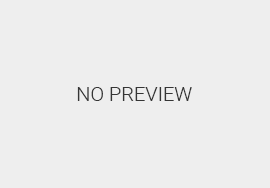SOEKARNO – SOEHARTO: KONTINUITAS DAN KOREKSI
SOEKARNO – SOEHARTO: KONTINUITAS DAN KOREKSI [1]
Djakarta, Kompas
APAKAH Soekarnoisme bangkit setelah Soekarno wafat?
Tidak tepat dikatakan demikian. Penghormatan pemerintah dan orang banjak jang meluap2, bukanlah pada Soekarnoisme melainkan pada manusia Soekarno, jang hampir 50 tahun lamanja sedjak 1926 berperanan dalam perdjoangan Kemerdekaan dan pembentukan bangsa Indonesia.
Jang dihormati setjara spontan lagi mendalam, bukanlah kekurangan dan kesalahannja jang memuntjak pada tahun 1965, melainkan djasa, kebaikan, pengorbanannja. Apa salahnja, kalau kebaikan dan djasa itu tertanam pada orang banjak? Saja tak melihatnja.
Menurut hemat saja bahkan ada manfaat jang fundamentil jaitu adanja kontinuitas antara masa lampau dan masa kini. Kontinuitas sesuatu bangsa memantapkan posisi bangsa itu. Kontinuitas mempertebal rasa senasib sepenanggungan bangsa itu. Kontinuitas memperkokoh persatuan.
Bagi Presiden Soeharto, kontinuitasnja dengan masa lampau memperkokoh kepemimpinannja. Ia tidak hanja memperoleh legalisasi konstitusionil, tetapi juga konfirmasi historis.
Usaha memupuk persatuan masa kini, dedikasi membangun kesedjahteraan orang banjak dengan pembangunan demokrasi Pantjasila adalah kelandjutan dari usaha masa lampau. Kita beladjar dari kelemahan, kesalahannja, kegagalannja.
Itu berarti, kita meneruskan warisan, kita mendjamin kontinuitas, tetapi kitapun bersikap korektif. Sikap kritis dan korektif ini tak kalah fundamentilnja untuk mendjamin agar usaha kita membangun berhasil. Untuk menjamin agar kepemimpinan Soeharto tidak mengulangi kesalahan2 Bung Karno.
Bukan itu sadja. Sikap kritis dan korektif diperlukan tidak hanja terhadap kepemimpinan Soekarno melainkan djuga terhadap sikap para pemimpin kelompok2 masjarakat dimasa lampau.
Selalu ada hubungan antara tipe kepemimpinan dengan watak masjarakat. Ada hubungan antara perangai kekuasaan dengan sifat kelompok2 masjarakat. Apabila kelompok2 masjarakat lewat para pemimpinnja tak mampu mengatur sendiri tata hidup politiknja, sehingga bisa berfungsi untuk membangun, nistjaja penguasa turun mengaturnja.
Intensitas tjampur -tangan penguasa sebagian ditentukan oleh mampu tidaknja para pemimpin kelompok2 masjarakat mengatur tata hidup politiknja bersama2. Mampu tidaknja mereka mematuhi persetudjuan dasar bersama jang normatif dan etis.
Mungkin agak berlebihan. Namun saja toh mendapat kesan masalah persatuan di negara kita ini bukan lagi soalnja rakjat hanja justru kebalikannja.
Tumbuh dalam postur kebapakan, Bung Karno mengembangkan paternalism dalam kekuasaanja. Ia merasa tahu semuanja dan mesti benar politiknja! Paternalisme dalam kekuasaan Negara tjenderung sekali untuk butuh keotoriterisme, itulah jang terdjadi.
Prosesnja kita tahu. Kekenesan (ijdelheid) pribadinja berperanan. Tetapi berperanan pula orang sekitarnja jang ikut menimbulkan ketjurigaan terhadap setiap bentuk kontrol, kritik dan koreksi. Timbul lapisan “sumuhun dawuh” jang makin luas, makin mengarus pula ke bawah.
Pada puntjaknja sekalipun dengan tudjuan jang berlainan, otoriterisme individu itu didukung dengan terror dari bawah jaitu oleh PKI. Sama sekali tak efektif lagi kritik tertutup, sedangkan kritik terbuka sudah lama mendjadi tahu.
Aspirasi dibangkitkan. Aspirasi itu bitjara langsung pada rakjat, maka didukungnja kemakmuran. lni dieksploitasinja bahkan roti itu sama sekali diterlantarkan sampai ekonomi bangkrut.
Kebadjikan2 disebarluaskan tetapi teladan dari atas tidak diberikannja. Demikianlah menjadi subur, salah kaprah, bahwa kekuasaan itu wewenang, bahwa dengan wewenang itu orang boleh menjalahgunakannja.
Karena tumbuh dari rakjat, memang Bung Karno faham benar akan aspirasi2nja. Tetapi lambat laun aspirasi itu mendjadi abstrak belaka, mendjadi sembojan belaka. Oleh orang2 sekitarnja ia dipisah dari kenjataan, dari peri hidup orang banjak jang sebenarnja.
Proses pengasingan (estrangement) dari orang banjak sebenarnja terjadi. Tetapi ia masih bisa mengatasinja dengan charismanja, dengan setiap kali berdialog langsung pada rakjat, dengan dukungan dari bawah oleh PKI dan golongan2 lainnja, meskipun semua itu tak wadjar lagi.
Orde Baru kontinuitas dari masa lampau, kepemimpinan Soeharto kelandjutannja. Tetapi kelanjutan jang disertai sikap dan tindakan korektif.
Dengan menghormati kepergiannja kita mengenangkan djasanja dan meneruskan kontinuitasnja. Dengan menghormati kepergiannja, kita memaafkan kelemahan dan kesalahannja.
Untuknja kita melupakan terapi untuk peladjaran kita sendiri, para pemimpin masjarakat dan pemerintahan Soeharto, kita tidak boleh melupakannja. Kita menarik peladjaran. (JAKOB OETAMA) (DTS)
Sumber: KOMPAS (03/07/1970)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 466-467.