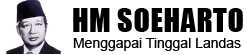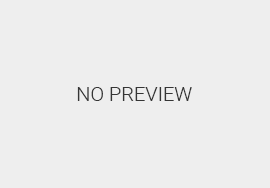BEBERAPA ASPEK DALAM UU TENTANG KEPRESIDENAN
BEBERAPA ASPEK DALAM UU TENTANG KEPRESIDENAN
[1]
Oleh : Patmono sk.
Jakarta, Merdeka
Persoalan mengenai perlu tidaknya undang-undang(UU) tentang kepresidenan telah lama diperdebatkan. Ada dua kelompok pendapat yang berpolemik dan hingga kini tidak pernah menemukan kata sepakat. Bahkan di kalangan para ahli hukum pun belum ada kata sepakat mengenai perlu tidaknya UU tersebut. Bagi yang berpendapat perlunya undang-undang itu, alasannya karena lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPA, BPK, MA serta DPR telah ada undang-undangnya.
Sedangkan yang berpendapat tidak perlu ada itu mendasarkan alasannya pada kenyataan bahwa tentang Presiden telah ada sekitar 14 pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengaturnya. Begitu pula kata mereka yang berpendapat tidak perlu ada UU tentang Kepresidenan, menimbulkan undang-undang itu berarti mengebiri UUD 1945. Ada apa sebenarya di balik polemik itu?
Ketika persoalan itu dimunculkan dalam dasawarsa 1980-an, pokok persoalan yang seringkali mengemuka adalah mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Mereka yang menginginkan adanya UU itu berharap, pembatasan masa jabatan presiden itu dilakukan seperti yang dilakukan di konstitusi Amerika Serikat yaitu dua kali masa jabatan. Tahun 1986, persoalan itu diangkat oleh Dr Suhardiman, Ketua Umum Depinas SOKSI yang waktu itu Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) bidang Polkam di Dewan Perwakilan Rakyat (DPPR). Hal ini pula yang dalam Sidang Umum MPR 1993 yang lalu diangkat oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), dalam sidang-sidang Badan Pekerja MPR, masalah ini diajukan oleh FPDI dalam rancangan dengan Ketentuan MPR tentang Lembaga Kepresidenan. Di Badan Pekerja MPR, Suhardiman yang dihadapkan kepada kliping koran yang berisi pernyataannya sendiri harus berkelit. Ia menyatakan pembatasan masajabatan presiden itu berlaku setelah 1998. Usulan dengan ketetapan dari FPDI MPR itu pun gugur, tidak disetujui oleh fraksi-fraksi yang lain.
Ini memang merupakan hal yang wajar di lembaga politik seperti MPR Fraksi PDI pun tentu menganggap kegagalan memperjuangkan aspirasi anggotanya itu merupakan lain hal yang biasa pula, karena usul mengenai hal itu pernah diperjuangkan pada Sidang Umum MPRI tahun 1973. Penafsiran terhadap “dapat dipilih kernbali” ini yang tidak memperoleh kesepakatan. Di satu pihak ada yang menafsirkan dapat dipilih kernbali itu hanya sekali lagi dan tidak terus menerus dipilih kembali, tetapi di pihak lain ada yang menafsirkan bahwa rumusan tersebut tidak ada batasannya. Jadi dapat dipilih kembali itu dapat diartikan setiap selesai masajabatannya dapat dipilih kembali. Persoalannya apabila ada UUD 1945 tidak dibatasi berapa kali seorang presiden dapat dipilih kembali, apakah pembalasan melalui TAP MPR atau UUmerupakan Penyirnpangan terhadap UUD? Untuk memberi penilaian terhadap penafsiran-penafsiran itu kita memang harus hati hati dan rasional. Apabila kita menilai secara emosional, apalagi kepentingan-kepentingan politik pribadi (vested interest) melekat dan mendasari penilaian kita maka yang kita peroleh adalah penilaian subyektif Dan rupanya itulah yang telah mewamai polemik mengenai hal itu selama ini. Mereka yang tidak setuju terhadap diadakannya UUitu memperoleh kesan bahwa sistem yang telah berlangsung selama ini salah, karena kita telah membiarkan terjadinya beberapa kali masa jabatan presiden. Pendapat yang didasarkan pada perasaan seperti itu tentu saja tidak benar. Menyatakan sesuatu yang telah lampau sebagai tindakan yang salah sementara kita berada di dalamnya dan ikut memutuskan tentu saja merupakan kenaifan. Terlebih lagi bila membiarkan sesuatu yang dianggap salah itu berlangsung terus menerus, tanpa ada keberanian untuk melakukan koreksi.
Pemerintah Orde Baru misalnya telah melakukan langkah awal, yang benar pada awalnya, yaitu berani melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu manakala ia tidak lagi berani melakukan koreksi terhadap kebijakan kebijakan setelah berlangsung sekian tahun , maka kebaruan orde yang telah menjadi “trade mark” itu harus dipertanyakan. Demikian juga yang menyangkut masalah lembaga kepresidenan. Sebagai lembaga yang diutus dalam UUD 1945 dan secara tegas dinyatakan tidak tak terbatas , lembaga itu harus diletakkan dibawah kontrol lembaga perwakilan, sebagaimana mekanisme yang dianut dalam UUD 1945. Pengaturan lembaga tersebut dalam undang-undang harus dilihat dalam konteks hukum yang disebut ekstra judicial. UU tentang lembaga kepresidenan bagaimanapun tetap perlu dibuat, karena dengan demikian lembaga tersebut berada dalam kontrol yang lebih pasti, terjangkau oleh Iembaga perwakilan. Walaupun lembaga kepresidenan itu di bawah MPR dan dipilih oleh MPR, apabila yang ada hanyalah pentilihan oleh dan pertanggungjawaban kepada MPR, maka tak ada kejelasan dalam mekanisme kontrol. Sebab MPR ditetapkan bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun dan itu yang dilakukan. Dalam keadaan seperti ini maka kekuasaan lembaga kepresidenan bisa menjelma dari “tidak tak terbatas” menjadi benar-benar “tidak terbatas”. Kalau itu yang terjadi maka kecenderungan untuk menjadi negara diktator sudah sangat dekat. Kita tentunya percaya bahwa hal itu merupakan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Selama ini mekanisme kontrol masih dapat dijalankan oleh Iembaga lembaga yang ada. Berkaitan dengan pokok penting dalam undang-undang kepresidenan, maka selain yang menyangkut pembatasan masa jabatan presiden adalah kedudukan presiden dalam hubungannya dengan kekuatan sosial politik. Dalam hal ini UUD 1945 telah menegaskan bahwa presiden sebagai Kepala Negara ada1ah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Pangti ABRl). Itu berarti presiden merupakan orang pertama dalam ABRl . Sedangkan ABRl dalam UU No. 20 tahun 1982 adalah Kekuatan Sosial Politik.
Hubungan
Dalam konteks di atas, maka kedudukan presiden sudah sangat nyata dan jelas. Lalu bagaimana hubungannya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain, khususnya dengan organisasi peserta Pemilu (OPP). Dalam hal ini presiden (dalam kapasitasnya sebagai pribadi) telah diangkat sebagai ketua Dewan Pembina Golongan Karya. Kenyataan inimemang merupakan sesuatu yang baru di Golkar, sebab dalam dasawarsa 1970-an (Munas I Golkar) Ketua Dewan Pembina Golkar masih dipegang oleh M Panggabean.
Walaupun dalam mengangkat ketua Dewan Pembina itu Golkar hanya menyebut nama pribadi tanpa jabatan yang melekat pada diri yang bersangkutan, namun siapa pun akan melihat kaitan antara ketua Dewan Pembina itu dengan presiden. Ini yang kemudian akan menutup kemungkinan netralitas presiden (baik dalam kapasitasnya pribadi maupun dalam kaitannya denganjabatan yang melekat padanya) dalam hubungannya dengan kekuatan sosial politik yang lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Akibat yang Jebih jauh adalah menyangkut sistem politik yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Selama ini kita mengenal Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem ini tidak ada oposisi, dan yang ada adalah kekeluargaan. Apabila kita kaitkan kedudukan pribadi presiden sebagai ketua Dewan Pembina Golongan Karya dan kaitannya dengan kemenangan-kemenangan Golkar dalam Pemilu, maka kita akan melihat kerancuan di dalam sistem ini. Sebagai perbanding kita dapat melihat kenyataan yang terjadi di Inggeris, di mana John Major sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) adalah Ketua Partai Konservatif, dalam hal ini Partai Buruh sebagai pesaing bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintahan, John Major. Pertanyaannya adalah, apakah ketua Dewan Pembina Golkar yang adalah presiden itu dapat disejajarkan dengan ketua Partai Konservatif yang adalah Perdana Menteri Inggeris? Tentu tidak! Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat (MPR) tidak hanya diusulkan oleh Fraksi Karya Pembangunan (GoIongan Karya), tetapi juga oleh Fraksi fraksi ABRI, PPP, PDI dan Utusan Daerah dalam Sidang Umum MPR. Lagi pula Presiden tidak hanya sebagai Kepala Pemerintahan tetapi juga sebagai Kepala Negara. Dengan kenyataan tersebut sudah seharusnya presiden berada dalamjarak yang sama dengan organisasi-organisasi peserta pemilihan umum (OPP). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sikap oposisi dari kekuatan sosial politik yang tidak terakomodasi dalam kabinet, walaupun pada kenyataannya mereka pun telah mencalonkan dan mernilih presiden yang sama. Itulah pokok-pokok yang perlu diatur dalam UU Kepresidenan tersebut. Dengan pengaturan itu maka semua kekuatan sosial politik akan ikut merasa telah mencalonkan dan memilih presidennya, sehingga dalam pembangunan sistem politik, asas kekeluargaan yang menjadi prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila itu bisa dilaksanakan seutuhnya.
Sumber: MERDEKA(l2/09/ 1995)
_______________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 267-271.