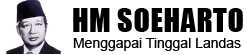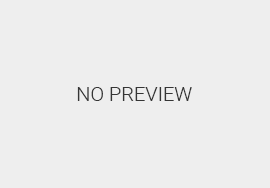BJ. Habibie: Pak Harto Menyatu dengan Aspirasi Bangsa (Bagian 1)
Menyatu dengan Aspirasi Bangsa (Bagian 1)[1]
BJ Habibie[2]
Pada saat Pak Harto merayakan ulang tahun beliau yang ketujuhpuluh tahun ini, berarti telah 41 tahun saya mengenal beliau. Dari tahun 1950 hingga tahun 1974 pertemuan antara Pak Harto dengan saya pribadi dan keluarga tidak sesering sebagaimana telah berlangsung sejak saya, pada tahun 1974, memperoleh kehormatan membantu beliau sebagai Presiden/Mandataris MPR melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Namun hubungan kerja dan silaturahmi dengan pertemuan-pertemuan yang sedemikian sering, teratur dan sistematis sejak tahun 1974 itu didahului oleh ikatan batin dan kekeluargaan yang telah berlangsung selama hampir 24 tahun.
Saya melihat Pak Harto pertama kali pada tahun 1950 di Ujung Pandang (Makassar). Pada waktu itu umur saya baru 13 tahun. Ketika itu saya sering melihat Pak Harto dengan ditemani oleh pemuda-pemuda lainnya, diantaranya Letnan Satu Subono Manthovani, anak buah beliau, yang sering berkunjung ke rumah dan kelak menjadi ipar saya. Saya melihat seorang muda, seorang pemimpin, seorang pejuang.
Saya melihat bagaimana waktu itu Pak Harto dengan yakin dan tekun melaksanakan tugas beliau di Makassar untuk menyelesaikan masalah Andi Azis. Saya tahu bahwa beliau datang untuk mempersatukan bangsa dari Sabang hingga Merauke. Saya kagum melihat kesadaran nasionalnya yang tinggi dan komitmennya yang tegas pada Sumpah Pemuda 1928. Saya memandang Pak Harto sebagai seorang pahlawan yang memimpin pahlawan-pahlawan lainnya untuk membebaskan bangsa kita dari sisa-sisa penjajahan melalui rencana yang sistematis yang dijiwai semangat perjuangan dan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Saya mengetahui bahwa waktu itu Pak Harto selalu memperhatikan kepentingan sekelilingnya sampai ke detail-detailnya; tidak saja kepentingan bawahannya sendiri tetapi juga kepentingan semua orang didalam lingkungannya, baik orang yang ia sukai maupun yang tidak. Kepentingan keluarga sayapun diperhatikan.
Umur beliau waktu itu baru 28 atau 29 tahun. kalau saya bandingkan dengan sikap dan perilaku beliau waktu itu dengan orang-orang muda berumur 28-29 tahun sekarang, jelas terdapat perbedaan yang jauh. Pada umur 28 tahun, pemuda Soeharto jauh lebih dewasa, jauh lebih berani. Kemandirian serta jiwa pejuang beliau tampak sekali; demikian pula kepeloporan beliau membuat terobosan-terobosan guna membangun sistem untuk membebaskan bangsa kita dari dampak penjajahan selama 350 tahun.
Dari sudut penglihatan saya sebagai anak kecil berumur 13 tahun, beliau adalah seorang idola yang patut dicontoh setiap orang, setidak-tidaknya setiap anak kecil seumur saya yang mampu berfikir dan berperasaan hati nurani yang dekat dengan keluarga, lingkungan, dan bangsanya.
Kekaguman itu bercampur dengan rasa haru yang mendalam ketika pada tahun 1950 itu ayah saya mendapatkan serangan jantung sewaktu sembahyang Isya di rumah. Semua itu masih jelas di bayangan saya, bagaikan suatu skenario yang tertanam didalam otak dan hati sanubari saya. Waktu itu saya berdiri di belakang ayah yang bertindak selaku iman. Dengan mata kepala sendiri saya melihat ayah terjatuh dan, dengan ucapan “Allahu Akbar, Allahu Akbar…”, mengakhiri hidup beliau.
Di saat itulah saya menyaksikan bagaimana Pak Harto bertindak tidak saja sebagai seorang pemimpin pemuda, tetapi juga sebagai seorang bapak, seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, seorang pemimpin dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.
Masih jelas dalam ingatan saya bagaimana Pak Harto menutup mata ayah saya, mendoakannya, serta menghibur ibu dan seisi rumah. Beliau berusaha meyakinkan agar kami menerima musibah itu dengan tabah.
Saya rasa tidak sukar bagi siapapun untuk membayangkan perasaan saya sebagai seorang anak belasan tahun pada saat itu. Siapapun, saya rasa, akan dapat memahami bagaimana pandangan anak itu terhadap seorang pemuda pejuang yang gagah dan tegas, tetapi begitu simpatik dan mesra, dan berhasil mengobati kesedihan serta kebingungannya dengan rasa hangatnya bimbingan dan hiburan yang meringankan beban musibah yang dialaminya. Tentunya perasaan itu akan tertanam untuk selama-lamanya di hati sanubari setiap anak kecil yang sangat mencintai ayahnya dan secara tiba-tiba harus mengalami ayahnya diambil kembali oleh Tuhan Yang maha Kuasa.
Disitulah, saya rasa, hubungan antara pribadi Rudi Habibie dengan pribadi Soeharto terpateri menjadi hubungan batin yang sangat erat. Pada saat ayah saya meninggal di tikar sembahyang itulah terbentuknya hubungan batin itu, ditakdirkan Tuhan, tanpa Pribadi Habibie dan Soeharto menyadari maksud dan tujuannya, apalagi maknanya untuk masa depan. Perasaan inilah yang hingga hari ini merupakan salah satu bekal yang diberikan Tuhan kepada saya dalam hubungan saya dengan Pak Harto sebagai manusia, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin bangsa, dan sebagai salah seorang pemimpin umat manusia.
Jika saya renungkan makna peristiwa itu dalam umur saya yang limapuluhlima tahun sekarang ini, maka dengan memanfaatkan ratio, saya dapat mengerti dan mendalami kepribadian seorang manusia Indonesia yang besar, seorang manusia Indonesia yang ditakdirkan untuk memimpin bangsanya dengan perasaan nasionalisme dan dedikasi yang tinggi pada bangsanya dengan sekaligus memiliki rasa kemanusiaan yang besar terhadap keluarga, dan orang serta rakyat di sekelilingnya. Sifat-sifat inilah yang menurut tafsiran saya, selalu menjiwai dan mengalbui Soeharto, putera Bangsa Indonesia.
Melalui ceritera-ceritera kakak tertua serta ipar saya yang mengabdi pada bangsanya melalui tugasnya sebagai anak buah Pak Harto, figur Pak Harto sebagai manusia yang patut dicontoh kemudian menjadi elemen yang secara insidentil dan sporadis memasuki sistem pemikiran saya selama masa perkembangan dari anak kecil menjadi seorang pemuda. Melalui ceritera-ceritera keluarga Subhono Manthovani itu, maka secara sengaja atau tidak, tetapi jelas, disamping Bung Karno dan pemimpin-peminpin Indonesia lainnya waktu itu, Soeharto sebagai pemuda yang pendiam tetapi tindakannya didalam perjalanan hidup saya selalu menonjol dan memberikan kehangatan, mungkin mempengaruhi pribadi saya sendiri dan perkembangannya sampai hari ini. Jika kita percaya pada Tuhan yang terus-menerus berkarya, maka pengaruh ini jelas diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. (Bersambung)
***
Catatan:
BJ Habibie terpilih sebagai wakil Presiden pada tahun 1997 mendampingi Presiden Soeharto dan secara konstitusional menggantikannya sebagai presiden, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti tahun 1998. Tersebar kabar bahwa sejak pengunduran dirinya sebagai presiden hingga wafatnya, Pak Harto tidak/belum berkenan menerima BJ Habibie atau BJ Habibie belum berhasil menemuinya. Hal itu memunculkan dua spekulasi:
- Kemungkinan pertama, Pak Harto ingin memberi ruang kepada BJ Habibie untuk menuliskan sejarahnya sendiri, agar sebagai presiden baru, tidak berada dalam bayang-bayang sejarah presiden sebelumnya, sekaligus melindungi BJ Habibie dari segala persepsi buruk atau propaganda hitam sejumlah kalangan, yang kesemuanya pada saat itu diarahkan kepada Pak Harto. Pak Harto tidak ingin membebankan propaganda hitam itu kepada orang lain, agar BJ. Habibie bisa fokus menangani dampak krisis moneter, yang mempertaruhkan jutaan masa depan rakyat Indonesia pada saat itu.
- Kemungkinan kedua, Pak Harto kurang berkenan soal lepasnya Timor-Timur dari NKRI. Pada saat itu Menteri Luar Negeri Ali Alatas kabarnya sudah hampir berhasil meyakinkan pihak-pihak terkait di dunia internasional untuk menyelesaikan soal ini melalui jalan diplomasi. Namun atas masukan dari para penasehatnya, yang jam terbangnya belum banyak, BJ Habibie memutuskan menggelar referendum yang menyebabkan lepasnya Timor Timur. Pak Harto tentu melihat suasana kebatinan para pejuang yang dengan susah payah mengintegrasikan wilayah ini dengan Indonesia dan suasana kebatinan penduduk Timor-Timur yang merasa terlindung dalam alam integrasi.
[1] BJ. Habibie, “Menyatu dengan Aspirasi Bangsa”, dalam buku “Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 370-373.
[2] Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam Kabinet Pembangunan V.