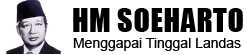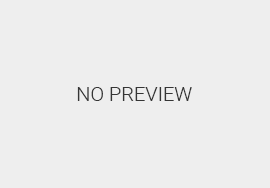DEPARPOLISASI : BUANG WAKTU
DEPARPOLISASI : BUANG WAKTU [1]
Djakarta, Harian Kami
BEBERAPA waktu jang lalu kita mensinjalir adanja pengorbit-an suatu gagasan tentang pentjiptaan suatu “floating masa” dari tingkat2 administratif dibawah Kabupaten. Singkatnja, gagasan tersebut menginginkan dilepaskannja masjarakat desa dari pengaruh partai2 politik. Operasionilnja, gagasan tersebut mengarah pada dilarangnja aktivitas partai2 politik dilingkungan desa-desa. Pada bulan jang lalu Pangdam Diponegoro, Majdjen Widodo untuk pertama kalinja pada tingkat propinsi mengketengahkan gagasan tersebut. Kurang-lebih 10 hari kemudian, Pangdam Djateng sekali lagi melalui tjorong RRI-Semarang mengkumandangkan idee ”floating mass”. Nampaknja “test-case” pertama pelarangan parpol beroperasi pada tingkat desa akan diadakan di Djateng.
Tjukup alasan bagi partai2 politik untuk setelah kekalahan mereka jang fenomenal pada pemilu jbl. tidak meributkan “issue” ini. Akan tetapi terlepas dari takut atau belum sadar kembali, kita beranggapan bahwa memang tiada alasan bagi parpol untuk chawatir. Sebenarnja sadja djuga tiada alasan jang tjukup kuat buat para penguasa untuk begitu menondjolkan suatu “target” jang dalam 9 dari 10 kasus desa toch sudah tertjapai.
Pada umumnja bisalah kita mengira-ngira bahwa “deparpolisasi” desa tidak mempunjai dasar alasan, pertama karena parpol sudah didjauhi oleh rakjat jang ketakutan oleh terulangnja terus-menerus pengedjaran2 terhadap beraneka-ragam parpol dari djaman kedjaman. Per-tama2, disekitar tahun 1948. PKI jang dikedjar: kemudian disekitar awal tahun2 1960-an, Masjumi dan PSI jang di-kedjar2; pada tahun 1965-1966, kembali PKI djang dapat giliran jang bersifat agak djangka pandjang. Setelah PKI, tidak lama kemudian timbul issue PNI-ASU, dst., dst. Logislah kalau rakjat didesa-desa sekarang melihat parpol sebagai momok jang lambat atau tjepat hanja membawa tjelaka sadja.
Alasan ke-dua, mengapa kita menganggap usaha “deparpolisasi” desa suatu usaha jang mubazir, adalah kenjataan bahwa parpol di Indonesia pada hakekatnja bukan parpol seperti jang dikenal dalam kamus2 politik. Partai politik Indonesia adalah wadah dimana aliran2 dalam masjarakat kita bergabung, seseorang masuk atau memilih parpol tertentu karena ia mengindentikkan sikap hidupnja dengan ideologi parpol tersebut. Tiada kartu anggota (ketjuali barangkali PKI), dan tiada kewadjiban apa-apa.
Ditindjau dari segi ini, besar kemugkinannja bahwa dimajoritas desa-desa parpol sebagai organisasi politik tidak ter-aktivitas. Paling banter ada kegiatan2 sosial, kegiatan2 pendidikan, dan itu biasanja dilakukan tidak oleh organ parpol, melainkan oleh organisasi2 sosial dan agama jang perlu diakui, oleh masjarakat desa diassosiasikan dengan aliran2 tertentu, aliran2 mana kemudian di-assosiasikan melalui simbol2 tanda-gambar pada parpol2 tertentu. Kesimpulan: sifat kegiatan parpol didesa-desa kebanjakan adalah tidak langsung.
Alasan ke-tiga jang perlu dikemukakan adalah tindjauan dari segi pengawasan. Salah-satu djalan keluar bagi parpol jang dilarang aktif didesa-desa adalah dengan tjara melalui “orang2 mereka” didesa mengkoordinir kegiatan di-beberapa desa, dus itu tidak lagi merupakan kegiatan desa melainkan mungkin sudah kabupaten.
Singkat dan padat, usaha deparpolisasi desa kita chawatirkan tidak mendasarkan daripada pengenalan kehidupan didesa-desa jang njata, tidak berdasarkan konsultasi setidak-tidaknja dengan beberapa sardjana, baik Indonesia maupun asing, jang pernah mengadakan penelitian didesa-desa; .”Assuch” gagasan tersebut adalah suatu kemewahan jang hanja bisa dilahirkan oleh pedjabat2 jang melihat desa dari djendela kamar2 kerdja jang “air-conditioned” dikota-kota besar. Kita dengan sangat mengandjurkan suatu penglihatan dan pemikiran dua kali, sebelum dilakukan suatu usaha jang memakan banjak ongkos serta waktu dan tenaga, tapi sebenarnja berdasarkan sedikit sekali alasan. (DTS)
Sumber: HARIAN KAMI (09/10/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 829-830.