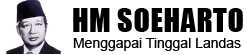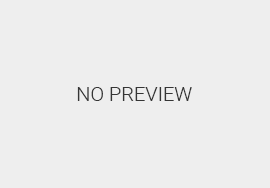Hal Kekeluargaan dan Monopoli
Hal Kekeluargaan dan Monopoli[1]
Saya tidak boleh jemu dengan memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi. Saya seperti tidak diizinkan untuk merasa capek dengan membangun dan membangun, sementara saya harus memecahkan persoalan-persoalan mengenai pembangunan itu. Tetapi sudahlah, saya jawab tantangan-tantangan itu. Untuk rakyat yang menaruh kepercayaan kepada saya, saya tidak boleh menyerah. Dan saya lakukan itu dengan senang.
Saya pergi ke Lombok Timur, ke Sembalun. Bertemu dan tatap muka serta bicara dengan para petani bawang putih di sana. Tentu saja temu bicara dengan petani itu tanpa teks. Seperti biasa. Dengan mereka saya mesti bicara jelas, gampang, dan terinci.
Kepada mereka saya tegaskan, agar prinsip-prinsip demokrasi ekonomi ditegakkan oleh segenap warga masyarakat dengan menempatkan usaha ekonomi sebagai usaha bersama secara kekeluargaan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya untuk sebesar-besamya kemakmuran si produsen, bukan hanya untuk si penjual jasa, juga bukan hanya untuk konsumen. Ketiga-tiganya harus melaksanakan prinsip usaha bersama dan kekeluargaan.
Filsafat demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 pada prinsipnya adalah menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Dan untuk dapat saling menghargai itu, pertama produsen atau petani harus diangkat derajatnya. Artinya, harga produksinya harus dihargai dan dilindungi.
Saya tanya di tempat itu berapa harga bawang putih di sana. Jawabnya Rp 1.500,- saja yang diterima petani. Padahal di pasaran harganya per kilo Rp 5.000,-. Itu artinya masih jauh sekali selisihnya. Andaikata separuhnya saja diterima oleh si produsen, si petani, maka ia akan menerima Rp 2.500,-. Karena itu si petani perlu berdialog dengan para pengusaha untuk menetapkan harga.
Dalam pada itu si konsumen perlu dilindungi. Artinya, jangan sampai harga bawang putih itu terlalu mahal. Konsumen juga perlu menikmati kemakmuran. Maka harga tertinggi harus dirundingkan. Dan ketiga, para penjual jasa pun hams dihormati karena mereka telah bersusah payah juga mengumpulkan, memproses dan mengantarkan bahan itu ke daerah-daerah dan bersusah payah meminjam uang dengan bunga. Ini pun harus dihargai dan diberi untung, tetapi keuntungannya itu harus wajar. Jadi, kepentingan masing-masing dipenuhi, baik petani, konsumen maupun penjual jasa. Itu prinsipnya. Tentunya ini tidak gampang. Tetapi begitu seharusnya. Ketiga pihak mesti berunding, mesti bisa berunding. Itu pemecahan secara kekeluargaan.
*
Dan sekarang, bagaimana soal yang disebut monopoli itu? Pertanyaan ini muncul lagi sewaktu saya menerima pengusahapengusaha swasta dari pelbagai negara yang datang di Jakarta. Pengusaha-pengusaha dari 19 negara, antara lain dari Singapura, Arab Saudi, Belgia, Finlandia, Jerman Barat, Amerika Serikat itu saya terima di Istana Merdeka di bulan Oktober (1987). Mereka adalah peserta World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia).
“Kapan pemerintah Indonesia akan mengeluarkan peraturan anti monopoli?”, tanya salah seorang di antara pengusaha-pengusaha swasta asing itu.
Saya jawab. Monopoli perseorangan tidak dibenarkan di Indonesia, karena itu bertentangan dengan Pancasila. Tetapi pemerintah Indonesia menjamin, bahkan melindungi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Memang pernah ada saran agar pemerintah kita membuat undang undang anti monopoli. Tetapi untuk itu hams dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan monopoli.
Jika monopoli yang dimaksud ialah penguasaan oleh negara pada sektor-sektor yang sangat vital demi hajat hidup orang banyak, itu bisa dibenarkan. Ini bertujuan untuk memberikan kemakmuran sebesarbesarnya bagi rakyat. Sesuai dengan UUD ’45. Pasal 33 UUD ’45 menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat lainnya menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penguasaan listrik oleh PLN, minyak, gas bumi oleh Pertamina dan semacamnya. Tetapi di samping itu penguasaan kekayaan alam oleh pemerintah itu tidak perlu harus secara fisik. Bisa juga melalui peraturan-peraturan. Tetapi monopoli perseorangan tidak dibenarkan di Indonesia.
Namun kepada para pengusaha dari mancanegara saya ingatkan tidak perlu khawatir. Pemerintah Indonesia menjamin kelanjutan usaha mereka yang telah dan akan ditanam di sini. Tetapi prinsipnya harus merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.
Saya ajak para pengusaha swasta dari berbagai negara untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah akan menciptakan iklim yang sebaik-baiknya dengan pemberian berbagai kemudahan.
Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, saham Indonesia dalam PMA dalam waktu paling lama sepuluh tahun harus mencapai jumlah mayoritas. Tetapi untuk meningkatkan gairah investor asing, pemerintah akan memperpanjang batas waktu dengan mengubah undang-undangnya.
Mudah-mudahan kebijaksanaan ini dapat menambah gairah investasi bagi penanaman modal asing. Hal ini tidak saja di bidang industri besar, tetapi juga di bidang industri yang berskala kecil.
Pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya dalam industri yang berskala kecil, terutama yang belum mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Tetapi dalam hal industri yang berskala kecil ini, pemerintah juga tetap mengutamakan memberikan kesempatan kepada investasi dalam negeri (PMDN). Investasi asing lebih-lebih saya harapkan datang pada sektor teknologi tinggi yang belum dikuasai oleh ahli-ahli Indonesia.
Saya ajak kalangan swasta untuk melakukan investasi pada jenis industri paling hulu. Misalnya di bidang baja, di bidang alumunium dan industri plastik untuk mendirikan pusat olivin, karena industri hilirnya sudah banyak dibangun.
Rasanya jelas sudah mengenai hal ini. Untuk waktu sekarang dan untuk masa yang akan datang.
***
[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta tahun 1982, hlm 513-516.