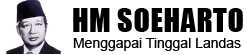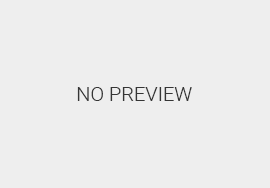Pak Harto Dan Trilogi Pembangunan (5)
Pak Harto Dan Trilogi Pembangunan (5)
Capaian-Capaian Pembangunan[1]
Oleh
Abdul Rohman
Terdapat dua instrumen pemersatu energi bangsa yang dipergunakan Presiden Soeharto dalam membangun kembali Indonesia. Pertama, konsolidasi orientasi idiologi kebangsaan yang diletakkan dalam pijakan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, visi kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa yang diletakkan dalam road map Trilogi Pembangunan dengan target yang dirumuskan secara jelas yaitu tercapainya tinggal landas (setara dengan negara maju) pada tahun 2019/1920. Target itu hendak dicapai melalui dua periode pembangunan jangka panjang (PJP) yang di distribusikan melalui tahapan pembangunan lima tahunan.
Dalam hal ini, ia (Presiden Soeharto) mengungkapkan bahwa:
“Mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu Pelita saja. Masyarakat adil dan makmur tidak akan jatuh dari langit, harus diperjuangkan melalui pembangunan secara bertahap, diperlukan landasan yang kuat, ialah industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh”[2]
Kelebihan Presiden Soeharto terletak pada kemampuanya mewujudkan gagasan dan agenda-agenda kebangsaan melalui manajemen organisasi yang rapi, tangguh dan efisien. Road map kemandirian bangsa yang dilaksanakan melalui trilogi pembangunan itu telah berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden. Selama periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% pertahun. Namun pada saat terjadinya krisis moneter dan disusul dengan krisis ekonomi pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot atau minus hingga kisaran 13,13%.
Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara. Antara tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, (2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.
Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, Indonesia juga mengalami peningkatan dalam penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia yang keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan ini menghasilkan akumulasi modal fisik maupun SDM bagi pembangunan bangsa secara umum. Sebagai ilustrasi adalah adanya peningkatan signifikan penanaman modal domestik (dalam negeri) yang rata-rata meningkat sebesar 50,43% pertahun selama kurun waktu 1976-1997. Kondisinya mengalami anomali pada era reformasi karena penanaman modal domestik mengalami penurunan atau minus rata-rata 17,20% pertahun selama lima tahun pertama reformasi (1998-2002).
Selama periode tahun 1990 s/d 1997, penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam untuk kemudian mengalami perlambatan oleh krisis pada tahun 1998. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 1999, akibat krisis politik berkepanjangan, penanaman modal dalam negeri terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.
Begitu pula dengan gairah pemodal luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 42,10% pertahun selama kurun waktu 1977-1997. Hal ini menandakan iklim investasi di Indonesia cukup diminati oleh investor luar negeri. Sejalan dengan trend penanaman modal domestik, penanaman modal asing juga mengalami anomali pada era reformasi yang mengalami penurunan atau minus rata-rata 15,04% pertahun selama lima tahun pertama reformasi.
Pertumbuhan tinggi yang dapat dipertahankan secara stabil juga meningkatkan tabungan domestik sehingga dapat mendorong tingginya tingkat investasi. Tabungan domestik selama kurun waktu tahun 1974-1996 meningkat rata-rata 69,08% pertahun.
Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang untuk mempaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO).
Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5 juta ton dalam periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.
Begitu pula dalam pengadaan papan, selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.
Sebagaimana diakui oleh Presiden Soeharto, usaha penyediaan papan bukanlah urusan gampang karena harus didukung oleh pembangunan industri bahan bangunan:
“Ternyata usaha ini merupakan usaha besar yang kompleks, yang sungguh tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Karena itu, dalam usaha menyediakan perumahan bagi rakyat, kecuali melaksanakan pembangunan perum,ahan melalui Perum Perumnas, pemerintah juga berusaha keras untuk menyediakan bahan-bahan bangunan rumah dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Itulah sebabnya, disamping membangun perumahan rakyat, pemerintah juga berusaha keras mendorong pembangunan industri bangunan rumah, seperti pabrik-pabrik semen, kayu, besi dan lain-lainnya. Melalui Perum Perumnas, kita berhasil membangun perumahan rakyat dimana-mana, baik di kota-kota besar, di kota-kota sedang maupun di kota-kota kecil”
Pemerintahan Presiden Soeharto juga berhasil melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial.
Atas keberhasilan Indonesia ini, Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi[3].
Prestasi ekonomi pemerintahan Presiden Soeharto merupakan buah dari kebijakan pembangunan yang tepat yang dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan tersebut antara lain[4]:
- Sistem perekonomiam berdasarkan managed market economy atau pasar terkelola dengan hati-hati karena ketidaksempurnaan pasar.
- Pengelolaan ekonomi makro yang baik, sehingga menghasilkan kinerja ekonomi makro yang stabil yang mendorong meningkatnya kepercayaan internasional dan dalam negeri serta investasi di sektor riil dan prasarana.
- Kebijakan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan, yang mudah terjangkau oleh penabung non tradisional dan pedesaan, sehingga meningkatkan tabungan melalui berbagai reformasi dan deregulasi.
- Kebijakan pendidikan yang awalnya menitikberatkan pada pendidikan dasar, menengah dan teknis secara luas, yang mampu mempercepat peningkatan ketrampilan kerja.
- Kebijakan pertanian yang menekankan pada pemberdayaan —bukan perlindungan—, tidak dikenakan beban pajak yang berlebihan, dan sistem pengairan yang baik, sehingga mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing sektor riil.
- Pengendalian distorsi harga dan ekonomi pada batas yang wajar.
- Keterbukaan dengan luar negeri terhadap dana, gagasan-gagasan dan teknologi.
- Penyediaan infrastruktur ekonomi yang baik.
Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain kebijakan anggaran berimbang, pemerintahan Presiden Soeharto juga mempertahankan kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs yang kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik investasi dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, yaitu terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.
Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang. Pada saat itu terdapat dua jenis pinjaman yaitu utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni 1966) dan utang baru (yang diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa macam pinjaman lama yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara Eropa Timur (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.
Untuk menjaga etika hubungan internasional maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut dan akhirnya dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara Paris Club pada bulan April 1970 untuk penyelesaian tunggal dan menyeluruh utang-utang Indonesia dengan kesepakatan[5]:
- Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.
- Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.
- Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.
- Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.
Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya dan mengalokasikannya untuk biaya kegiatan pembangunan yang produktif. Kehati-hatian ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde Baru dengan era reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan Presiden Soeharto mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan reformasi yang mencatatkan utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. Pada saat mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mencatatkan utangsebesar Rp. 553 triliun. Sedangkan 10 tahun pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang sebesar Rp. 1667 triliun.
Selain membangun sektor pertanian yang tangguh, komitmen Presiden Soeharto mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa tercermin dalam pengembangan industri-industri strategis berbasis high tech (teknologi tinggi). Melalui Kepres No.59 Tahun 1983, ia menetapkan 10 BUMN strategis dan dalam perkembangannya bertambah dengan sejumlah industri strategis lainnya[6]:
Strategi pembangunan jangka panjang telah menentukan perlunya landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam bidang ekonomi, landasan yang kuat itu diwujudkan dengan pengembangan industri yang tangguh dengan dukungan pertanian yang kuat. Tangguh dalam arti memiliki daya tahan yang lama dan daya saing yang keras. Karena itu memerlukan pemilikan teknologi yang tepat.
Beberapa BUMN strategis pada era reformasi telah dijual (privatisasi) dengan alasan efisensi. BUMN-BUMN strategis berbasis high tech yang dibangun atau dikembangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto antara lain:
1. PT. IPTN, berdiri tahun 1976, bergerak di bidang kedirgantaraan, ddan telah menghasilkan produk pesawat CN 235, helikopter NBO 105, Terpedo SUT.
2. PT. PAL berdiri tahun 1980, bergerak di bidang kemaritiman, produknya berupa kapal patroli cepat, kapal kargo, kapal tanker.
3. PT. Pindad, berdiri tahun 1950 (masih era Presiden Soekarno), bergerak dalam bidang persenjataan, dengan produk senapan serbu, pistol, meriam, panser.
4. PT. Dahana, berdiri tahun 1975, bergerak dalam bidang produksi bahan peledak, produknya berupa jasa pemboman, peledakan, produksi bahan peledakan.
5. PT. INKA, berdiri pada tahun 1981, bergerak di bidang perkeretaapian, dengan produk-produknya berupa lokomotif, KRL dan KRD.
6. PT. INTI, berdiri tahun 1974, bergerdak dalam bidang telekomomunikasi, produknya berupa jaringan telpon, multi analyzer protocol.
7. PT. Krakatau Steel berdiri tahun 1970, bergerak dalam bidang usaha produksi baja, dengan produknya berupa baja berbagai jenis.
8. PT. Boma Bisma Indra, berdiri tahun 1971, bergerak dalam bidang produksi kontainer, produknya berupa lube oil station, boiler, feed drier.
9. PT. Barata, berdiri tahun 1971, bergerak dalam bidang pengecoran, dengan produknya berupa jasa konstruksi teknik dan manufaktur.
10. PT. LEN, berdiri tahun 1985, bergerak dalam bidang elektronika, dengan produknya berupa sistem persinyalan, sistem elektronika pertahanan dan pembangkit listrik
11. PT. Telkom, bergerak dalam bidang dibidang telekomunikasi, dengan produknya berupa jaringan telekomunikasi
12. PT. Indosat, bergerak dalam bidang operator satelit dengan produknya berupa jasa layanan satelit dan produk telekomunikasi lainnya
Berdasarkan ilustrasi diatas, capaian prestasi pembangunan yang telah ditorehkan Presiden Soeharto telah secara nyata mengarahkan Indonesia untuk melaju dalam track terwujudnya tinggal landas dalam dua tahap pembangunan jangka panjang. Agenda tinggal landas mengalami keterputusan akibat krisis politik yang datangnya menyusul hampir bersamaan dengan krisis ekonomi dan moneter. Terdapat beberapa kalangan yang bermain dalam memanfaatkan krisis ekonomi dan moneter —termasuk kelompok kepentingan internasional— yang targetnya untuk mengendalikan potensi-potensi strategis Indonesia —dengan menumbangkan Presiden Soeharto— dan hal itu tidak direncanakan secara tiba-tiba.
Agenda kepentingan internasional itu tercermin dari Bill Clinton yang merasa perlu mengungkapkan pelepasan dukunganya terhadap Presiden Soeharto pada saat kampanye presiden Amerika Serikat tahun 1992. Sebagaimana dikutip Lee Kuan Yew melalui bukunya berjudul “From Third World to First “ (2000) dengan sub judul “Indonesia: From Foe to Friend”, dalam kampanye 1992 itu Bill Clinton mengungkapkan sebagai berikut:.
“Mereka tetap tidak berubah untuk memenuhi kebutuhan ditegakkannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan pelaksanaan HAM. Perang dingin telah usai. Tidak ada lagi alasan untuk “memanjakan” (molly-coddle) Soeharto” [7]
Fadli Zon dalam bukunya berjudul “Politik Huru Hara Mei 1998” juga mengungkapkan pernyataan Michel Camdesus, Direktur IMF yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the conditions that obliged President Soeharto leave his job”[8]. Dua penyataan dari dua tokoh berpengaruh internasional itu mengindikasikan bahwa telah sejak lama Presiden Soeharto —dengan agenda tinggal landas-nya— menjadi target untuk ditumbangkan. Setelah itu aset-aset strategis Indonesia —dengan alasan efisiensi— mulai berpindah kepemilikan kepada pihak asing yang bermarkas di Singapura.
Menjelang krisis ekonomi-moneter-politik di Indonesia (tahun 1997-1998), Presiden Soeharto juga bersitegang dengan Jepang dalam upayanya memutus ketergantungan teknologi dan produk otomotif dari Jepang. Melalui Inpres No. 2/1996 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membangun mobil nasional dengan beberapa fasilitas, terutama bebas pajak impor barang mewah. Pada tahun pertama Mobnas ditargetkan memiliki local content, sebesar 20%, dan pada tahun kedua 40% serta 60% pada tahun ketiga. Komponen-komponen untuk mobil nasional dapat diimpor bebas bea masuk dan bebas kewajiban pajak-pajak lain selama tiga tahun pertama. Sementara produsen mobil lain tetap dikenakan kewajiban untuk membayar bea masuk 100%[9].
Permasalahannya terletak pada joint partner yang kali ini tidak melibatkan Jepang —yang dinilai Presiden Soeharto tidak ber-iktikad baik dalam alih teknologi selama 20 tahun lebih kerjasamanya dengan Indonesia— yang keberadaannya sebagai salah satu investor terbesar bagi pembangunan Indonesia dan merupakan pemasok produk otomotif ke Indonesia. Joint partner proyek Mobnas ini adalah KIA, perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea Selatan yang dinilai ber-iktikad baik melakukan transfer teknologi. Melalui Keppres No. 42/1996 pemerintah mengijinkan kerjasama Mobnas dibuat diluar negeri sejauh memenuhi syarat dalam kriteria muatan lokal dan dibuat pekerja-pekerja Indonesia. Melalui keputusan Menperindag, PT Timor Putra Nasional (PT TPN) —yang dimiliki Tomy Soeharto— sebagai perintis mobnas, karena dinilai sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki persyaratan untuk menjalankan proyek tersebut. Kebijakan ini tentunya memukul produsen otomotif Jepang yang telah menguasai pasar otomotif Indonesia selama lebih dari dua puluh tahun.
Jepang yang didukung Amerika Serikat membawa permasalahan ini ke meja WTO namun dibalas oleh Presiden Soeharto dengan realitas ketergantungan Jepang terhadap kebutuhan minyak mentah dari Indonesia untuk keperluan industrinya serta ancaman Asosiasi Importir Indonesia (GINSI) untuk memboikot produk-produk Jepang jika WTO menjatuhkan sanksi secara tidak adil kepada Indonesia. Begitu seriusnya kebijakan mobnas bagi Jepang membuat PM Jepang Ryutaro Hashimoto menanyakan langsung kepada Pemerintah Indonesia dalam kunjunganya ke Jakarta pada bulan Januari 1997. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa alasan memilih perusahaan Korea Selatan sebagai joint partner PT TPN bukan dilatarbelakangi alasan diskriminasi, akan tetapi murni pertimbangan ekonomi. Kerelaan KIA Corporations mentransfer teknologinya secara ekonomi menguntungkan Indonesia[10].
Bargaining Indonesia melalui ancaman kelancaran pasokan minyak dan boikot impor produknya telah menyurutkan Jepang membawa kasus mobnas ke meja WTO. Akan tetapi setelah itu menyeruak black campaign yang beredar di Indonesia bahwa proyek mobnas merupakan proyek diskriminatif dan sarat KKN, karena dikelola putra Presiden. Melihat latar belakang mencuatnya kasus ini, tidak mustahil kalangan produsen otomotif Jepang dan para principle-nya di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap menyeruaknya tudingan itu yang kemudian digemakan seiring tuntutan reformasi politik tahun 1998. Proyek mobnas pada akhirnya mengalami kegagalan seiring keputusan pengunduran diri Presiden Soeharto sehingga ketergantungan terhadap teknologi dan produk otomotif dari luar negeri (khususnya Jepang) semakin tidak bisa dihindari.
Presiden Soeharto juga menampakkan kegigihannya manakala memperoleh tekanan agar struktur APBN tahun 1998 disesuaikan dengan keinginan IMF. Begitu pula dengan tekanan internasional — termasuk melalui Lee Kuan Yew, Menteri Senior Negara Singapura— terhadap pencalonan BJ Habibie sebagai calon wakil presiden pilihannya. Habibie dikenal sebagai ujung tombak Presiden Soeharto dalam pengembangan industri strategis dan keberadaanya sebagai Wapres akan mendorong percepatan kemandirian industri-industri strategis Indonesia berbasis high tech. Presiden Soeharto tentu menolak tekanan dan campur tangan IMF yang terlalu dalam karena menyadari implikasinya terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa. Mengikuti tekanan itu sama artinya dengan menyerahkan Indonesia —yang nyaris berhasil mewujudkan tinggal landas— kedalam kendali kebijakan kelompok-kelompok kepentingan internasional melalui tangan IMF.
Pernyataan Bill Clinton dalam kampanyenya tahun 1992 dan tekanan-tekanan internasional pada saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan bukti kuat adanya peranan kelompok-kelompok kepentingan internasional dalam krisis politik tahun 1998. Agenda mereka bukan hanya menjatuhkan Presiden Soeharto dari jabatannya, akan tetapi untuk memutus keberhasilan Indonesia dari tahapan-tahapan tinggal landas —termasuk penguasaan aset-aset dan potensi strategis— sehingga keberadaannya tetap dapat dikelola sebagai pasar bagi produk negara-negara maju. Membiarkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang mandiri berarti terlepasnya kendali Asia Tenggara dimana Indonesia menjadi regional leader-nya.
Keterputusan agenda tinggal landas akibat krisis ekonomi dan moneter barangkali tidak akan terlalu parah —dan dapat dilanjutkan kembali— manakala terdapat soliditas komponen bangsa. Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi 1998 yang didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing sehingga soliditas bangsa tidak bisa segera terwujud. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai beragam instabilitas (keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi) sehingga keberlangsungan agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.
Target mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan dari 20 besar negara di dunia pada tahun 2005, hanya bisa diwujudkan dengan predikat sebagai “the emerging market” atau negara yang pasarnya sedang tumbuh dengan stabil dan dalam hal ini merupakan bahasa halus dari “tempat pembuangan produk negara-negara maju”. Sedangkan target tinggal landas (setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020) dengan struktur perekonomian yang didukung industri pertanian dan industri strategis yang kuat justru semakin menjauh. Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi de-industrialisasi pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan siapa loyalis nusantara yang sesungguhnya.
[1] Disarikan dari buku Politik Kenusantaraan
[2] G. Dwipayana & Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 1989), hlm.254
[3] G. Dwipayana & Ramadhan KH, Op. Cite, hlm 242.
[4] Sri Hadi, Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm 25
[5] Widjoyo Nitisastro, Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjoyo Nitisastro, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm 201
[6] G. Dwipayana & Ramadhan KH, Op. Cite, hlm 280.
[7] Sulastomo, Lengser Keprabon, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 109.
[8] Fadzli Zon, Politik Huru Hara Mei 1998 (Jakarta: Institut For Policy Studys, 2004), hlm 4
[9] Dr. Syamsul Hadi, Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik industrialisasi dan modal Jepang di Malaysia dan Indonesia, (Jakarta:Pelangi Cendekia, 2005), 327.
[10] Ibid, hlm 328.