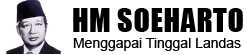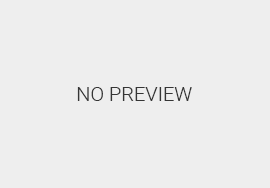Prinsipnya Tak Tergoyahkan
Prinsipnya Tak Tergoyahkan[1]
Oleh:
H Alamsyah Ratu Perwiranegara[2]
Perkenalan saya dengan Pak Harto terjadi ketika beliau menjadi Deputi I di Mabad (Markas Besar Angkatan Darat) dan saya perwira menengah yang diperbantukan pada beliau. Pada waktu itu beliau berpangkat brigadir jenderal dan saya letnan kolonel yang baru saja pulang ke tanah air setelah menyelesaikan sekolah kemiliteran di India. Jadi di Mabad inilah saya mengenal beliau dari dekat, yaitu dalam kerangka hubungan formal fungsional. Pada waktu Pak Harto masih. menjadi Panglima Divisi Diponegoro, saya hanya mengenal beliau dari jauh saja, karena saya bertugas di Palembang.
Pada akhir tahun 1960 ketika beliau mendapat tugas sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, saya bersama dengan beberapa orang perwira, antara lain Kolonel Achmad Wiranata kusumah dan Overste Dharsono dan beberapa perwira menengah lainnya, membantu beliau untuk mempersiapkan semua rencana yang akan dilakukan sehubungan dengan tugas beliau tersebut. Tetapi saya tidak dapat terus membantu beliau, karena saya dikirim ke Amerika Serikat untuk belajar di US Army Command and General College, Ft. Lavenfort, Kansas. Ketika saya pulang pada pertengahan tahun 1962, Pak Harto sudah menjadi Panglima Kostrad dan kemudian saya diangkat menjadi Asisten VII (Bidang Perbendaharaan) Men/Pangad. Intensitas hubungan kami pada waktu itu memang meningkat.
Pada masa konfrontasi dengan Malaysia, dimana beliau menjadi komandannya, hubungan saya dengan Pak Harto menjadi lebih sering lagi. Bidang tugas saya meliputi pengaturan segala hal yang berkenaan dengan pembiayaan, perlengkapan dan semua yang berhubungan dengan keperluan pasukan, baik yang di Kalimantan maupun Sumatera. Waktu itu kami bersama Jenderal Achmad Yani, Men/Pangad/Kaskoti, sering berkeliling daerah di seluruh Indonesia untuk memeriksa kesiapan di lapangan dalam rangka konfrontasi tersebut.
Tiga hari setibanya kami dari suatu perjalanan keliling itulah meletus peristiwa G-30-S/PKI; Pak Yani gugur ditembak pemberontak. Pada hari itu juga saya: dipanggil Pak Harto untuk datang menghadap beliau di Kostrad. Keadaan memang sangat ruwet, karena kami belum mengetahui siapa yang PKI dan siapa yang bukan. Pada mulanya kami hanya melihat dari sudut pemberontakannya saja; menurut perkiraan kami, peristiwa tersebut akan dapat dengan cepat ditumpas. Tetapi ternyata masalah tersebut sangat kompleks, karena kami harus berhadapan dengan sikap Bung Karno dan militer yang berhaluan PKI dan seluruh slag orde PKI.
Dalam menghadapi pemberontakan PKI itu, Pak Harto menunjukkan sifatnya yang tegas, cepat dan gesit tetapi penuh dengan perhitungan yang matang. Melalui peristiwa-peristiwa itulah saya baru dapat memahami pendirian dan sifat beliau. Ketika G-30-S/ PKI meletus, Pak Harto dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah perbuatan Untung yang PKI dan harus ditumpas. Padahal kami semua masih ragu, karena kami semua belum mengetahui dengan pasti siapa kawan dan siapa lawan, termasuk di kalangan ABRI sendiri. Disamping itu kewibawaan Bung Karno juga masih sangat besar. Tetapi justru karena sikap Pak Harto yang tegas dan tidak ragu-ragu dalam menghadapi masalah tersebut, korban yang lebih banyak dapat dihindarkan.
Beliau tidak pernah terpengaruh oleh bermacam-macam desakan dari. berbagai kelompok, baik yang rasional ataupun yang irrasional. Pak Harto tetap pada pendirian beliau dalam menyelesaikan masalah PKI dan Bung Karno. Dalam hal yang terakhir ini beliau bertindak dengan bijaksana dengan memegang prinsip mikul dhuwur mendhemjero. Tanpa ragu sedikitpun, dengan Surat Perintah 11 Maret 1966, PKI beliau bubarkan. Padahal waktu itu jumlah kekuatan PKI lebih kurang enam juta orang ditambah simpatisannya sebanyak kurang lebih 20 juta orang, seperti yang pernah dikemukakan Sekretaris Jenderal PKI, Aidit, dalam salah satu pidatonya.
Mengenai masalah Bung Karno, sejak semula beliau berpendirian tidak akan bertindak inkonstitusional, dengan pegangan sabda pandita ratu, yang artinya bahwa raja itu tidak boleh dilawan dan suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti yang artinya, semua yang jelek itu pada akhirnya akan hancur oleh kebaikan. Prinsip inilah yang mungkin memberikan kesan kelambanan beliau dalam menghadapi situasi yang membuat banyak pihak menjadi tidak sabar. Tetapi akhirnya beliau memutuskan untuk bertindak dengan penuh kebijaksanaan, yaitu berusaha meyakinkan Bung Karno bahwa dibelakang G-30-S adalah PKI, karena itu PKI harus segera dibubarkan. Namun Bung Karno tetap tidak mau membubarkan PKI. Karena sikap Bung Karno yang dengan tegas tidak bersedia membubarkan PKI, sedangkan jalan penyelesaian peristiwa G-30-S/ PKI adalah dengan membubarkan PKI, akhirnya dicari jalan meyakinkan Bung Karno melalui kawan-kawan dekat beliau, yaitu Pak Dasaad (masih paman saya). Pak Dasaad akhirnya dibantu oleh Hasyim Ning, yang kebetulan adalah juga ternan dekat Bung Karno. Jadi kedua orang ini merupakan penghubung Pak Harto dengan Bung Karno dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Nampaknya pembicaraan diantara mereka, yang memakan waktu hampir dua minggu itu, mungkin merupakan salah satu sebab keluarnya Supersemar.
Di sinilah saya melihat ketegasan dan sikap kehati-hatian beliau yang dapat mencegah bangsa kita jatuh dalam kemelut perang saudani. Malam sesudah diterimanya Supersemar, Pak Harto memanggil semua panglima angkatan dan beberapa orang perwira tinggi lainnya, termasuk saya. Kemudian Pak Harto memerintahkan memanggil pula Front Pancasila dan kesatuan-kesatuan aksi. Di situ, atas perintah Pak Harto, kami memberikan briefing kepada mereka dan memutuskan untuk mengadakan pawai besar-besaran, untuk mendukung pembubaran PKI, esok harinya.
Selama bulan Maret itu keadaan memang sangat kacau. Meskipun PKI sudah berhasil dibubarkan tetapi keadaan masih jauh dari tenang, karena PKI itu telah berhasil menyusup ke mana-mana. Barisan Sukarno, pasukan ASU atau Ali-Surahman dan kelompok kelompok lain suah menyatu dengan gerakan PKI, sehingga semuanya bersemboyan “pejah gesang nderek Bung Karno”. Dalam menghadapi masalah ini, prinsip Pak Harto tetap kokoh, yaitu semua harus diselesaikan secara konstitusional. Itu sebabnya beliau mengembalikan masalah tersebut kepada DPR. DPR, yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Sjaichu, mengeluarkan resolusi untuk mengadakan Sidang Umum IV MPRS. Ini terlaksana pada bulan Juni 1966.
Dalam sidangnya yang keempat ini, MPRS mengambil beberapa keputusan penting. Antara lain Supersemar dan pembubaran PKI dijadikan Tap MPRS. Bung Karno juga diminta untuk memberikan penjelasan, tetapi tidak dapat datang dan hanya mengirimkan penjelasan yang tidak dapat diterima oleh MPRS. Keputusan terpenting yang diambil dalam sidang tersebut adalah menetapkan Pak Harto sebagai Ketua Presidium Kabinet yang akan membentuk kabinet bersama dengan Presiden Soekarno. Sebelum hal ini dilaksanakan, pemerintah telah mengamankan beberapa orang menteri yang berindikasi terlibat PKI.
Dengan terbentuknya kabinet baru yang dibentuk oleh Jenderal Soeharto dan disetujui oleh Presiden Soekarno, masyarakat mengharapkan bahwa keadaan akan segera pulih kembali. Harapan ini tidak terpenuhi, karena apa yang terjadi kemudian adalah dualisme dalam kepemimpinan kabinet, sehingga para menteri dan masyarakat menjadi bingung. Sampai sejauh ini Pak Harto masih tetap berpegang pada prinsip yang tidak mau mengganggu Bung Karno, tetapi akan tetap berjalan atas landasan konstitusional.
Prinsip beliau yang seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan DPR-GR meminta MPRS untuk kembali bersidang memecahkan masalah ini. Suasana menjadi sangat genting, karena menjelang sidang tersebut, tersiar berita bahwa MPRS akan diserbu oleh beberapa pasukan. Tetapi akhirnya keadaan dapat diatasi. Sidang Istimewa MPRS yang diadakan pada bulan Juli tahun 1967 itu, memutuskan untuk menonaktifkan Bung Karno dan mengangkat Pak Harto sebagai Pejabat Presiden. Tetapi dualisme politik masih tetap terjadi karena Presiden yang non-aktif masih mempunyai pengaruh yang besar, sementara pejabat Presiden mempunyai kekuasaan penuh. Konflik situasi yang hangat ini harus segera diakhiri. Akhirnya MPRS memberhentikan Bung Karno karena pertanggungjawabannya tidak dapat diterima; MPRS ketika itu juga mengangkat Pak Harto sebagai Presiden penuh. Barulah ketegangan situasi dapat diredakan. Seluruh kabinet diganti pada tahun 1968 dengan tugas antara lain, menjamin ketertiban dan keamanan, melaksanakan pembangunan dan pemilihan umum.
Di sinilah saya melihat konsistensi beliau dalam menangani suatu masalah, tetap berpegang pada prinsip yang konstitutional serta menentukan langkah dengan sangat hati-hati. Langkahlangkah inilah yang kadang-kadang memberikan kesan tidak tegas. Tetapi justru tindakan beliau yang seperti itulah, menurut pendapat saya, yang menyelamatkan bangsa dari kehancuran, yang mungkin saja terjadi bila beliau salah langkah.
Konsistensi Pak Harto pada prinsip yang telah beliau tentukan juga nampak jelas pada waktu saya menjadi Koordinator Staf Pribadi beliau pada tahun 1966. Staf pribadi tersebut meliputi staf ahli polltik, yang anggotanya antara lain adalah Pak Sarbini, Pak Fuad Hassan dan lain-lain; staf ahli ekonomi terdiri atas Prof. Widjojo, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, dan Sadli. Sedangkan staf ahli militer antara lain adalah Kolonel Yoga Sugomo, Kolonel Slamet Danudirdjo, Letnan Kolonel Ali Moertopo dan saya sebagai Koodinator, berpangkat brigadir jenderal. Sebagai Koordinator Staf Pribadi, saya mempunyai kesempatan untuk sering berhubungan dengan beliau. Di sinilah saya mengetahui bahwa beliau sangat memegang teguh segala hal yang telah beliau gariskan, sehingga amat sukar atau hampir tidak pernah terjadi bahwa beliau melakukan penyimpangan dari sesuatu yang sudah menjadi keputusan beliau.
Dari Koordinator Staf Pribadi, saya diangkat menjadi Sekretaris Negara. Pengangkatan ini terjadi beberapa hari sebelum beliau: diangkat menjadi Presiden. Jabatan ini saya pegang selama empat tahun dan pada tahun 1972 saya ditunjuk menjadi Dubes di Belanda. Sesudah itu selama satu tahun saya menjadi anggota DPA dan kemudian pada tahun 1977 saya menjadi Wakil Ketua DPA. Ketika pada tahun 1978, dalam Sidang Umum MPR, terjadi semacam gejolak sehingga PPP melakukan walk out, Pak Harto dengan risiko yang amat besar mengangkat saya menjadi Menteri Agama untuk membantu beliau melicinkan keadaan.
Mengapa tindakan Pak Harto mengandung risiko yang besar? Sebab, semua orang tahu bahwa saya ini bukan ahli agama, bukan kyai, bukan pula ulama apalagi sarjana agama. Walaupun demikian saya diangkat menjadi Menteri Agama. Di sinilah kembali saya lihat bahwa Pak Harto adalah seorang yang pantang mundur dalam mengambil sesuatu putusan, sekalipun yang berisiko tinggi, asalkan menurut perhitungan beliau dapat menanggulangi suatu masalah. Pengabdian saya yang terakhir pada negara adalah sebagai Menko Kesra dari 1983-1988.
Konsistensi beliau pada prinsip yang seakan tak pernah tergoyahkan itu bukanberarti bahwa Pak Harto tidak dapat bersikap terbuka dan demokratis. Beliau adalah seorang yang mau mendengarkan saran atau usul yang dikemukakan oleh pembantu beliau, paling tidak itulah yang saya alami sendiri. Sikap beliau yang seperti ini saya ketahui ketika saya menjadi Menteri Agama. Dalam suatu pembicaraan, kami membahas masalah umat Islam yang selalu merasa dicurigai dan dipojokkan terus. Menurut saya, hal ini tidak dapat terus berlangsung. Jalan pemecahannya adalah kita harus mencari titik temu antara pemerintah dan umat Islam.
Dalam kerangka inilah saya mengusulkan kepada beliau agar umat Islam diberikan kebebasan untuk berdakwah, karena selama ini dakwah seakan-akan dikungkung. Disamping itu saya juga mengusulkah supaya televisi mengadakan azan pada waktu Magrib dan Isya’. Masalah aliran kepercayaan juga saya bicarakan dengan beliau karena masalah ini cukup menjadi ganjalan bagi umat Islam. Beliau mengatakan bahwa aliran kepercayaan itu adalah kebudayaan. Kalau·demikian halnya, maka aliran kepercayaan ini saya kembalikan kepada Departemen P dan K; beliaupun setuju. Akhirnya umat Islam menjadi lega. Pada umumnya semua langkah yang saya lakukan ternyata mendapat persetujuan dan dukungan beliau.
·Persoalan lain adalah mengenai Pancasila yang tadinya merupakan anjalan bagi umat Islam, tetapi syukur alhamdulillah hal ini bisa·teratasi. Saya mengatakan pada beliau bahwa umat Islam itu hendaknya diberi pujian sedikit, dihargai sedikit. Saya ajukan kepada beliau bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai hasil pengorbanan umat Islam. Kita semua tahu bahwa Pancasila itu pada mulanya diajukan oleh kelompok sekuler dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara yang akan merdeka itu. Tetapi di segi lain, golongan Islam menghendaki suatu negara Islam.
Karena masalah ini, kita menghadapi deadlock. Akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang memutuskan bahwa ide negara Islam dicoret dan diterimalah Pancasila sebagai ideologi negara, dengan penambahan dalam sila pertama dari Pancasila yang berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”. Inilah yang akhirnya dinamakan Piagam Jakarta sebagai konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945. Tetapi pada sore hari sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 (diproklamasikannya kemerdekaan), datanglah utusan golongan non-Islam kepada Bung Hatta, dan menyatakan keberatan mereka terhadap tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu. Mereka menyatakan bila Piagam Jakarta itu tidak dicoret, mereka akan memilih berada diluar kemerdekaan Indonesia.
Esok harinya tanggal l8 Agustus 1945, Bung Hatta memanggil empat orang wakil golongan Islam. Mereka itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Hasyim Asy’ari, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hassan. Bung Hatta bertanya pada mereka: “Bagaimana, apakah kemerdekaan kita ini bersatu apa tidak?”. “Bersatu”, jawab keempat tokoh tersebut. “Nah, kalau begitu carilah katakata lain, jangan dipakai tujuh kata dalam sila pertama dari Piagam Jakarta ini”, kata Bung Hatta. Akhirnya atas nama umat Islam, kata-kata dalam sila pertama pada Piagam Jakarta dicoret oleh mereka dan diganti dengan tiga kata: Ke-Tuhanan Yang Mana Esa.
Nah, dua kali pencoretan keinginan umat Islam demi kemerdekaan dan persatuan, bukankah hal ini merupakan pula pengorbanan umat Islam? Pengorbanan mereka inilah yang mesti kita hargai. Pendapat saya ini dapat diterima oleh Pak Harto. Sebagai realisasi dari persetujuan Presiden itu, saya berpidato di tempat Rais Aam NU/PPP, Kyai Bisri, di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, pada tangga l8 Juli 1978. Dimuka para santri tersebut, saya mengatakan bahwa arsitek Pancasila itu diantaranya adalah Kyai Wahid Hasyim menantu Rois Aam ini. Jadi kalau dimakamnya beliau mendengar bahwa ada orang Islam, apalagi NU, anti Pancasila, maka beliau tentu akan menangis.
Sesudah saya selesai berbicara, Kyai Bisri berkata dalam bahasa Jawa: ”Mbah iki wis sepuh, sing teko ngomong Pancasila kujur, yo kujur; mbah ora ngerti sing Wahid Hasyim iku arsiteke Pancasila. Nek ngono mbah arep ngomong” (Mbah ini sudah tua, yang datang mengatakan bahwa Pancasila itu kafir, ya setuju; mbah tidak mengerti bahwa Wahid Hasyim itu arsiteknya Pancasila. Kalau begitu mbah akan berbicara). Iapun terus berbicara di muka para santri; ”Saiki aku wis weruh sing jenenge Pancasila iku opo. Saiki, nek ono wong Jowo, nek ono wong Islam, ono wong NU anti Pancasila, iku yo anti karo aku. ‘(Sekarang saya sudah mengerti yang namanya Pancasila itu apa. Sekarang kalau ada orang Jawa, orang Islam, ada orang NU anti Pancasila, itu juga anti kepada saya). Sejak peristiwa itu, PPP kemudian menerima Pancasila yang diikuti oleh Muhammadiyah, semua organisasi Islam dan akhirnya HMI juga menerima. Nah, sekarang kita semua telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, sehingga tidak akan lagi terdapat alasan yang mempersoalkan Pancasila itu.
Untuk menghindarkan kecurigaan antara para umat yang beragama, saya mengusulkan kepada Pak Harto untuk membentuk Badan Musyawarah Antar Umat Beragama. Beliaupun menyetujui usul saya ini. Masalah ini memang dianggap penting oleh Pak Harto, karena sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memberikan suasana yang seharmonis mungkin bagi kehidupan semua agama yang berkembang di Indonesia ini. Akhirnya kita sekarang ini; telah menjadi bangsa dimana semua agama yang berkembang dapat hidup berdampingan secara damai.
Masalah lain yang cukup meruwetkan juga timbul, yaitu perayaan Natal Bersama. Saya membicarakan masalah ini dengan beliau. Beliau mengatakan: “Sudah, bagi dua saja”. Kemudian saya membuat peraturan bahwa Natal Bersama itu adalah untuk umat Kristen dan Katolik dalam pelaksanaan ibadahnya. Tetapi kalau seremonialnya, seperti makan-makan atau malam keseniannya, semua orang yang non-Kristen dapat saja menghadirinya. Sama saja bagi umat Islam juga demikian. Pada waktu shalat led, hanya rnereka yang beragarna Islam saja yang rnelakukannya. Kalau sudah di rumah, pintu terbuka bagi semua orang dengan tidak melihat beragama apa mereka. Masalah agama merupakan masalah yang sangat peka, tetapi berkat perhatian beliau yang sangat dalam mengenai masalah ini, akhirnya banyak negara yang memuji tentang kehidupan keagamaan kita.
Disarnping sikap keterbukaan dan ketegasan, yang beliau perlihatkan dalam menanggulangi beberapa masalah tersebut di atas, Pak Harto adalah seorang yang lembut kebapakan dan pengayom. Beliau juga selalu menerapkan cara tut wuri handayani terhadap para pembantu beliau. Selama saya menjadi pembantu beliau, baik ketika beliau rnasih seorang militer maupun seorang Kepala Negara dan Pemerintahan, sifat kebapakan dan ketegasannya itulah yang sangat mengesankan saya. Saya tidak pernah merasakan sifat yang memaksa dari beliau. Pak Harto selalu memberikan kebebasan kepada kami untuk bekerja dan mengembangkan gagasan-gagasan yang telah kami setujui bersama.
Bila timbul suatu masalah, beliau selalu menegur dan menasehati kami dengan cara yang halus. “Cara Jawa”, yang mesti kita pahami antara lain dengan memperhatikan mimik beliau dalam memberikan suatu reaksi. Mengapa, karena beliau tidak pernah rnengatakan “tidak” sekalipun untuk hal yang tidak beliau setujui. Jadi kita harus peka terhadap kehalusan beliau. Pada mulanya memang agak sukar bagi saya yang orang dari sebrang, tetapi akhirnya saya menjadi peka pula dalam melihat setiap reaksi beliau. Barangkali gabungan antara kelembutan dan ketegasan Pak Harto inilah yang merupakan kekuatan beliau dalam memimpin Indonesia selama lebih kurang 20 tahun (tahun 1988).
***
[1] H Alamsyah Ratu Perwiranegara, “Prinsipnya Tak Tergoyahkan”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 590-598.
[2] Letjen. TNI Purnawirawan; Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Pembangunan IV