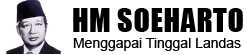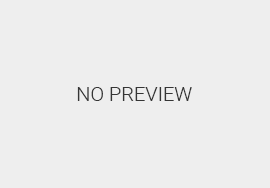Bung Karno Wafat
Bung Karno Wafat [1]
Sejak Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, lebih dari sepuluh kali saya bertemu dengan Presiden Soekarno. Di antaranya ada yang disaksikan oleh yang lain, tetapi selebihnya terjadi pertemuan empat mata. Saya sempat menganjurkan agar Bung Karno membubarkan PKI. Tetapi waktu itu Bung Karno menjawab, “Kalau PKI dibubarkan, akan hilang muka saya sebagai pimpinan dunia.” Dalam pada itu saya memandang lebih penting keutuhan nasional ketimbang kepentingan internasional.
Sejak awal 1968 Bung Karno berada dalam “karantina politik” dan tinggal di pavilyun Istana Bogar. Kemudian beliau minta pindah, dan kami setujui, ke peristirahatan “Hing Puri Bima Sakti” yang terletak di Batutulis, Bogor. Kepindahannya itu rupanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh lingkungan hidup yang lebih segar. Tetapi lalu beliau menulis surat kepada saya yang dibawa oleh Rachmawati (Soekarno), agar diizinkan pindah ke Jakarta.
Rachmawati datang di rumah kami di Jalan Cendana: Istri saya yang mula-mula menerimanya. Lalu dibawanya kepada saya. Sambil menyampaikan surat dari Bung Karno itu, Rachmawati menceritakan keadaan kesehatan ayahnya. Saya dengarkan kabar itu dengan penuh perhatian. Rupanya keadaan kesehatannya yang menyebabkan beliau ingin pindah ke Jakarta. Udara di Bogor mungkin tidak baik baginya.
Maka saya janjikan kepada Rachmawati untuk berusaha mengatur kepindahan Bung Karno. Mendengar ucapan saya begitu Rachma menunjukkan keterharuannya, matanya kelihatan berlinang. Memang saya menaruh perhatian dan simpati kepada Proklamator kita itu. Tetapi suasana politik memagarinya. Dan terutama kekerasan hatinya saja yang menyebabkan segala ini. Maka pindahlah Bung Karno pada permulaan 1969 ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto, yang sekarang jadi Museum Satria Mandala.
Saya perintahkan team dokter di bawah ketuanya, Prof. Dr. Mahar Mardjono, menjaganya. Benar, semasa itu Bung Karno diminta keterangan untuk keperluan Kopkamtib. Tetapi setelah saya ketahui bahwa sakitnya cukup serius, saya perintahkan untuk berhenti dengan pemeriksaan itu.
Waktu putrinya, Sukmawati, melangsungkan pernikahannya di rumah Ibu Fatmawati di Kebayoran Baru, beliau diperkenankan untuk pergi ke sana. Kesehatan beliau di bulan Februari 1970 itu kelihatan sekali menurun.
Tanggal 16 Juni 1970 saya terima kabar bahwa penyakit beliau tambah parah saja. Saya perintahkan kepada dokter-dokter untuk menjaganya baik-baik dan jika perlu membawanya ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Hari itu juga Bung Karno diangkut ke RSPAD Gatot Subroto dan mendapat perawatan intensif.
*
Waktu saya mendengar beliau meninggal pada tanggal 21 Juli 1970, cepat saya menjenguknya ke rumah sakit. Setelah itu barulah saya berpikir mengenai pemakamannya. Tetapi semua itu tidak mengejutkan dan tidak membingungkan saya, karena memang sudah ada rencana untuk menghormati Bung Karno sebagai Proklamator. Hanya waktu itu saya masih merasa perlu mendengar pendapat orang-orang lain dalam rangka mempraktekkan “mikul duwur mendem jero”, pegangan hidup saya itu.
Saya perintahkan untuk mengangkut jenazahnya ke Wisma Yaso. Lalu saya kumpulkan para pemimpin partai-partai. Saya sudah punya pikiran bahwa beliau harus kita hormati. Artinya, bangsa Indonesia harus memberikan penghormatan terakhir kepada beliau dengan melaksanakan upacara pemakaman kenegaraan. Kecurigaan bahwa beliau terlibat dalam G.30.S/PKI sudah bisa dikesampingkan karena hal itu belum bisa dibuktikan.
Yang jelas, kita harus memberikan penghargaan atas jasa-jasa beliau sebagai pejuang yang luar biasa. Sejak dulu beliau adalah pejuang, perintis kemerdekaan. Dan sebagai Proklamator beliau tidak ada bandingannya.
Ternyata para pemimpin partai politik menyetujui pikiran saya, termasuk Bung Hatta yang juga saya minta pertimbangannya. Dengan spontan mereka menyatakan sangat menghargai sikap penghargaan saya kepadanya.
Maka keputusan pun saya ambil: pemakaman dilaksanakan dengan upacara kenegaraan. Kemudian timbul masalah: di mana pemakaman itu harus kita lakukan? Kami ingat akan wasiatnya. Kami ingat bahwa permintaan almarhum semasa hidupnya, jenazahnya hendaknya dimakamkan di suatu tempat di mana rakyat dapat datang seperti dipesankan kepada Dewi. Pesannya kepada Hartini pun begitu. Tetapi keluarga yang lain mempunyai. pandangan yang lain lagi. Ternyata keinginan keluarga Bung Karno yang banyak itu berbeda-beda.
Andaikata kita serahkan kepada keluarga besar yang ditinggalkannya, maka saya melihatnya bakal repot.
Maka kemudian saya memutuskan dengan satu pegangan yang saya jadikan titik tolak, yakni bahwa Bung Karno sewaktu hidupnya sangat mencintai ibunya. Beliau sangat menghormatinya. Kalau beliau akan bepergian ke tempat jauh, ke mana pun, beliau sungkem dahulu, meminta doa restu kepada ibunya. Setelah itu barulah beliau berangkat. Sekalipun beliau adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, terpelajar, beliau toh tetap hormat kepada ibunya. Ini merupakan teladan bagi generasi yang akan datang.
Melihat kebiasaan Bung Karno begitu, maka saya tetapkan bahwa alangkah baiknya kalau Bung Karno dimakamkan di dekat makam ibunya, di Blitar. Inilah alasan saya dan keputusan saya berkenaan dengan pemakaman Proklamator kita itu.
Ada terdengar familinya yang protes. Demikian juga di antara istri-istrinya dan di antara putra-putrinya. Tetapi kalau saya turuti keinginan mereka, saya pikir, takkan ada penyelesaian. Maka saya ambil oper seperti demikian. Soal nanti, terserah. Yang jelas kemudian segalanya berjalan dengan baik.
Dalam rangka “mikul dhuwur mendhem jero”, kita buktikan Iagi dengan keputusan saya berikutnya. Kita pugar makam Bung Karno itu sehingga merupakan makam yang representatif, yang pantas sebagai makam pahlawan yang dihormati oleh bangsanya. Bukti yang lain lagi adalah bahwa sampai sekarang makam itu dihormati orang. Banyak yang ziarah ke sana.
Di tahun 1980 kita dirikan patung kedua Proklamator kita; Bung Karno dan Bung Hatta, di halaman bekas tempat dikumandangkannya Proklamasi. Di tahun 1985 saya tetapkan nama untuk bandar udara di Cengkareng, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menghormati kedua Proklamator kemerdekaan kita. Di tahun 1986 kita tetapkan beliau bersama Bung Hatta sebagai Pahlawan Proklamator.
*
Berpikir mengenai Bung Karno, selalu saya bertolak dari ingatan bahwa manusia memang tidak ada yang sempurna. Jangankan manusia biasa, nabi pun bisa khilaf. Sehubungan dengan ini saya melihat Bung Karno, sampai di mana pengorbanannya untuk negara dan bangsa. Jelas, pengorbanannya amat besar, sampai kita, sebagai bangsa, bisa merdeka. Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai menjadi proklamator bersama-sama dengan Bung Hatta. Ini merupakan suatu jasa seorang pejuang, patriot yang harus kita hargai.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia merdeka, kita pun membuat kesalahan. Bukan Bung Karno saja. Tetapi kesalahan Bung Karno, jelas tidak sampai menjerumuskan bangsa maupun rakyatnya. Mungkin semata karena terdorong oleh suatu ambisi besar, maka kesalahan itu dibuatnya. Ambisi besarnya itu adalah ambisi untuk menjadi pemimpin dunia. Untuk itu tentunya Bung Karno harus bermodal, dan modalnya adalah yang ada pada bangsanya. Jadi, modalnya itu adalah kekuatan nasional.
Dalam menuju cita-cita Bung Karno, ada kekuatan yang mengetahuinya dan lalu membonceng, yaitu PKI. Ancaman pihak yang membonceng terlupakan oleh Bung Karno. Yang salah adalah orangorang sekitarnya. Mereka kurang waspada di dalam memberikan peringatan bahwa PKI membonceng, menunggangi Bung Karno sewaktu Bung Karno hendak mencapai tujuannya.
Sementara cita-cita Bung Karno untuk menjadi pemimpin dunia belum tercapai, PKI –setelah kuat– mengadakan kup. Melihat itu semua, apakah kita bisa menimpakan kesalahan itu kepada Bung Karno? Memang ada kesalahannya, yaitu memberi kesempatan kepada PKI. Tetapi kesalahan Bung Karno itu tidak sampai terbukti bahwa Indonesia menjadi negara komunis. Tidak sampai begitu.
Bung Karno memang keras dalam pendirian dan teguh dalam mempertahankan konsepsinya ialah NASAKOM. Ingin mempersatukan agama dan komunis dalam Pancasila. Sesuatu yang tidak mungkin. Kenyataannya memang tidak berhasil. Dalam kesempatan berdialog pada tahun 1958 di Semarang, Bung Karno telah menegaskan kepada saya, ingin menjadikan PKI menjadi PKI Pancasila. Saya sempat menanyakan, apakah mungkin. Bung Karno bertekad membuktikan. Karena itulah lahir konsepsi Nasakom. Dalam sejarah ternyata yang berhasil justru PKI, dapat memperkuat diri dan kemudian mengkhianati Pancasila. Bung Karno marah bila disinggung mengenai konsepsi Nasakom, apalagi membubarkan PKI, walaupun itu menjadi tuntutan rakyat. Bung Karno tetap pada pendiriannya, tetapi belum menemukan jalan pemecahan keadaan yang diakibatkan ulah PKI itu.
Menghadapi pengalaman seperti ini saya berpegang kepada falsafah Jawa saya “Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti” (Keberanian yang emosional akan tunduk pada ketenangan dan kesabaran).
Nah, ingat pada periode 1965-1967, saya pernah berkata: kalau orang mencak-mencak dihadapi dengan kekerasan, maka ia akan menjadi tambah marah. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, dengan sikap yang menunjukkan penghargaan kepadanya, maka ia akan luluh dengan sendirinya. Lahirnya “Supersemar” itu adalah hasil pengambilan sikap seperti itu. Bukan dengan paksaan. Bukan karena ancaman saya. Sama sekali tidak.
Waktu itu saya sudah yakin, bahwa Bung Karno sudah merasa tidak mampu, dan beliau mengetahui, bahwa pada saya ada kemampuan, tetapi tidak sesuai dengan Bung Karno. Dialog terjadi sehingga akhirnya beliau percaya, bahwa saya tidak akan menghancurkan Pancasila dan tidak akan menyengsarakan beliau. Saya kira, setelah keyakinan beliau demikian halnya, maka lahirlah “Surat Perintah 11 Maret”. Ingatlah akan dialog saya dengannya mulai tanggal 2 Oktober 1965 sampai dengan 11 Maret 1966.
Saya merenung, ingat akan pengalaman-pengalaman saya dengan Bung Karno, akan jawaban saya kepada beliau “mau mikul dhuwur mendhem jero”. Juga ingat akan sikap saya terhadapnya.
Boleh jadi ada orang yang bertanya, apakah sikap saya itu boleh ditiru oleh orang lain? Apakah saya: membenarkan seseorang yang patuh kepada atasan, tetapi sebagai pejuang bisa mengatakan “tidak”? Tentu saja, dengan sendirinya saya bisa membenarkannya.
Sebagai seorang militer kita harus patuh, tetapi sebagai seorang pejuang jangan “ya-ya” saja. Sebab, bila akibatnya tidak menyenangkan, bukan hanya yang diperintah bisa menjadi korban, bukan pula hanya bersama dengan yang memerintah bisa menjadi korban, melainkan seluruh bangsa bisa menjadi korban. Karena itu, saya selalu bertanya, “Apa pendapatmu ?” dan selalu mau mendengar jawaban atas pertanyaan saya itu. Kalau pendapatmu baik, OK.
Sebagai militer pun sebetulnya harus demikian, dalam pengertian, andaikata seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu tetapi terasa olehnya bertentangan dengan akal sehatnya, ia pun harus menyampaikan sarannya. Tetapi kalau sarannya itu ditolak oleh atasannya, ia tetap harus menerima untuk menjalankannya. Namun, dengan begitu, yang bersangkutan sudah menyampaikan pendapatnya. Begitulah hendaknya sebagai militer.
Tetapi sebagai pejuang, itu lebih luas lagi. Karena pejuang itu tidak hanya berhubungan dengan soal antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ia harus memikirkan keselamatan negara dan nasib bangsa.
***
[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 244-249.