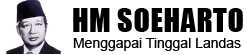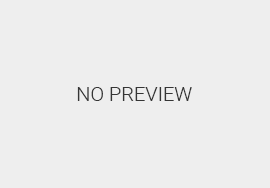Hidup dalam Pergesekan Sejarah Bangsa
BIOGRAFI PRESIDEN SOEHARTO (2)
(Hidup dalam Pergesekan Sejarah Bangsa)1
Sebelum akhirnya takdir sejarah mengantarkannya menjadi Presiden, hidup Soeharto muda selalu berkaitan erat dengan puncak-puncak peristiwa penting jatuh bangunnya negara dan bangsa Indonesia. Ia berkontribusi dalam perlucutan tentara Jepang dan persenjataannya menjadi bekal bagi pengembangan TNI. Ia juga menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kudeta Mayor Soedarsono dan kelompok Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1946. Melakukan netralisasi satuan-satuan pendukung FDR/PKI dalam pemberontakan Madiun. Merupakan aktor utama pengembalian kedaulatan Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 yang legendaris. Serangan itu menentukan diplomasi Indonesia di Panggung internasional sehingga diakui sebagai negara berdaulat. Pak Harto, yang kala itu berpangkat Mayjen, juga menajdi Panglima Komando Mandala dalam rangka pengembalian Irian Jaya ke pangkuan Indonesia. Tak kalah penting juga merupakan aktor utama gagalnya kudeta PKI tahun 1965 pada saat komunisme internasional pada puncak kejayaan. Setelahnya, sisa hidupnya dikontribusikan untuk memperjuangkan terwujudnya tinggal landas (menjadikan Indonesia setara negara maju, berdaulat secara ekonomi, politik, hankam dan sosial budaya) melalui sekenario dua kali Pembangunan Jangka Panjang (PJP).
PERLUCUTAN TENTARA JEPANG
Berita proklamasi 17 Agustus 1945 yang didapatnya melalui koran Matahari terbitan Yogya pada tanggal 19 Agustus 1945, bagi Soeharto Muda merupakan sebuah panggilan jiwa untuk mendedikasikan dirinya dalam pengabdian kebangsaan. Berita itu telah menjadi tonggak awal bagi dirinya untuk secara formal terlibat dalam menentukan jatuh bangunnya Republik Indonesia pada waktu-waktu berikutnya.
Koran itu memberitakan telah diproklamasikannya Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden. Koran itu juga memberitakan seruan Sultan Hamengku Buwono IX agar rakyat Indonesia, tanpa terkecuali harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk mendedikasikan dirinya dalam menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.
Ia berinisiatif mengumpulkan teman-temannya bekas tentara PETA dan pertama-tama menemui Oni Sastroatmojo, seorang Komandan Kompi Polisi Istimewa, untuk bersama-sama mengumpulkan bekas-bekas Chudancho dan Shodancho. Ia kemudian membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) di daerah Sentul dan terpilih sebagai wakil ketua. Umar Slamet, seorang teman dekatnya menjadi ketua. Inisiatif ini seiring seruan Presiden Soekarno agar bekas PETA, Heiho, Keigun dan KNIL dan para pemuda untuk mendirikan BKR-BKR di daerahnya masing-masing. Posisi sebagai wakil ketua BKR merupakan “tangga pertama pada zaman baru” yang akan menaikkannya pada “tangga-tangga karir selanjutnya”.
Pada tanggal 7 Oktober 1945, tepatnya jam 10.30, ia berhasil memimpin pasukannya turut menaklukkan markas tentara Jepang di Kotabaru. Pada saat itu usia Pak Harto masih 24 tahun dan harus mengambil beban tanggung jawab kepemimpinan pasukannya karena komandan sedang menjalani tugas dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Madiun. Selanjutnya memimpin pasukannya dalam “Pertempuran Lima Hari” di front Pandeanlamper Semarang. Prestasi kemiliterannya terus berlanjut dengan turut serta menaklukkan tentara Jepang di lapangan terbang Maguwo. Pertempuran-pertempuran itu selain merupakan pengambilalihan kendali Militer Jepang —yang sudah kalah dalam Perang Dunia II— atas wilayah Republik Indonesia, juga merupakan konsolidasi kekuatan persenjataan BKR. Pasukan Seharto muda dalam pertempuran di Maguwo itu dapat merebut beberapa buah pesawat yang kelak menjadi modal dalam pembentukan Angkatan Udara Republik Indonesia.
Selain peran perlucutan senjata tentara Jepang, Soeharto muda juga turut serta memukul mundur majunya pasukan sekutu dari Magelang menuju Ambarawa. Ia memimpin Batalyon X dari sektor Yogyakarta dengan kekuatan empat kompi. Pasukannya menusuk Ambarawa melalui Banyubiru dalam sebuah pertempuran “Palagan Ambarawa” yang bersejarah. Pertempuran itu dipimpin langsung Kolonel Sudirman yang kala itu hendak dilantik sebagai Panglima Besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan strategi “supit udang”. Pasukan Soeharto muda diberi tugas menduduki Banyubiru untuk pengamanan lambung pasukan induk pejuang yang memasuki Ambarawa. Setelah Magrib ia masuk Banyubiru dan memukul mundur kekuatan Sekutu menuju Ambarawa serta menempatkan pasukan yang baru menang itu jauh di garis depan (front line) pertempuran. Penempatan pasukan itu menunjukkan kejeniusan strategi perang komandan muda untuk mengelabuhi serangan balik pasukan sekutu yang lebih lengkap dalam teknologi persenjataan modern. Malam harinya, semalam suntuk Banyubiru dihujani keganasan meriam sekutu. Namun pasukannya terlindung karena berada dalam zona jauh di depan dan Banyubiru tetap tertutup bagi sekutu dalam menusuk lambung pasukan induk pejuang.
Keberhasilan Soeharto muda di berbagai front ini mengundang apresiasi para petinggi TKR, seperti Kolonel Gatot Soebroto dan Kolonel Soedirman. Prestasi ini kelak mengantarkannya diangkat sebagai Komandan Brigade X Ibukota Yogyakarta, dengan pangkat Letkol, dalam struktur TNI yang baru direorganisasi oleh Jenderal Soedirman.
PENYELAMATAN PRESIDEN SOEKARNO DARI KUDETA
Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 September 1945, Van Mook, pimpinan NICA (Netherland Indies Civil Administration/pemerintahan sipil Hindia Belanda), menyatakan tidak akan berunding dengan Soekarno yang dianggapnya bekerjasama dengan Jepang. NICA membawa misi pembentukan negara persemakmuran dengan keanggotaan kerajaan Belanda dan Indonesia yang diketuai Ratu Belanda.
Pada tanggal 4 Januari 1946, seiring tekanan sekutu mempersempit ruang gerak pejuang, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pindah ke Yogyakarta, sekaligus menandai perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Perpindahan Ibukota semakin menambah tekanan kepada Yogyakarta sebagai simbol eksistensi pemerintah Republik Indonesia yang di dalamnya syarat dengan tekanan politis maupun militer, baik dari dalam maupun luar (Sekutu dan Belanda). Sementara itu, Letkol Soeharto, atas prestasinya di berbagai front pertempuran, dipercaya sebagai Komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro Yogyakarta yang ternyata kemudian menjadi Ibu Kota.
Untuk mengantisipasi sikap Belanda para pemimpin Indonesia melakukan perubahan sistem kabinet dari presidensil menjadi kabinet parlementer dan Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sjahrir merupakan tokoh sosialis yang dipandang tepat menjalankan diplomasi dengan Belanda karena bersamaan dengan momentum kebangkitan Partai Sosisialis di Belanda.
Proses diplomasi Sjahrir dinilai cenderung kooperatif dengan agenda Belanda untuk pembentukan negara persemakmuran. Puncaknya ketika Sjahrir mengirim surat rahasia (usulan balasan) kepada Van Mook yang isinya secara samar-samar menerima gagasan Van Mook. Sebagaimana diakui Van Mook —melalui kawatnya ke Den Haag—, Soekarno tidak menyetujui surat balasan itu. Walaupun menyatakan dukungan penuh kepada Sjahrir, pada tanggal 27 Juni 1946, Wakil Presiden Muhammad Hatta memaparkan isi surat balasan itu dalam pidato peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw, di alun-alun utara Yogyakarta, yang dihadiri khalayak luas dan Presiden Soekarno. Pada hari itu pula Perdana Menteri Sjahrir di culik oleh orang tidak dikenal di Solo.
Sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Juni 1946, Tan Malaka, Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri dan Sukarni sebagai tokoh kelompok Persatuan Perjuangan —sebuah sumber menyebutkan sebagai tokoh politik golongan Murba— ditangkap dengan tuduhan berencana menculik anggota-anggota kabinet Sjahrir II. Mereka tidak puas terhadap politik diplomasi Sjahrir dalam menghadapi Belanda. Kelompok ini mengklaim menginginkan kedaulatan RI secara penuh, sedangkan kabinet Sjahrir dianggap hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Pada saat penangkapan itu, kelompok milter yang sejalan dengan garis politik kelompok Persatuan Perjuangan belum ditangkap. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat dan mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan. Dalam momen inilah, Letkol Soeharto sebagai Komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro, pengendali Ibukota Yogyakarta, dihadapkan ujian politik dan militer.
Beberapa saat setelah pengumuman keadaan darurat, Letkol Soeharto didatangi ketua pemuda Pathuk bernama Sundjoyo di markasnya, Wiyoro Yogyakarta. Tanpa bukti tertulis, Sundjoyo mengaku sebagai utusan Istana dan membawa pesan agar Letkol Soeharto menangkap pimpinannya, Panglima Divisi Diponegoro, Mayor Jenderal Sudarsono. Mayor Jenderal Sudarsono diidentifikasi sebagai sayap militer kelompok Tan Malaka yang berencana melakukan kudeta.
Letkol Soeharto menghadapi situasi tarik ulur politik ini dengan tangkas. Ia mendudukkan penugasan itu dalam koridor konstitusional dan mengembalikan surat perintah dengan menyatakan bahwa hirarki perintah itu seharusnya melalui atasannya, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pengembalian surat itu disertai jaminan bahwa tidak ada gerakan militer yang membahayakan pemerintah (Presiden Soekarno). Atas sikap komandan muda itu, pembawa pesan melakukan faita comply bahwa Jenderal Sudirman juga terlibat dalam gerakan kudeta. Hal mana situasinya menambah keyakinan Letkol Soeharto bahwa perintah itu tidak benar karena tahu benar karakter Jenderal Sudirman. Atas penolakan itu Letkol Soeharto diberi julukan opsir koppig (keras kepala) oleh Presiden Soekarno, walaupun yang bersangkutan belum pernah saling ketemu.
Setelah mengembalikan surat perintah, Letkol Soeharto memenuhi janjinya, melakukan konsinyir resimen yang ia pimpin. Ia juga melapor kepada panglimanya, Mayor Jenderal Sudarsono tentang laskar-laskar dari biro perjuangan yang akan menangkapnya. Ia menyampaikan alasan apabila penangkapan itu terjadi, kehormatan Divisi Diponegoro akan tercoreng. Oleh karena itu ia meminta Mayor Jenderal Sudarsono bersedia konsinyir bersama pasukannya di Wiyoro dan permintaan itu benar-benar dipenuhi.
Sesaat setelah tiba di Wiyoro, Mayor Jenderal Sudarsono membuka surat telegram dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mayor Jenderal Sudarsono mengatakan kalau dirinya dipanggil menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat itu juga. Dengan alasan tersebut, Letkol Soeharto melepas Mayor Jenderal Sudarsono dengan pengawalan satu peleton pasukan berkendaraan truk. Namun berselang satu jam berikutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman menelpon dan memerintahkan agar menahan Mayor Jenderal Sudarsono di Wiyoro. Letkol Soeharto menyampaikan bahwa Mayor Jenderal Sudarsono sudah pergi untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menyerahkan kebijakan selanjutnya pada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Berdasarkan perbincangan telpon itu, Letkol Soeharto mengetahui secara pasti bahwa Panglima Besarnya Jenderal Sudirman, tidak terlibat dengan usaha coup yang dilakukan kelompok Tan Malaka maupun menyetujui gerakan Mayor Jenderal Sudarsono.
Tanggal 2 Juli 1946 tengah malam, Mayor Jenderal Sudarsono bersama politisi kelompok Persatuan Perjuangan —yang sebelumnya ditangkap dan ia bebaskan sendiri dari tahanan Wirogunan— datang lagi ke Wiyoro. Setibanya di Wiyoro, Mayor Jenderal Sudarsono mengatakan kepada Letkol Soeharto bahwa dirinya memperoleh perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk membuat surat kepada Presiden yang isinya “supaya pemerintahan sekarang dibubarkan dan diganti pemerintah baru”. Surat tersebut akan disampaikan keesokan harinya.
Pernyataan yang baru saja didengar itu melengkapi informasi yang harus dihimpun seputar keterlibatan Mayor Jenderal Sudarsono dalam aksi kudeta, setelah sebelumnya memperoleh kepastian Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak terlibat. Ia juga merasa akan ditipu oleh Mayor Jenderal Sudarsono dengan mengklaim tindakannya merupakan perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Atas pemetaan situasi yang dirasa cukup, Letkol Soeharto menyampaikan rencana Mayor Jenderal Sudarsono kepada pihak istana dan menyerahkan penangkapan kepada pihak istana. Letkol Soeharto juga menyampaikan jaminan keamanan di luar istana dan menjamin tidak akan ada gejolak dikalangan prajurit atas penangkapan Panglimanya itu.
Pagi hari tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono bersama kelompoknya menghadap Presiden Soekarno dan menyodorkan empat maklumat untuk ditandatangani presiden. Mereka menuntut Presiden Soekarno agar bersedia:
- Memberhentikan Kabinet Sjahrir II,
- Menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik,
- Mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka dan beranggotakan Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Buntaran Martoatmodjo, Budiarto Martoatmodjo, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, Gatot, dan Iwa Kusuma Sumantri.
- Mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat.
Tuntutan itu secara jelas tidak hanya meminta pergantian Kabinet Sjahrir, akan tetapi juga meminta penyerahan kepemimpinan Presiden yang meliputi kepemimpinan politik, sosial dan ekonomi. Presiden Soekarno sudah mengetahui rencana tersebut berkat laporan Letkol Soeharto. Aparat keamanan istana sudah berjaga-jaga dan dengan mudah melakukan penangkapan terhadap Mayor Jenderal Sudarsono beserta kelompoknya. Penangkapan itu tanpa gejolak karena pasukan di konsinyir Letkol Soeharto. Pada hari itu pula upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah dengan sendirinya berakhir tanpa pertumpahan darah. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum 2 sampai 3 tahun, sedangkan Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara. Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1948, seluruh tahanan dibebaskan melalui pemberian grasi presiden.
Apabila dicermati Letkol Soeharto yang kala itu masih berusia 25 tahun merupakan aktor penting kegagalan kudeta pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia, karena:
- Kebanyakan analisis atau pengamat hanya memfokuskan penolakan perintah Presiden oleh Letkol Soeharto sebagai pembangkangan sehingga memperoleh julukan sebagai perwira muda koppig. Pengembalian surat perintah pada dasarnya dilatarbelakangi semata-mata pertimbangan normatif seorang komandan muda lugu untuk tidak menyalahi hirarki kemiliteran. Bahwa sebuah operasi militer harus merupakan kebijakan dan perintah dari hirarki yang lebih tinggi dan bukan oleh perintah komponen-komponen di luarnya. Dalam usia muda itu Letkol Soeharto sudah terbentuk sebagai pemimpin yang memiliki visi constitutionalized (taat hukum) bahwa segala tindakannya harus didasarkan pada koridor peraturan yang berlaku.
- Terlepas adanya alasan normatif, apabila perintah penangkapan itu dilaksanakan dengan serta merta —dimana tindakan penangkapan Panglima Divisi dilakukan oleh bawahanya sendiri— kemungkinan dapat menimbulkan komplikasi dalam tubuh ketentaraan RI, berupa konfrontasi yang tajam antar satuan militer yang pro dan kontra penangkapan. Hal itu kontra produktif dengan upaya konsolidasi semua potensi ketentaraan dalam menghadapi Sekutu. Apalagi pada saat perintah itu diberikan, tampaknya Letkol Soeharto belum yakin betul bahwa Panglima Divisinya terlibat kudeta. Ia bahkan tampak kawatir, perintah itu merupakan buah permainan kelompok-kelompok politik, yang apabila dipenuhi akan merusak soliditas TKR yang sedang berkonsentrasi melawan sekutu.
- Walaupun mengembalikan surat perintah, tindakan Letkol Soeharto memberikan jaminan keamanan Ibukota —dari gerakan militer atau coup yang membahayakan pemerintah— dengan sendirinya telah menutup peluang terjadinya kudeta. Jaminan itu diberikan bukannya tanpa alasan kuat, mengingat Resimen 22 yang dipimpinnya merupakan resimen terkuat dengan persenjataan paling lengkap dan merupakan kekuatan inti Divisi Diponegoro. Tanpa keterlibatan Resimen 22, Divisi Diponegoro tidak akan dapat digerakkan untuk melakukan kudeta oleh siapapun, termasuk oleh Panglima Divisinya sendiri, Mayor Jenderal Sudarsono. Jaminan itu diberikan dengan keyakinan penuh bahwa dirinya bisa memenuhinya dan mengendalikan keadaan.
- Langkah konsinyir yang dilakukan Letkol Soeharto selain untuk memastikan Resimen 22 dalam kendali sepenuhnya, juga untuk melokalisir dan mengontrol pergerakan Mayor Jenderal Sudarsono. Pengawalan satu peleton pasukan menyertai Mayor Jenderal Sudarsono ketika meninggalkan Wiyoro dapat diartikan sebagi pengawalan keamanan sekaligus “karantina halus” untuk membatasi ruang gerak Panglima Divisinya itu. Konsinyir pasukan dan “karantina halus” merupakan antisipasi jika sewaktu-waktu mendapat perintah dari Jenderal Soedirman untuk melaksanakan perintah Istana.
- Melalui dua langkah yang ditempuhnya —di satu sisi menolak menangkap Panglima Divisi Diponegoro Mayor Jenderal Sudarsono kecuali atas perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman namun melakukan “karantina halus” terhadap Mayor Jenderal Sudarsono disisi lain— telah memberi cukup waktu bagi Letkol Soeharto untuk mengetahui kebenaran keterlibatan Panglima Divisi Diponegoro, sikap Jenderal Sudirman, siapa-siapa yang terlibat dan berapa kekuatan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu dengan tetap memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Mayor Jenderal Sudarsono telah memungkinkan semua pihak memperoleh bukti formal yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam pelaksanaan kudeta, seperti pembebasan tahanan politik dan pengajuan maklumat kepada presiden.
- Jaminan keamanan yang diberikan Pak Harto kepada pihak istana telah menyebabkan Mayor Jenderal Sudarsono beserta anggota Kelompok Persatuan Perjuangan tidak memiliki kesiagaan ketika ditangkap oleh satuan keamanan istana. Mereka tidak bisa menggerakkan satuan-satuan ketentaraan dalam naungan Divisi Diponegoro untuk memberikan tekanan kepada istana. Hal itu disebabkan inti kekuatannya dari Resimen 22 telah dikondisikan oleh Letkol Soeharto untuk memberikan perlindungan atas “tindakan istana”.
- Letkol Soeharto , sebagai komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro memang tidak secara formal melakukan penangkapan pelaku kudeta. Namun ia memiliki peran sentral dalam mengkarantina ruang gerak sayap militer kelompok kudeta dan mengamankan kebijakan istana dalam penangkapan tokoh-tokoh pelaku kudeta. Tanpa disadari tindakannya berperan besar dalam menggagalkan kudeta tanpa pertumpahan darah dan komplikasi dalam tubuh institusi ketentaraan.
Peristiwa itu sendiri dikenal sebagai peristiwa 3 Juli 1946. Namun peran Letkol Soeharto yang genial itu tidak banyak diekspose kecuali penolakan surat perintah yang kemudian dirinya dijuluki sebagai perwira muda koppig.
NETRALISASI SATUAN-SATUAN PENDUKUNG FDR MADIUN
Letkol Soeharto merupakan salah satu bagian skenario Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam menetralisir pemberontakan FDR/PKI Madiun tahun 1948. Penugasan Letkol Soeharto merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana Panglima Jenderal Sudirman menjadikan Divisi III/Diponegoro sebagai instrumen penengah konflik antar kesatuan ketentaraan yang terjadi pada saat itu.
Infiltrasi PKI telah menyebabkan konflik antara Divisi Siliwangi (yang baru long march dari Jawa Barat menuju Ibukota Yogyakarta sebagai konsekwensi perjanjian renvile) dan kesatuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) nyaris mengalami jalan buntu. Kedua belah pihak (brigade-brigade siliwangi dan KPPS) bertempur secara fanatik. Tidak jarang perkelahian perorangan dengan sangkur terjadi. Konflik ini benar-benar tajam. Panglima Besar Jenderal Sudirman bahkan hampir memenuhi tuntutan KPPS untuk mengeluarkan kesatuan Siliwangi dari Surakarta, namun atas masukan dari para stafnya (termasuk AH. Nasution), rencana tersebut dibatalkan.
Penyelesaian konflik tentu tidak cukup di atas meja, namun juga harus dilakukan gelar pasukan yang disegani kedua belah pihak untuk menjadi penengah. Sebagai solusi, selain menempatkan sosok tegas Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta, Jenderal Sudirman melibatkan Divisi III Diponegoro (sebagai satuan ketentaraan yang tidak terlibat konflik) untuk turut menengahi konflik, yaitu:
- Pada tanggal 17 September 1948 Jenderal Sudirman memerintahkan Batalyon Suryo Sumpeno Divisi III/Diponegoro berangkat ke Solo untuk melapisi kekuatan Kolonel Gatot Subroto melerai tembak menembak antara Divisi Siliwangi dengan KPPS.
- Pada tanggal 21 September 1948 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajak Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/Diponegoro melakukan konsolidasi pasukan di Solo. Salah satu misinya adalah melakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan TNI yang selama ini bertikai akibat infiltrasi PKI.
- Pada tanggal 21 September 1948 tidak semua komandan pasukan menghadap Kolonel Gatot Soebroto sebagaimana tenggat ultimatum yang sudah ditetapkan. Diantara Komandan yang membangkang dan tidak memenuhi ultimatum itu adalah Letkol Suadi Suromihardjo (Komandan KPPS), Mayor Slamet Riyadi dan Mayor Soediarto. Masalah tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan memperlemah kekuatan TNI dimana pada tanggal 19 sebelumnya, FDR telah mengumumkan perlawanannya terhadap Republik Indonesia. Untuk menetralisasi pembangkangan, Jenderal Sudirman memerintahkan Letkol Soeharto, Komandan Brigade X Divisi III Diponegoro Yogyakarta untuk menetralisasi keterlibatan lebih jauh Letkol Suadi Suromihardjo dalam Gerakan FDR/PKI Madiun dan mengembalikannya kedalam barisan republik.
Upaya meyakinkan Letkol Suadi Suromihardjo tidak berjalan mulus. Selain sudah terkena doktrin FDR/PKI, Letkol Suadi Suromihardjo sudah barang tentu menghitung dampak pembangkangannya terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto. Ia justru memanfaatkan kedatangan Letkol Soeharto ke Wonoigiri menemui dirinya, untuk melaksanakan misi Djoko Suyono (komandan militer pasukan-pasukan PKI) yang hendak menunjukkan bahwa keadaan Madiun aman dan tertib serta pemerintahan Front Nasional yang baru dibentuknya berjalan dengan baik. Pada tanggal 22 September 1948, Djoko Suyono mengumumkan undangan kepada Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Polisi dan Komandan-Komandan lain di seluruh daerah RI untuk menghadiri konferensi di Balai Kota Madiun. Letkol Sadikin (Brigade II Siliwangi berkedudukan di Surakarta) juga diundang akan tetapi tidak hadir walaupun pemerintah Front Nasional Madiun memberikan jaminan keamanan.
Letkol Soeharto mengakui menuruti ajakan Letkol Suadi Suromihardjo, sebab kalau tidak menuruti nanti disangkanya tidak berani. Apalagi dirinya sedang menjalankan misi sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan tugas membujuk Letkol Suadi Suromihardjo agar yang bersangkutan melepaskan dukungannya terhadap FDR/PKI. Sikap baik terhadap Letkol Suadi Suromihardjo perlu ditunjukkan agar upayanya mengajak kembali kedalam barisan republik juga ditanggapi dengan baik. Akhirnya Letkol Soeharto datang ke Madiun dan oleh Letkol Suadi Suromihardjo dipertemukan dengan Muso di Karesidenan. Kepergian Letkol Soeharto ke Madiun memicu anggapan sementara kalangan bahwa ia menghadiri konferensi di Balai Kota sebelum akhirnya pulang kembali ke Wonogiri bersama Letkol Suadi Suromihardjo.
Kesediaan Letkol Soeharto memenuhi ajakan Letkol Suadi Suromihardjo pergi ke Madiun, sebenarnya merupakan bentuk kesungguhan seorang perwira muda menjalankan misi yang dibebankan Panglimanya. Ia tidak mungkin bergegas pulang dengan tangan kosong sebelum misinya berhasil meluluhkan sikap Letkol Suadi Suromihardjo dari dukungannya terhadap FDR/PKI. Maka dia penuhi “tantangan” Letkol Suadi Suromihardjo walaupun harus melewati resiko yang dapat saja membahayakan keselamatan jiwanya. Tentunya, selama melakukan perjalanan bersama itu, Letkol Soeharto dan Letkol Suadi Suromihardjo mendiskusikan banyak hal tentang pesan Panglima Jenderal Sudirman seperti implikasi destruktif apabila gerakan FDR/PKI tidak dihentikan dan masa depan karir militernya setelah melakukan pembangkangan terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto.
Kapten Tjokropranolo didampingi Kapten Soetanto Wiryoprasanto dan Kapten CPM Ali Aliamangku (CPM Siliwangi) —atas penugasan Jenderal Sudirman— akhirnya berhasil menghadapkan Mayor Slamet Riadi dan Letkol Suadi Suromihardjo. Mayor Slamet Riadi diketemukan di lereng selatan Gunung Merapi dan Letkol Suadi Suromihardjo diketemukan di Wonogori. Keberhasilan Kapten Tjokropranolo itu tentunya setelah Letkol Suadi Suromihardjo berhasil diyakinkan untuk kembali bergabung dengan pihak Republik oleh Letkol Soeharto. Begitu pula dengan posisi Letkol Suadi Suromihardjo berada, tidak lain merupakan informasi yang diberikan Letkol Soeharto kepada Jenderal Sudirman. Suatu hal yang mustahil bagi tiga orang kapten “membawa” Panglima KPPS —yang pada saat itu berada dalam wilayah/ perlindungan TLRI pimpinan Yadau dan Batalyon Soedigdo Honggotirtono yang mundur ke Wonogiri, dimana kedua satuan tentara tersebut berpihak kepada FDR/PKI—. Keberhasilan Kapten Tjokropranolo hanya dimungkinkan atas kehendak Letkol Suadi Suromihardjo sendiri setelah berhasil dinetralisasi Letkol Soeharto dari pengaruh PKI. Keberhasilan membawa kembali Letkol Suadi Suromihardjo menyebabkan dukungan KPPS terhadap FDR/PKI mengalami disorganisasi dan KPPS mampu dikonsolidasi kembali untuk berada dalam barisan Republik.
AKTOR UTAMA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
Letkol Soeharto merupakan aktor utama dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Keberhasilan serangan ini menjadi modal utama dalam melicinkan pintu diplomasi Indonesia di forum internasional sehingga Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Rencana Belanda hendak menguasai kembali Indonesia yang pada awalnya didukung sekutu dapat dipatahkan.
Ada banyak pihak yang meragukan Letkol Soeharto sebagai aktor utama Serangan ini. Namun mencermati fakta dan situasi yang mengitarinya, keragu-raguan itu dengan sendirinya terpatahkan. Fakta-fakta tersebut antara lain:
1. Sistem Wehrkreise
Tusukan Belanda melalui Agresi I tanggal 21 Juli 1947, dan secara sepihak menetapkan garis “status quo” baru yang dinamai “Garis Van Mook” (23 Agustus 1947) telah mempersempit wilayah Indonesia. Kenyataan tersebut mendorong penyempurnaan strategi perjuangan TNI dalam bentuk Wehrkreise sebagai pangkal perlawanan terpadu antara Pemerintahan RI tingkat kecamatan, desa, rayat dan tentara. Wehrkreise merupakan skema perjuangan militer yang pada dasarnya membagi-bagi suatu daerah pertempuran kedalam lingkaran-lingkaran (bahasa Jerman “kreise”) yang dapat mengadakan pertahanan (bahasa Jerman “wehr”) secara sendiri-sendiri. Semua tenaga manusia dan materiil serta bahan-bahan yang berada dalam lingkaran-lingkaran itu diintegrasikan. Konsep ini pada segi taktis militer dilengkapi dengan strategi gerilya. Sebagai komandan Brigade X/ Wehrkreise III Yogyakarta, Letkol Soeharto merupakan penanggung jawab perjuangan di wilayah Yogyakarta. Maka menjadi sangat logis apabila dirinya mengambil inisiatif, merencanakan, memobilisasi kekuatan dan sekaligus memimpin serangan Umum 1 Maret 1949. Bahwa dalam perkembanganya —setelah konsep dan persiapan serangan mulai terkonsolidasi— terdapat berbagai pihak memberikan masukan ataupun dukungan dan mengklaim memiliki (atau diduga memiliki) peran besar dalam merencanakan Serangan Umum 1 Maret 1949, sebenarnya dapat dikonforontasikan dengan sifat serangan itu sendiri yang jelas-jelas merupakan domain strategi perang dalam skema Wehrkreise.
Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 murni keberhasilan taktik militer. Taktik peperangan dalam kasus Serangan Umum 1 Maret 1949 meliputi mekanisme mobilisasi pasukan, penyusupan pasukan ke titik-titik serang, percikan-percikan pertempuran gerilya sebelum serangan besar, aspek pendadakan serangan pada hari H, orisinalitas sandi melalui simbolisasi janur kuning, dan mekanisme mundurnya pasukan tanpa membawa implikasi bumi hangus bagi masyarakat sipil. Serangan dilakukan dengan begitu terintegrasi dan serentak di dalam kota maupun titik-titik serang melingkari kota. Semua ruang gerak tentara Belanda telah ditutup dengan serangan gencar, sehingga selama enam jam keberadaan tentara Belanda —yang begitu perkasa ketika menerobos masuk Yogya— menjadi “mati suri” tanpa bisa menyajikan perlawanan berarti.
Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya dimungkinkan oleh keberadaan komando tunggal —yang memiliki kendali penuh atas setiap lini kekuatan tempurnya— dalam mengaplikasikan strategi perang yang telah direncanakan. Kemampuan menyusun “taktik perang” dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya dimiliki seorang komandan terlatih yang memang menguasai strategi sekaligus memahami medan pertempuran yang dihadapi.
2. Para Pimpinan TNI Bergerilya
Bersamaan dengan Agresi Belanda II, para pimpinan TNI bergerilya ke daerah-daerah pedalaman yang jauh dari Ibukota. Menjelang maupun pada saat terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, selain dipisahkan jarak, juga dihadapkan oleh kendala komunikasi. Maka perintah serangan pada esensinya tidak berasal dari struktur militer yang lebih tinggi, namun oleh sistem wehrkreise yang mengamanatkan komandannya untuk mengambil inisatif pertahanan atas wilayahnya masing-masing.
Sebagai komandan wilayah Ibukota, Letkol Soeharto dituntut mengambil tindakan cepat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap eksistensi TNI. Oleh karena itu setelah menyaksikan pertahanan Ibukota begitu mudahnya ditembus pasukan Belanda, ia segera memobilisir pasukan yang ditempatkan diluar kota untuk segera menyusun setor-sektor pertahanan mengililingi Ibukota maupun di dalam kota sendiri. Setelah persiapan dirasa cukup, ia memerintahkan pasukannya melakukan serangan kecil-kecilan untuk mengelabuhi kesigapan tentara Belanda. Sehingga ketika pada hari H serangan umum dilakukan, pasukan Belanda menjadi sangat terkejut karena tidak menduga akan memperoleh serangan sebesar itu.
Dalam kondisi terpisah dan terputus komunikasi dengan struktur kemiliteran yang lebih tinggi, maka kendali penuh atas wilayah Yogyakarta berada di tangan Letkol Soeharto. Begitu pula dalam konteks Serangan Umum 1 Maret 1949, perencanaan, mobilisasi pasukan dan penyiapan strategi perang merupakan inisiatif sepenuhnya komandan Brigade X/ Wehrkreise III Yogyakarta.
3. Penolakan Serah Terima
Keberadaannya sebagai komando tunggal wilayah perang Yogyakarta tercermin dari kepercayaan diri Letkol Soeharto ketika menolak melakukan serah terima Kota Yogyakarta dari Belanda kepada TNI. Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 segera membuat redup pamor Belanda di dunia internasional dan meja perundingan. Melalui perjanjian Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949 diputuskan pasukan Belanda harus segera meninggalkan Yogyakarta. Sementara itu pasukan RI dengan segenap aparat pemerintahanya kembali memasuki Yogyakarta.
Letkol Soeharto menolak serah terima karena menurut pendapatnya Belanda tidak pernah berkuasa di Yogya. Bahkan ketika dirinya memperoleh tekanan dari Sultan untuk melakukan serah terima, sikap itu tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan kenapa ia bersikukuh dengan sikapnya. Walaupun para pejabat politis melakukan kompromi-kompromi dengan menunjukkan sikap akomodatif kepada Belanda, Letkol Soeharto —sebagai representasi rakyat dan TNI yang hatinya terluka— tetap mempertahankan sikapnya dengan membiarkan pasukannya siaga tempur. Ia tidak menganggap eksistensi pasukan Belanda di Yogyakarta dan akan melakukan perjuangan hingga detik terakhir manakala pasukan itu tidak segera ditarik pergi dari wilayah Yogya. Hal itu menandakan ia telah mempersiapkan segala implikasi penolakan serah terima. Sikapnya itu membuat gusar Sultan HB IX sebagaimana tercermin dari sepucuk suratnya kepada Letkol Soeharto yang isinya “Overste Soeharto, kalau Overste tidak mendukung saya, mandate akan saya kembalikan”. Namun Letkol Soeharto tetap tidak bergeming. Bahkan Panglima Besar Sudirman menjuluki Letkol Soeharto sebagai “bunga pertempuran” dalam peristiwa Serangan Umum 1 maret 1949. Bahkan Letkol Soeharto lah yang berhasil meyakinkan Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Ibukota. Pada saat Panglima Besar itu dilanda ketidakpercayaan kepada para pimpinan politik.
MEREDAKAN SERANGKAIAN PEMBERONTAKAN
Letkol Soeharto juga turut serta meredakan berbagai pemberontakan penataan internal TNI. Ia pernah ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk turut serta menjalankan misi penumpasan pemberontakan Andi Azis. Disanalah Letkol Soeharto bertemu dengan BJ Habibie yang kelak ketika menjabat sebagai presiden dipercaya dalam mengembangkan teknologi tinggi (high tech) dan industri strategis Indonesia.
Setelah itu ia kembali ditugaskan di Jawa sebagai Komandan Brigade O Surakarta dalam tatanan angkatan perang yang baru direorganisasi oleh Menteri Pertahanan. Dalam masa penugasannya itu ia bersinggungan dengan masa-masa gejolak pemberontaan DI/TII. Setelah itu ia diberi penugasan sebagai Komandan Brigade Pragola I di Salatiga dengan tugas melakukan reorganisasi satuan-satuan kekuatan yang ada di dalamnya. Pada saat itu ia menghadapi perlawanan dari satuan yang direorganisasi yaitu Batalyon 426 dan Batalyon Infantri 423. Selain dampak psikologis reorganisasi sebagai akibat pergeseran pimpinan puncak pasukan yang jumlahnya semakin mengecil, perlawanan satuan-satuan tersebut juga disebabkan “keterlibatan rahasia” sejumlah perwira (dalam batalyon 426 dan 423) dengan gerakan DI/TII. Untuk penumpasan pemberontakan, Panglima Tentara Teritorium IV, Kolonel Gatot Soebroto membentuk satuan tugas Operasi Merdeka Timur V dimana Letkol Soeharto diserahi tugas kepemimpinan menggantikan Letkol Bachrum. Setelah itu ia berpindah-pindah tugas menjadi pimpinan Resimen 14 di Salatiga (tahun1952), Komandan Resimen 15 di Solo (1953) dan kemudian diangkat sebagai Panglima Tentara Teritorium IV/Diponegoro berkedudukan di Semarang.
Ketika bertugas di Solo, Letkol Soeharto memahami karakteristik satuan-satuan yang ada dibawahnya, termasuk Batalyon Digdo di Kleco yang memperoleh pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin. Untung dan Suradi merupakan anggota Batalyon Kleco, sehingga ketika yang bersangkutan (Letnan Letkol Untung) memimpin G.30.S/PKI, dirinya segera mengetahui motif idiologis dibalik peristiwa itu.
Pada saat memimpin Tentara Teritorium IV, ia mulai memikirkan kesejahteraan TNI dengan mendorong kegiatan koperasi di seluruh kesatuan yang dipimpinnya. Ia juga mulai mendorong tumbuhnya kesejahteraan rakyat —yang diakuinya telah berjasa dalam revolusi fisik— namun masih hidup dalam suasana kekurangan. Salah satunya adalah kelangkaan pangan (beras) walaupun di wilayah kerjanya surplus gula. Ia berinisiatif melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Pada saat memimpin Tentara Teritorium IV/Diponegoro itu, ia kembali dipercaya mengantarkan kepergian tokoh pejuang Nusantara dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dimana ia bertindak menjadi inspektur upacara pada saat pemakaman. Terekam kuatnya memori wafatnya Ki Hajar Dewantara dalam perjalanan karir hidupnya (selain Jenderal Soedirman), menandakan bahwa Letkol Soeharto merupakan salah satu generasi penerus nusantara yang dipercaya oleh takdir sejarah untuk memimpin dalam memberikan penghormatan secara langsung kepergian para pejuang-pejuang pendahulunya.
Selanjutnya karir militernya dilanjutkan dalam tempaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat /SSKAD (mulai 1 November 1959). Ia lulus sebagai peserta terbaik dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal TNI. Ia kemudian diangkat sebagai Deputi I KSAD dan pernah menjabat sebagai ketua Adhoc Retooling Departemen AD. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat /Caduad (1 Maret 1961) dan Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat /Kohanudad (sejak 1 Oktober 1961). Pengalaman eksternalnya mulai ditempa ketika dipercaya menyertai KSAD Jenderal A.H. Nasution melakukan kunjungan dinas ke sejumlah Negara Eropa. Tempaan pengalaman itu mengantarkanya pada pergulatan elit TNI pada waktu-waktu berikutnya.
KOMANDO MANDALA PEMBEBASAN IRIAN BARAT
Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan Irian Barat disepakati akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagaimana tabiat aslinya, Belanda berusaha merobek perjanjian dengan berbagai cara, termasuk melalui pintu diplomasi maupun cara-cara militer dengan terus memperkuat tentaranya di Irian Barat. Setelah melalui jalur diplomasi tidak menuai hasil, pemerintah Indonesia memutuskan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui konfrontasi di segala bidang termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.
Pada awalnya, langkah-langkah militer pembebasan Irian Barat kurang menuai hasil. Sampai suatu ketika Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat sekaligus memenuhi usulannya —usulan Mayor Jenderal Soeharto— menjadikan Kawasan Timur Indonesia-Irian Barat sebagai satu kesatuan Mandala di bawah satu komando.
Secara keseluruhan operasi, perjuangan pembebasan Irian Barat dilaksanakan dalam empat fase. Pertama, fase diplomasi. Kedua, fase operasi militer pra Mandala. Ketiga, fase Mandala terintegrasi, dan; Keempat, fase konsolidasi. Melalui keempat fase tersebut dapat diketahui peran penting Mayor Jenderal Soeharto dalam proses percepatan pembebasan Irian Barat.
1. Fase Diplomasi (Desember 1950-November 1957)
Merupakan fase perjuangan pembebasan Irian Barat dalam bentuk diplomasi, baik secara bilateral dengan Belanda maupun secara multilateral melalui forum-forum internasional. Misi diplomasi adalah terealisasinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang salah satu klausulnya menyatakan penyelesaian Irian Barat dalam waktu satu tahun (pada akhir tahun 1950, secara de facto maupun de jure sudah menjadi bagian Indonesia). Upaya diplomasi itu menemui fakta baru, dimana Belanda secara terang-terangan merobek hasil KMB dengan mempengaruhi PBB agar memutuskan Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Belanda juga memasukkan Irian Barat sebagai bagian wilayahnya pada bulan Agustus 1952. Sikap Belanda tersebut membuat eskalasi politik diplomasi Indonesia-Belanda semakin panas. Perlawanan rakyat Irian Barat terhadap tentara Belanda yang menduduki wilayahnya semakin meningkat. Desakan rakyat untuk segera membentuk provinsi Irian Barat juga semakin menguat.
Sikap Belanda di satu sisi (mengingkari KMB) dan desakan rakyat Irian Barat maupun rakyat Indonesia di sisi lain (menuntut segera dilakukan pembebasan Irian Barat) pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia mempergencar diplomasi internasional. Negara-negara Asia-Afrika berhasil digalang untuk memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam forum-forum internasional. Upaya-upaya itu terus dihadang Belanda, sehingga upaya memasukkan masalah Irian Barat sebagai agenda Sidang Umum (SU) PBB terus menemui jalan buntu karena masalah quorum. Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mengarahkan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi di segala bidang.
Salah satu kegagalan politik diplomasi Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah keberhasilan Belanda dalam mempengaruhi Amerika Serikat untuk mendukung agendanya. Dukungan Amerika Serikat itu diduga memiliki keterkaitan dengan tawaran limpahan sumber daya alam Irian Barat yang secara bersama-sama akan dikelola dengan Belanda. Hal itu terbukti melalui pemberitaan New York Time pada tanggal 16 Maret 1959 atas penemuan cadangan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Perkembangan selanjutnya (tahun 1960), Perserikatan Perusahaan Borneo Timur dan Freeport Sulphur menandatangani perjanjian mendirikan tambang tembaga di Timika. Sikap tertutup tampak dari perjanjian kontrak kerjasama yang tidak menyebut adanya kandungan emas ataupun tembaga sebagai bidang usaha yang akan dikelola.
2. Fase Operasi Militer Pra Mandala (Desember 1957-Maret 1962)
Sebagai bentuk strategi baru menekan Belanda dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan warisan kolonial Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nasionalisasi diawali dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut oleh KSAD, AH. Nasution dalam kapasitas Sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) pada tanggal 2 Desember 1957. Tindakan itu akhirnya disahkan melalui UU No. 86 Tahun 1958. Upaya tersebut berhasil menasionalisasi 700 buah perusahaan Belanda dengan total asset 1.500 juta dolar. Pemerintah RI juga melarang perusahaan penerbangan Belanda Koninlijke Luchtvaart Maschappij (KLM) melakukan aktifitasnya di Indonesia.
Langkah selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1958 pemerintah Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang diketuai oleh KSAD Mayor Jenderal Nasution. Dalam kapasitasnya sebagai ketua FNIB dan KSAD, Mayor Jenderal Nasution merumuskan tiga kebijakan operasi pembebasan Irian Barat, yaitu:
- Operasi A dengan tugas melakukan kegiatan intelijen dengan mengirim infiltran-infiltran ke daratan Irian Barat.
- Operasi B dengan tugas mempersiapkan satuan-satuan militer untuk perebutan Irian Barat secara fisik.
- Operasi C dengan tugas kegiatan diplomasi luar negeri untuk memperlemah Belanda dan memperkuat RI dalam forum internasional.
Pada tanggal 12 April 1961 melalui Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H Nasution, Presiden/Panglima Tertinggi memerintahkan Gabungan Kepala Staf (GKS) untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Pembebasan Irian Barat. Pada 30 Juni 1961 GKS telah berhasil merumuskan konsep operasi, meliputi:
- Operasi B-1, merupakan operasi militer terbuka dengan sasaran penuh untuk memperoleh kekuasaan de facto seluruh wilayah Irian Barat.
- Operasi B-2 merupakan operasi sasaran terbatas untuk menguasai suatu daerah tertentu di wilayah Irian Barat agar menimbulkan suasana politik yang menguntungkan sekaligus membuka garis depan.
- Operasi B-3 merupakan ilfiltrasi militer untuk memperoleh pangkalan dalam serangan lanjutan.
Dalam rentang waktu yang tidak berjauhan, atas usulan Jenderal A.H Nasution dibentuk pula Depertan (Dewan Pertahanan Nasional) dan KOTI Permibar (Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat) serta Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ketiga struktur tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
- Depertan, diketuai Presiden dan dibantu Menteri Pertama Juanda dan Menhankam Jenderal A.H Nasution, berperan dalam menetapkan grand strategy pembebasan Irian Barat.
- KOTI Permibar (Presiden Soekarno sebagai Panglima, Jenderal A.H Nasution sebagai Wakil Panglima dan Jenderal A. Yani sebagai Kepala Staf Tertinggi), merupakan tingkat Komando Tertinggi (KOTI) yang berperan dalam menetapkan pokok-pokok strategi militer.
- KOLA (Komando Mandala Pembebasan Irian Barat), dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, dengan tugas melaksanakan pokok-pokok strategi militer yang telah ditetapkan KOTI.
Konsolidasi struktur organisasi perjuangan pembebasan Irian Barat —yang pada akhirnya menempatkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima komando garis depan perjuangan militer— sebenarnya dilatarbelakangi serangkaian kegagalan operasi militer dalam fase ini. Sebagai pelaksanaan operasi A, pemerintah telah melaksanakan operasi Pasukan Gerilya 100 (PG-100) hingga PG-600. Operasi tersebut menemui sejumlah kegagalan. Operasi lain yang juga mengalami kegagalan adalah tenggelamnya MTB Macan Tutul dan gugurnya Deputi I KSAL Komodor Laut Yos Sudarso. Kegagalan tersebut diantaranya disebabkan faktor-faktor berikut:
- Belum terintegrasinya kekuatan-kekuatan militer pendukung operasi sehingga masing-masing kesatuan bergerak secara mandiri. Sebagai contoh adalah saling tuding kegagalan MTB Macan Tutul dimana Angkatan Udara yang dipimpin Laksamana Udara Suryadarma dianggap tidak memberikan dukungan udara terhadap pelaksanaan operasi.
- Belum adanya kesiapan pangkalan-pangkalan depan pendukung operasi (Makasar, Ambon, Pulau Seram dan sekitarnya) dan tidak jarang operasi diberangkatkan dari Jakarta dengan jarak tempuh yang panjang.
- Belum tersedianya daya dukung peralatan perang dan angkutan pasukan termasuk pengamanan pasukan dalam perjalanan menuju zona pendaratan di Irian Barat.
- Merupakan ulah atau desakan politisi-politisi sayap keras yang mendorong percepatan operasi tanpa perhitungan taktik militer secara rinci.
Fakta tersebut mendorong Presiden menoleh Mayor Jenderal Soeharto, perwira militernya yang dianggap paling mumpuni dalam menangani kemelut untuk segera memulai operasi. Presiden juga menyetujui usulan Mayor Jenderal Soeharto untuk diberi kewenangan menyusun staf operasi gabungan dan menjadikan Irian Barat-Indonesia Bagian Timur sebagai kesatuan satuan “Mandala”. Dengan kewenangan tersebut semua angkatan yang tergabung dalam Operasi Mandala berada di bawah satu komando dirinya sebagai Panglima KOLA.
3. Fase Mandala Terintegrasi (Maret 1962-September 1962)
Penunjukan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dilatarbelakangi oleh pertimbangan militer. Ia merupakan sosok perwira militer pendiam dan tidak ambisius sehingga dipercaya mampu mengendalikan operasi militer skala besar. Karakter Mayor Jenderal Soeharto dinilai tepat untuk melaksanakan kampanye militer prestisius bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diakui Jenderal Nasution, Presiden Soekarno menghargai Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan menonjol dalam TNI dan oleh karenanya Presiden tidak ragu-ragu menerima usulan Jenderal Nasution mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Setelah ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan konsolidasi internal, pemetaan internal-eksternal dan merumuskan strategi militer pembebasan Irian Barat. Konsolidasi militer dilakukan dengan mengintegrasikan semua komponen Mandala yang terdiri dari Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala, Angkatan Udara Mandala, Kepolisian Negara, Pertahanan Udara Gabungan dan Pengerahan Cadangan Nasional (Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara/GIA).
Pembebasan Irian Barat dilakukan dalam tiga tahapan strategi. Pertama, strategi infiltrasi untuk membentuk kantong-kantong atau daerah bebas de facto di Irian Barat, sehingga bisa menjadi bargaining yang baik dalam diplomasi. Strategi tersebut dimaksudkan untuk: (1) membentuk pancangan kaki (beach head) bagi serangan terbuka pasukan besar yang akan didaratkan, (2) memecah belah pasukan Belanda kedalam arena pertempuran-pertempuran kecil dalam titik yang banyak, dan (3) menyiapkan instrumen bargaining diplomasi yang kuat, bahwa Belanda tidak benar-benar menguasai semua wilayah Irian Barat. Berdasarkan pemetaan kekuatan dan fasilitas militer yang ada, strategi ini akan berhasil dilaksanakan sampai akhir tahun 1962 dengan memasukkan 10 kompi pasukan. Kedua, tahap exploitasi. Merupakan tahap serangan terbuka ke Induk pasukan Belanda di Biak dan menduduki semua pos pertahanan di Irian Barat. Tahap ini diperkirakan bisa dilakukan pada tahun 1963. Ketiga, tahap konsolidasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan RI di Irian Barat. Tahap ini dilakukan pada tahun 1964.
Mengingat Mayor Jenderal Soeharto hanya diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan operasi militer pembebasan Irian Barat —agar bendera Merah Putih sudah bisa berkibar di Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1962 —, maka penetapan jadwal melampaui tenggat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, tenggat tersebut menggambarkan peluang sebenarnya dari sudut strategi militer. Kedua, merupakan strategi untuk mengaburkan rencana RI bagi Belanda, karena faktanya hari H serangan besar ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1962 atau jauh dari asumsi kesiapan pasukan. Ketiga, merupakan gambaran riil kondisi eksiting dan oleh karena itu dilakukan percepatan persiapan sehingga hari H dapat dilaksanakan sebelum tenggat tanggal 17 Agustus 1962.
Terlepas dari teka-teki estimasi kesiapan pasukan, faktanya Komando Mandala telah melakukan operasi infiltrasi militer sejak 1 Maret 1962 atau kurang dua bulan setelah Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai panglima KOLA. Hingga hari H, tanggal 12 Agustus 1962 tidak kurang 17 kali operasi infiltrasi —baik dari unsur Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala dan Angkatan Udara Mandala— telah dilaksanakan. Fasilitas-fasilitas militer yang memungkinkan terbukanya pangkalan depan juga telah direhabilitasi dengan cepat.
Untuk mempercepat dan menjamin efektifitas infiltrasi, Mayor Jenderal Soeharto mengirimkan pasukan para yang antara lain RPKAD dan PGT. Hal ini mengundang kritik banyak pihak, namun dengan menggunakan terlatih pasukan inilah, mitos bahwa hutan lebat Irian Barat tidak bisa dipergunakan penerjunan bagi pasukan para, menjadi terpatahkan. Keberhasilan infiltrasi pasukan para, selain dengan mengirimkan pasukan terlatih juga dilakukan dengan terbang rendah sehingga tidak terpantau radar Belanda. Penggunaan pasukan khusus RPKAD dan PGT juga dimaksudkan sebagai strategi untuk secara efektif mengikat musuh supaya kekuatannya terpecah-pecah dan memaksa menggunakan pasukan cadangan Belanda menghadapi infiltran sehingga induk pasukan menjadi lemah.
Pada tanggal 20 Juli 1962, hari H operasi Jayawijaya, sebuah serangan besar ke sasaran utama Biak dan Holandia (Jayapura) telah ditetapkan. Pada tanggal 23 Juli 1962, kapal selam pembawa pasukan RPKAD sudah berada diantara Holandia dan Biak. Tanggal 2 Agustus 1962 konvoi Angkatan Tugas Amphibi 17 (ATA-17) telah berada di Titik Kumpul I (TK-I) Teluk Peleng dan pada tanggal 7 Agustus 1962 menuju Titik Kumpul II (TK-II) utara Morotai. Pada tanggal 8 Agustus 1962 ATA-17 telah bergerak menuju Biak untuk memulai serangan besar pada hari-H. Iring-iringan tersebut dipantau oleh kapal selam dan pesawat pengintai (U2) AS yang akhirnya meyakini Indonesia dalam kondisi siap tempur. Pada saat pasukan Indonesia berada dalam kondisi siap tempur itulah, tanggal 15 Agustus 1962 (2 hari sebelum tenggat 17 Agustus 1962) telah dicapai kesepakatan New York yang pada intinya Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat melalui Penguasa Sementara PBB. Latar belakang dicapainya kesepakatan New York dapat dilihat dari aspek politis maupun militer:
- Secara militer, Panglima Komando Mandala berhasil melakukan infiltrasi dan mobilisasi kekuatannya untuk siap menjepit Belanda dari semua sudut, baik dari udara, laut dan satuan-satuan kecil darat, sebelum nantinya terjadi serangan besar dilaksanakan. Selain strategi dan taktik militer telah diperhitungkan dengan cermat, tambahan peralatan militer, khususnya kedatangan kapal-kapal selam yang di beli dari Uni Soviet merupakan ancaman serius bagi kekuatan Angkatan Laut Belanda. Terlepas apakah nantinya mampu memenangkan pertempuran selama lima hari —sebagaimana diproyeksikan Mayor Jenderal Soeharto— hal yang pasti adalah jatuhnya korban skala besar pada kedua belah pihak. Mayor Jenderal Soeharto merupakan perancang strategi sekaligus eksekutor lapangan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang telah memaksa Belanda kehilangan muka dan angkat kaki dari Indonesia. Merupakan pilihan rasional bagi Belanda untuk menyerah kalah di meja perundingan sebelum nantinya kehilangan banyak pasukan dan citra internasionalnya untuk kedua kali. Kesiapan operasi militer telah menjadi alat bargaining diplomasi yang sangat kuat bagi Indonesia dalam menghadapi Belanda di meja perundingan.
- Penguasaan Belanda atas Irian Barat tidak memiliki pijakan moral kuat setelah kolonialisasi bukan lagi pilihan populer dalam percaturan internasional. Pihak Indonesia berangkat ke medan perang dengan spirit menggelora untuk mengambil kembali haknya yang dirampas. Perbedaan spirit pasukan itu akan menggiring Belanda —cepat atau lambat— menelan kekalahan militer dari Indonesia dan kehilangan pijakannya di tanah Irian Barat. Belantara Irian Barat merupakan kawasan gerilya dimana pasukan Indonesia memiliki ketangguhan lebih baik jika dibandingkan dengan pasukan Belanda.
- Secara politis, Belanda tidak lagi memperoleh dukungan AS untuk terus memaksakan agenda kolonalisasinya, apalagi dengan menggunakan kekuatan militer. Bagi AS, mendukung Belanda tidak lagi memiliki pijakan moral dan bukan pilihan strategis karena justru akan menambah lawan dalam konfrontasi perang dingin. AS belajar dari kasus pengabaiannya terhadap permintaan kerjasama persenjataan dari Indonesia yang pada akhirnya justru membuka ruang masuknya peralatan militer dari blok Komunis Uni Soviet.
Terlepas dari aspek-aspek politis, kesiapan operasi militer Komando Mandala merupakan faktor utama penyerahan Irian Barat oleh Belanda. Kesiapan operasi militer itu sendiri tidak lepas dari faktor-faktor berikut:
- Ketegasan Mayor Jenderal Soeharto menetralisasi operasi Mandala dari tarik ulur politik yang tidak sejalan dengan segi-segi taktis kemiliteran. Hal itu ditunjukkan ketika Muhammad Yamin memintanya agar segera menenggelamkan kapal-kapal Belanda untuk tujuan bargaining diplomasi. Permintaan itu secara tegas ditolak karena menurutnya sikap tergesa-gesa justru akan memporak-porandakan persiapan militer yang waktu itu hampir matang.
- Kejelian Mayor Jenderal Soeharto melakukan pemetaan kekuatan-kelemahan militer Indonesia maupun Belanda serta potensi-potensi pendukung di Irian Barat yang bisa dimobilisasi mendukung operasi militer Indonesia. Ia mempersiapkan operasi militer dengan penuh perhitungan dan menghindari optimisme berlebihan. Ia juga tidak menutup-nutupi aspek-aspek kelemahan kekuatan dan strategi militer Indonesia hanya untuk membuat Presiden Soekarno senang. Hal itu ditunjukkan ketika ia meminta kewenangan mengintegrasikan seluruh kekuatan militer dalam satu Komando Mandala untuk mempermudah koordinasi sekaligus penyiapan sarana-prasarana pendukung operasi militer yang berada di garis depan. Ia juga berterus terang dalam hal kekurangan pasokan persenjataan dan peralatan perang. Atas kejujuran yang didasarkan pada pertimbangan segi taktis kemiliteran itu, Presiden Soekarno tidak ragu memberikan dukungan pada tindakannya.
- Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto mengeksplorasi titik lemah lawan seperti halnya strategi mengelabui radar Belanda dengan terbang rendah menggunakan pesawat C-47 Dakota pada saat penyusupan pasukan para. Begitu pula penggunaan pasukan khusus RPKAD yang disusupkan dengan menerjunkannya melalui belantara Irian Barat. Strategi itu telah memungkinkan infiltrasi pasukan pendahulu melalui udara dapat dilakukan secara efektif. Begitu pula dengan kemampuan pasukan yang diturunkan, sebagai pasukan khusus, RPKAD lebih menjamin keberhasilan dalam mengikat dan menarik keluar cadangan induk pasukan Belanda kedalam titik-titik kecil pertempuran. Strategi ini mirip dengan penggunaan airborne (pasukan para) yang diterjunkan sebagai pasukan pendahulu dengan misi mematikan meriam pertahanan udara dan bunker-bunker pertahanan Jerman sebelum akhirnya dilakukan serangan besar melalui pantai Normandia Prancis.
- Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto yang dalam waktu cepat dapat mempersiapkan serangan militer terintegrasi dari darat, laut dan udara, baik dari garis depan (serangan serentak) maupun belakang (satuan-satuan infiltran). Kesiapan serangan itu menyebabkan Belanda terkepung dari berbagai sudut. Cepat atau lambat kekalahan Belanda sudah diambang pintu dengan korban yang diprediksikan akan sangat banyak. Sementara itu mendatangkan pasukan bantuan sangat kecil kemungkinannya karena berada dalam jarak yang jauh dari negaranya.
4. Fase Konsolidasi (Pasca September 1962)
Merupakan fase konsolidasi kekuasaan pemerintah RI di Irian Barat dalam bentuk konsolidasi pasukan untuk memantapkan kendali teritorial di wilayah Irian Barat. Selain itu juga disiapkan operasi Brajamusti sebagai antisipasi pengingkaran Pemerintah Belanda terhadap perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah Belanda selalu mengingkari hasil perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Indonesia.
Pada fase ini juga menjalankan misi mengawal pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dimana rakyat Irian Barat dari Sabang hingga Mereauke memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil Pepera menjadi dasar lahirnya resolusi PBB yang menyatakan bahwa secara de facto maupun de jure, Irian Barat menjadi bagian wilayah Indonesia.
PENYELAMATAN KUDETA BANGSA/PERISTIWA G.30.S/PKI
Setelah menjalankan peran penting dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat, garis takdir menempatkan Mayor Jenderal Soeharto menjalani peran penyelamatan kudeta bangsa atau yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September 1965/PKI.
Salah satu ciri paham komunisme adalah ortodoksi dan homogenisasi idiologi politik yang ditegakkan melalui cara-cara revolusioner dan bahkan melalui jalan kekerasan militer. Suatu paham yang jelas-jelas tidak akan dapat bersemi dengan baik, atau suatu cara hidup yang pada akhirnya akan memperoleh perlawanan dan eksistensinya mengalami pelapukan cepat di bumi nusantara. Peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 pada dasarnya merupakan proyek untuk menjadikan nusantara sebagai subordinasi paham dan wilayah kekuasaan idiologi Komunisme. Aidit merupakan wayang yang bersedia memerankan diri sebagai operator dari sebuah drama besar usaha akuisisi peradaban nusantara oleh Komunisme. Ia berhasil berlindung dibalik penguasa nusantara kala itu, sosok kharismatik Presiden Soekarno, dan hampir berhasil pula memenggal “kepala naga kekuasaan nusantara” untuk kemudian menjalankan agendanya mendirikan imperium komunisme.
Takdir sejarah tidak menghendaki dekonstruksi peradaban Nusantara yang kali ini hendak didesain sebagai subordinasi imperium Komunisme. Oleh sebab sepele, rencana kudeta yang telah disusun rapi itu hancur berantakan. Kegagalan itu diawali dengan melesetnya rencana “pengamanan” Presiden Soekarno untuk hadir tepat waktu di Lapangan Udara Halim pada pagi hari pelaksanaan kudeta. Kegagalan Brigadir Jenderal Soepardjo “menjemput” Presiden Soekarno di Istana Negara menyebabkan rencana menyandera Presiden Soekarno agar secara mudah diarahkan sesuai skenario Aidit menjadi berantakan. Aidit dan komplotannya, Letkol Untung Cs, kemudian bertindak ceroboh dengan mendemisionerkan kabinet dan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara melalui pengumuman radio.
Kecerobohan sepele itu akhirnya membongkar kedok Aidit yang sebenarnya, sekaligus menggerakkan naluri Mayor Jenderal Soeharto, yang segera menangkap situasi, bahwa Presiden maupun bangsa dan negara dalam keadaan bahaya. Berbekal amanat Jenderal Soedirman agar dirinya menjaga keselamatan bangsa dan negara, ia mengumpulkan loyalis nusantara yang tersisa, untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap upaya kudeta. Kurang dari 24 jam, kudeta yang telah disusun rapi itu akhirnya hancur berantakan oleh serangan balik Mayor Jenderal Soeharto. Keberhasilan ini tidak hanya menggagalkan upaya PKI mengganti pemerintahan yang sah, akan tetapi juga menyelamatkan eksistensi peradaban nusantara yang akan dicerabut oleh kekuatan Komunisme.
Mayor Jenderal Soeharto menamakan kegagalan rencana kudeta itu sebagai kemenangan Pancasila. Hari kemenangan itu disebutnya sebagai hari kesaktian Pancasila. Penyebutan itu memiliki makna mendalam, bahwa untuk kesekian kalinya upaya mencerabut peradaban nusantara tidak menuai hasil. Pancasila sebagai falsafah peradaban nusantara tidak bisa dihapus dan kedaulatan bangunan peradaban yang telah berdiri berabad-abad lamanya, tetap berdiri tegak.
Keberhasilan G.30.S/PKI bukan saja menempatkan Indonesia subordinat oleh comintern, akan tetapi juga mencerabut eksistensi peradaban nusantara yang secara fundamental berbeda dengan nilai-nilai dan sistem Komunis. Keberhasilan kudeta itu hanya akan menempatkan nusantara dalam kenangan sejarah dari peradaban-peradaban.
PERJUANGAN TINGGAL LANDAS
Selama lebih 30 tahun kepemimpinannya, Presiden Seharto berhasil membawa Indonesia kedalam pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% pertahun. Panjang usia harapan (life expectancy) meningkat tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1990. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolute menurun tajam dari 60% pada tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990. Investasi meningkat tajam, tabungan domestik cukup tinggi dan usaha pertanian tumbuh cepat sehingga mencapai swasembada pada tahun 1984. Inflasi dapat dipertahankan dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan mencapai 2,5% dan cadangan devisa dipertahankan mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selama 7 tahun —antara tahun 1983 sampai tahun 1990—, ekspor non migas telah tumbuh rata-rata diatas 20% pertahun dan ekspor barang-barang manufaktur tumbuh 30% setiap tahunnya.
Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara. Antara tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, (2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.
Apabila kondisi ini tidak mengalami distorsi dan krisis tahun 1997-1998, kekuatan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Indonesia masuk kelompok 20 negara terbesar di dunia.
- Proporsi produksi pertanian dalam PDB relatif menurun digantikan peningkatan proporsi manufaktur, walaupun secara absolut produksi pertanian meningkat.
- Separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat investasi perkotaan dan pertimbangan perlindungan lingkungan serta lahan pertanian.
- Pendapatan buruh meningkat secepat peningkatan PDB perkapita dan pertumbuhan luar Jawa akan lebih pesat.
- Ekspor tumbuh cepat melalui sistem perdagangan dan investasi menggantikan peranan pinjaman luar negeri.
- Pertumbuhan modal dan ketrampilan SDM menghasilkan pertumbuhan teknologi secara alami.
- Pendapatan dan lapangan kerja tumbuh secara cepat dan merata.
Sri Hadi, Phd, dalam bukunya berjudul “Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an”, memprediksikan apabila pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan secara konstan selama 50 tahun —selama dua kali Pembangunan Jangka Panjang/PJP dan tidak terdistorsi krisis ekonomi-politik pada tahun 1997/1998—, posisi Indonesia akan setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020. Pada tahun 1997, Indonesia sedang memulai tahapan Pelita (pembangunan lima tahun) tahap II dari skenario Pembangunan Jangka Panjang II (tinggal landas) yang dasar-dasarnya telah dibangun selama PJP I oleh Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto merupakan kader terbaik bangsa yang keseluruhan hidupnya dihabiskan untuk membangun bangsa ini. Mulai dari perjuangan fisik pada era kemerdekaan hingga perjuangan terwujudnya Tinggal Landas. Ia selalu hadir dalam momen-momen penting krisis bangsa. Mulai dari perlucutan tentara Jepang, menahan masuknya Belanda ke Indonesia, penggagalan Kudeta Presiden Soekarno Indonesia 3 Juli 1946, Serangan Umum 1 Maret 1949, meredakan pemberontakan-pemberontakan, menjadi panglima operasi Mandala, penggagalan kudeta PKI tahun 1965 dan perjuangan mewujudkan tinggal landas hingga tahun 1998. Keterkaitan erat perjalanan hidupnya dengan jatuh bangunnya bangsa ini, maka segencar apapun pihak-pihak tertentu berusaha menghapus peran Presiden Soeharto dari peta sejarah, tetap tidak akan menuai hasil. Penghapusan peran kesejarahan Presiden Soeharto akan berarti penghapusan eksistensi kesejarahan Indonesia itu sendiri. Jika generasi Presiden Seokarno menjadi peletak dasar visi kebangsaan, maka Presiden Soeharto lah peletak tiang pancang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui struktur kelembagaan negara yang kuat. Maka tidak heran jika ia berhasil membawa Indonesia menjadi Newly Industrializing Economies dan macan asia.
***