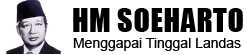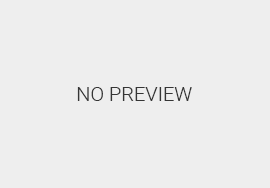Pak Harto Dan Trilogi Pembangunan (3)
Pak Harto Dan Trilogi Pembangunan (3)
Stabilitas Ekonomi: Antara Mekanisme Pasar dan Sistem Perekonomian Pasar Terkelola[1]
Oleh
Abdul Rohman
Presiden Soeharto juga dinilai berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi yang ditandai dengan relatif stabilnya harga-harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas ini diwujudkan dengan menerapkan mekanisme pasar terkelola dan menghindari “kapitalisme pasar bebas” yang digagas Milton Friedman, seorang pemegang Hadiah Nobel 1976 untuk ilmu ekonomi. Melalui para ekonom yang dimotori Widjoyo Nitisatro, pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan demokrasi ekonomi yang didalamnya tidak memberi tempat bagi: (1) sistem “free-fight liberalism” yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan serta mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia, (2) sistem “etatisme” dalam mana negara beserta aparatur negara berdominasi penuh dan yang mendesak serta mematikan potensi, serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, (3) gejala monopoli yang merugikan masyarakat, baik monopoli swasta maupun monopoli negara[2].
 Presiden Soeharto ditakdirkan naik ke panggung kekuasaan dengan mewarisi kondisi ekonomi yang secara eksponensial menderita kemunduran yang sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik tajam mencapai 100% per tahun antara 1962-1964 untuk kemudian melesat mencapai 650% dari Desember 1964 ke Desember 1965. Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari dan Indonesia terperangkap dalam spiral hyper-inflasi yang disebabkan tidak terkendali naiknya volume uang yang di dorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Empat puluh lima persen APBN dipergunakan untuk persenjataan sehingga tidak berdampak pada kenaikan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat. Kenaikan laju hyper-inflasi disebabkan oleh kumulasi beberapa persoalan, yaitu membesarnya defisit anggaran, arah alokasi anggaran ke jurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi. Ekspor dan impor menurun, sedangkan utang luar negeri perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960) turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS (1965)[3].
Presiden Soeharto ditakdirkan naik ke panggung kekuasaan dengan mewarisi kondisi ekonomi yang secara eksponensial menderita kemunduran yang sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik tajam mencapai 100% per tahun antara 1962-1964 untuk kemudian melesat mencapai 650% dari Desember 1964 ke Desember 1965. Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari dan Indonesia terperangkap dalam spiral hyper-inflasi yang disebabkan tidak terkendali naiknya volume uang yang di dorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Empat puluh lima persen APBN dipergunakan untuk persenjataan sehingga tidak berdampak pada kenaikan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat. Kenaikan laju hyper-inflasi disebabkan oleh kumulasi beberapa persoalan, yaitu membesarnya defisit anggaran, arah alokasi anggaran ke jurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi. Ekspor dan impor menurun, sedangkan utang luar negeri perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960) turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS (1965)[3].
Permasalahan yang dihadapi pemerintahan Presiden Soeharto pada awal kepemimpinanya meliputi kelangkaan pangan, kelangkaan suplai bahan pokok yang parah, terganggunya produksi, ekspansi moneter yang berlebihan, hiperinflasi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, berhentinya industri, pengangguran yang besar sekali, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri, utang luar negeri yang besar, krisis neraca pembayaran dan defisit anggaran. Maka program rehabilitasi dan stabilisasi yang dilakukan Presiden Soeharto dilaksanakan dengan[4]:
- Menyelesaikan konflik internal dan eksternal, masalah sosial, dan pemberontakan
- Menyelesaikan utang luar negeri
- Mengurangi laju inflasi
- Rehabilitasi infrastruktur
- Meningkatkan ekspor
- Menyediakan bahan pangan dan sandang bagi masyarakat.
- Mengatasi berhentinya industri, pengangguran, krisis neraca pembayaran, menurunnya cadangan devisa dan tunggakan utang luar negeri.
Untuk mengatasi permasalahan itu pemerintahan Presiden Soeharto melakukan: (1) stabilisasi keamanan, (2) minimalisasi pengeluaran yang tidak produktif, dan (3) penggunaan sumber daya langka secara efisien. Kebijakan dan rehabilitasi ekonomi pada era Pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun 1966 s/d 1970 dijalankan dan didasarkan pada:
- Sistem Perekonomian Pasar Terkelola
- Stabilisasi harga
- Pembentukan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia, meliputi: (1) tim birokrasi profesional yang disterilisasikan dari kepentingan politik, (2) dukungan politik kepada tim birokrasi, (3) penyediaan bantuan teknik untuk meningkatkan dan memperlancar jalannya ekonomi, (4) pembentukan Bappenas untuk merancang pembangunan nasional, dan (5) bantuan ekonomi penunjang pembangunan.
- Pemerintah bertindak langsung menghilangkan sebab-sebab inflasi dan bukan hanya berdasarkan gejala inflasi.
Para ekonom Orde Baru memandang mekanisme pasar secara murni —sistem pembentukan harga berdasarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan secara bebas— memang menjamin dihindarinya penghamburan (waste) dan kelangkaan (scarcity). Namun dibalik sistem ini terdapat kekuatan yang bisa mengakibatkan ketidak-seimbangan (dis-equilibrium) antara penawaran dan permintaan sehingga menimbulkan distorsi harga. Oleh karena itu harga yang terbentuk dalam pasar perlu dikoreksi secara sadar agar terjadi alokasi barang dan sumber lain untuk diarahkan mencapai sasaran perencanaan pembangunan. Widjoyo Nitisastro menekankan perlunya perencanaan mempengaruhi pasar melalui intervensi dalam penawaran ataupun permintaan. Ia mengembangkan analisa ekonomi guna memahami permasalahan pembangunan untuk kemudian melalui perencanaan pembangunan mengoreksi pasar dengan kebijakan mengalokasikan faktor-faktor produksi untuk mencapai sasaran pembangunan[5].
Pada era reformasi, sistem perekonomian pasar terkelola ditinggalkan dan sebagai gantinya diterapkan mekanisme pasar secara murni, sehingga menyebakan gejolak harga kebutuhan pokok sering dijumpai[6]. Pergeseran kebijakan itu dikarenakan telah masuk era perdagangan bebas dan lemahnya para pengelola ekonomi negara dalam mewujudkan efisiensi sosial sekaligus efisiensi komersial[7].
Era liberalisasi dan perdagangan bebas ditandai dengan diratifikasinya WTO, AFTA, dan NAFTA. Ratifikasi itu mengakibatkan sering terjadinya gejolak harga dan untuk mengendalikannya dilakukan dengan mendatangkan komoditi yang sama dengan harga lebih murah dari luar negeri. Secara komersial melakukan impor produk sejenis yang harganya lebih murah memang lebih efisien, namun secara sosial akan menghantam produksi dalam negeri dan bahkan dalam jangka panjang dapat mematikannya. Disinilah para penyelenggara ekonomi negara dituntut melakukan pengelolaan pasar secara lebih cerdas dengan mencari celah agar bisa melakukan stabilisasi harga sekaligus efisien secara sosial (menguntungkan pelaku ekonomi dalam negeri dan bukan sebaliknya). Sebagai contoh adalah Jepang yang juga telah meratifikasi WTO tidak memasarkan beras petaninya di dalam negeri dengan bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah. Kasus yang sama juga diberlakukan bagi produk-produk teknologi tinggi buatan Jepang. Bahkan untuk masuk golongan profesional (dokter, pengacara, ahli-ahli teknik, daln lain-lainnya), Jepang mensyaratkan kemahiran dalam bahasa Jepang baik lisan maupun tulisan. Kebijakan ini bukan saja menjadikan kompetitor-kompetitor dari luar akan berhadapan dengan budaya Jepang, akan tetapi menghadapi keseluruhan sistem budaya Jepang[8].
Para penyelenggara ekonomi negara pada era reformasi seharusnya menyusun road map yang jelas dan bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan keseimbangan efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Apabila liberalisasi dan perdagangan bebas tidak diiringi perlindungan negara dalam mewujudkan keseimbangan kedua hal tersebut, maka bukan saja perekonomian bangsa akan terus dihinggapi gejolak-gejolak harga, namun juga berdampak pada matinya pelaku ekonomi dalam negeri dan cita-cita untuk berdaulat serta mandiri dalam bidang ekonomi hanya terhenti sebatas slogan. Para penyelenggara negara harus mampu mencari solusi cerdas agar liberalisasi dan globalisasi bukan merupakan ancaman bagi kemandirian ekonomi dalam negeri, akan tetapi menjadikannya sebagai peluang agar rakyat Indonesia dapat menikmati efisiensi komersial namun juga memiliki kemandirian (efisiensi sosial).
***
[1] Disarikan dari buku Politik Kenusantaraan
[2] Widjoyo Nitisastro, Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjoyo Nitisastro, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm 62.
[3] Emil Salim, dalam “Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjoyo Nitisastro”, ibid, hlm xvii
[4] Sri Hadi, Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm 7-9.
[5] Emil Salim, Op. Cite, hlm xvii
[6] Seperti melonjaknya harga cabai, gula, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya.
[7] Efisiensi komersial menekankan ketersediaan barang dengan harga murah walaupun harus mengimpor produk dari luar negeri dan sebagai konsekuensinya menguntungkan atau membesarkan pelaku usaha (produsen) luar negeri. Sedangkan efisiensi sosial menekankan perlindungan pelaku ekonomi dalam negeri —khususnya UKM— walaupun barang yang sama dari luar negeri harganya lebih murah.
[8] Adi Sasono, Membangun Ekonomi Kerakyatan Untuk Membangun Ketahanan Nasional, makalah seminar “Ketahanan Ekonomi dan Kemandirian Bangsa”, Gedung Joang 1945, Kamis 25 November 2010, hlm 5-6.