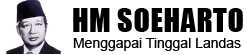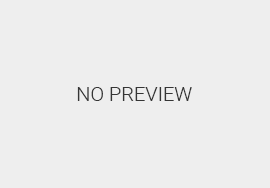Jodoh Saya
Jodoh Saya [1]
Suasana rundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang hidup, setelah Dewan Keamanan PBB menengahi persoalan Indonesia. Terdengar bahwa rundingan itu akan dilaksanakan di atas kapal Amerika “Renville” yang telah berlabuh di permulaan Desember di Tanjung Priok. Dan suasana rundingan Indonesia-Belanda ini ternyata disambung dengan rundingan mengenai diri saya pribadi.
Datanglah keluarga Pak Prawirowihardjo yang tinggal di Wuryantoro ke daerah di sekitar tempat saya. Maka saya menemui mereka. Percakapan kami pada mulanya menyangkut hal-hal yang biasa saja. Tetapi tidak lama setelah itu muncul pertanyaan yang tidak saya sangka. Ibu Prawiro bertanya soal hari depan saya. Diingatkannya bahwa saya sudah berusia 26 tahun. Dan hal ini menjadi pikirannya. Sebab di kampung kita, orang seusia itu mestinya sudah berumah tangga.
Mula-mula saya tidak menganggap serius soal ini. Saya jelaskan kepada mereka bahwa saya sedang sibuk di Resimen. Perjuangan belum selesai. Kekacauan masih mengancam. Belanda masih belum mau angkat kaki dari negeri kita. Tetapi Ibu Prawiro menekankan bahwa perkawinan tidak perlu terhalang oleh perjuangan. Membentuk keluarga adalah penting, katanya. “Tetapi siapa pasangan saya?” saya balik bertanya kepada mereka. Saya tidak punya calon. “Percayakan soal itu kepada kami,” kata Bu Prawiro. “Kamu masih ingat kepada Siti Hartinah, teman sekelas adikmu, Sulardi, waktu di Wonogiri?” tanya Ibu Prawiro. Saya mengangguk, mengiyakan. Saya ingat. “Tetapi bagaimana bisa?” pikir saya.
“Apa dia akan mau?” tanya saya. “Apa orang tuanya akan memberikan? Mereka orang ningrat. Ayahnya, Wedana, pegawai Mangkunegaran.” Bu Prawiro kelihatannya seperti tidak menganggap hal itu sebagai persoalan. Mungkin dirasakannya zaman sudah berubah. “Saya kenal dengan orang yang dekat dengan mereka,” kata Bu Prawiro. “Saya akan minta dia menanyakan, apa mereka dapat menerima kedatanganku. Saya tahu cara-caranya. Saya tahu adat kebiasaan di situ, ” katanya.
Saya tidak mau mengecewakan Bu Prawiro. Dan saya ingat, apa yang dikemukakan Ibu Prawiro itu benar. Hati saya tergugah, memang benar, kita mesti membentuk keluarga. Kita diwajibkan oleh keyakinan agama kita untuk melanjutkan keturunan kita dan hanya melewati pernikahan, kita bisa melanjutkan·keturunan kita dengan sah. Sebab itu, kita harus membentuk keluarga, sebagai perantara untuk melahirkan keturunan kita.
Ternyata Pak Soemoharjomo dan Ibu Hatmanti sedia menerima kami, setelah Ibu Prawiro mendapatkan seseorang yang bertindak lebih dahulu sebagai perantara. Maka kemudian upacara “nontoni”, pertemuan antara yangakan melamar dan yang dilamar; dilangsungkan. Agak kikuk juga sebab sudah·lania saya tidak melihat Hartinah dan keragu-raguan masih ada pada saya, apakah dia akan benar-benar suka kepada saya.
Dalam pada itu saya ingat, sudah ada pertanda baik, yakni mereka semua suka menerima kami. Itu artinya lampu hijau bagi kami. Ternyata pula suasana dalam upacara, “nontoni” itu baik sekali sehingga tidak diperlukan waktu lama, untuk kemudian langsung merundingkan soal waktu. “Ini rupanya benar-benar jodoh saya,” pikir saya. Dan jodoh itu sama seperti lahir dan ajal, menurut orang tua-tua kita. Kemudian saya tahu bahwa sewaktu kami berkunjung ke rumah mereka itu, Hartinah baru saja sembuh dari sakit selama sebulan.
Perkawinan kami dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo, pada waktu saya berusia 26 tahun dan Hartinah, istri saya, dua tahun lebih muda dari saya. Dari tempat tugas saya di Yogya saya naik sebuah kendaraan dinas tua menuju Solo. Saya mengenakan pakaian penganten, serapi-rapinya untuk waktu yang tidak tenang itu. Sebilah keris terselip di punggung saya. Waktu akan naik kendaraan itu, terasa bukan main repotnya. Sulardi yang mengantar saya, mengganggu saya sepanjang jalan.
Perkawinan kami dilangsungkan pada sore hari dengan disaksikan oleh keluarga dan teman-teman Hartinah. Cukupan banyaknya, sebab keluarga Pak Soemoharjomo cukup terpandang dan disegani di kota ini. Dari pihak saya hadir Sulardi dan kakaknya. Tetapi kejadian yang bagi saya amat penting ini sayang tak ada yang mengabadikannya dengan potret. Maklumlah, keadaan serba darurat. Malam harinya diadakan selamatan, tetapi cuma bisa dengan memasang beberapa buah lilin, karena kota Solo waktu itu harus digelapkan, di waktu malam, mencegah terjadinya bahaya besar jika Belanda melakukan serangan udara lagi.
Tiga hari sesudah perkawinan, saya boyong istri saya ke Yogya. Saya harus kembali menjalankan tugas militer saya. Dan kemudian istri saya mulai dengan tugasnya sebagai istri Komandan Resimen. Dunia baru baginya, sekalipun sebelum ini ia giat dalam Palang Merah, dekat dengan barisan-barisan pejuang.
Alhasil, perkawinan kami tidak didahului dengan cinta-cintaan seperti yang dialami oleh anak muda di tahun delapan puluhan sekarang ini. Kami berpegang pada pepatah “witing tresna jalaran saka kulina”, datangnya cinta karena bergaul dari dekat.
Dalam pada itu, saya sudah punya pegangan untuk mendayung perahu keluarga di tengah-tengah bahtera yang luas. Sebagai suami-istri, sepatutnya kita mempunyai cita-cita mendapatkan keturunan yang baik. Dan salah satu syarat untuk itu adalah adanya ketentraman di tengah kehidupan bersuami istri itu. Ketentraman itu sebenarnya adalah saling pengertian antara suami dan istri. Tanpa saling mencintai, saling mengerti, tak akan ada kebahagiaan di rumah. Dan kebahagiaan hidup antara suami-istri itu tidak hanya untuk kedua orang itu, melainkan termasuk kewajibannya untuk menurunkan keturunan sebagai kodrat orang hidup yang percaya kepada Tuhan Yang Maha kuasa. Bahwasanya suka terjadi cekcok antara suami dan istri, itu adalah manusiawi. Tetapi percekcokan itu bukan sesuatu untuk dibiarkan menjadi sebab perpecahan, melainkan untuk mengoreksi satu sama yang lain, saling mengendapkan diri dan bukan untuk menjadi berantakan.
Dengan pegangan itu kami berlayar di atas perahu keluarga kami. Dan kami kemudian dititipi enam anak, yakni tiga laki-laki dan tiga perempuan.
***
[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 43-46.