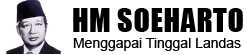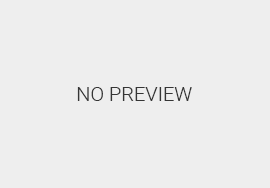Konsepsi Peradaban Pancasila (5)
Konsepsi Peradaban Pancasila (5)[1]
(Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan)
Oleh:
Abdul Rohman
Sila keempat Pancasila mengamanatkan agar penyelenggaraan negara —dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan peradaban bangsa, yaitu tercapainya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan terlindunginya segenap tumpah darah Indonesia— dilakukan secara demokratis berdasarkan pemerintahan rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat). Penyelenggaraan pemerintahan rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum secara periodik untuk memilih anggota-anggota legislatif (perwakilan rakyat), utusan daerah dan pejabat politis (Presiden, Gubernur, Kepala Daerah dan Kepala Desa).
Hal yang sering dikesampingkan adalah adanya amanat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dalam sila keempat. Amanat tersebut mengandung konsekuensi pengambilan keputusan dalam perumusan regulasi dan arah kebijakan penyelenggaraan negara harus berada dalam bimbingan “hikmat kebijaksanaan”[2]. Pencapaian “hikmat kebijaksanaan” bukan berarti identik dengan kesepakatan mayoritas, melainkan sebuah proses yang dilakukan dengan sadar, penuh pertimbangan dan tanggung jawab agar permusyawaratan-pemufakatan menghasilkan kearifan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa yang sejalan dengan philosophische grondslag. Oleh karena itu proses permusyawaratan-pemufakatan memerlukan pelaku yang benar-benar memahami philosophische grondslag, mencerminkan multikulturalisme nusantara dan memahami perubahan lingkungan strategis serta memiliki visi dalam menerjemahkannya kedalam kebijakan operasional penyelenggaraan negara. Institusi hikmat kebijaksanaan ini oleh UUD 1945 dibebankan kepada eksistensi utusan golongan (Pasal 2 UUD 1945) sehingga —meminjam istilah Bung Karno— MPR benar-benar menjadi cerminan aspirasi seluruh rakyat[3].
Selama ini dialektika ketatanegaraan kita lebih berfokus pada amanah “kerakyatan” dan “permusyawaratan perwakilan”. Terselenggaranya pemilu dan permusyawaratan-pemufakatan melalui para wakil rakyat hasil pemilu —di DPR maupun MPR— dianggap sudah cukup memenuhi amanat sila tersebut. Namun sejauh mana mekanisme pemilu itu mampu menjaring orang-orang terbaik dan mencerminkan pluralitas sehingga secara maksimal dapat merumuskan kebijakan negara dalam koridor “hikmah kebijaksanaan” masih harus direnungkan.
Presiden Soekarno mengaplikasikan konsep “yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” melalui demokrasi terpimpin, dengan menempatkan dirinya sebagai figur sentral dirigen tarik ulur perumusan arah maupun pelaksanaan kebijakan negara. Penerimaan terhadap dukungan berbagai pihak yang mengangkatnya sebagai Presiden tanpa batasan waktu —melalui jargon Presiden seumur hidup— telah menyimpang dari UUD 1945 yang secara tegas membatasi periode kepemimpinan Presiden dalam masa lima tahun, walaupun setelahnya bisa dipilih kembali[4]. Situasi kepemimpinannya perlu dimaklumi karena masa pemerintahanya diwarnai beragam instabilitas, sehingga pemilu tidak dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
Presiden Soeharto mengaplikasikan konsep tersebut dengan mengakomodasi perwakilan militer menjadi anggota DPR tanpa mengikuti pemilu[5] dan mengangkat para utusan golongan —yang berasal dari unsur ketokohan masyarakat— menjadi anggota MPR[6]. Unsur TNI dalam DPR mewakili aspirasi militer yang keberadaanya —demi terwujudnya stabilitas— harus bebas dari tarik ulur politik maupun keberpihakan pada salah satu golongan politik. Oleh karena itu eksistensi sentralnya sebagai penjaga kedaulatan negara dihargai dan diakomodasi dalam lembaga perwakilan. Keberadaan TNI dalam DPR memungkinkan adanya elaborasi secara cepat proteksi kewaspadaan —perkembangan Hambatan Tantangan Ancaman dan Gangguan (ATHG) terhadap kedaulatan negara dalam lingkungan strategis yang terus berubah— kedalam kebijakan negara.
Selain TNI, Presiden Soeharto juga mengakomodasi utusan golongan untuk mewakili elemen-elemen penting masyarakat seperti kelembagaan adat, kelompok agama, pemuda maupun kalangan kultural lainnya kedalam keanggotaan MPR[7]. Unsur utusan golongan —karena reputasi dan ketokohannya— diharapkan dapat menjadi pemerkaya perspektif dan kualitas “hikmah kebijaksanaan” dalam rumusan arah dan kebijakan strategis bangsa. Walaupun (mungkin sebagian) tidak memiliki kualifikasi akademik atau disiplin kepakaran sebagaimana wakil rakyat hasil pemilu, kompetensi dan reputasi unik utusan golongan sangat diperlukan untuk menjadi penyeimbang kalangan politisi yang berorientasi pada politik praktis[8]. Melalui MPR, para utusan golongan turut serta menentukan arah kebijakan negara dengan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pegangan pemerintah dalam menjalankan pembangunan[9]. Kebijakan Presiden Soeharto ini —yang didasarkan pada amanat UUD 1945— didekonstruksi seiring dengan generalisasi tuntutan “TNI kembali ke Barak” tanpa diiringi konsep pengganti institusi “hikmah kebijaksanaan” dalam penyelenggaraan negara.
Pada era reformasi, rekruitmen perwakilan rakyat (anggota DPR maupun perwakilan daerah) dilakukan melalui pemilu bebas. Sementara itu berdasarkan hasil amandemen terhadap UUD 1945, utusan golongan dihapus dari keanggotaan MPR[10] dan GBHN ditiadakan[11]. Konsekuensi penghapusan utusan golongan menjadikan para wakil rakyat terpilih (termasuk utusan daerah) murni dari kalangan politisi, atau orang-orang yang memiliki ketrampilan mengelola dirinya dalam kerja-kerja politik untuk dapat terpilih (menjadi anggota DPR atau DPD) melalui proses pemilu.
Proses tersebut —pemilihan langsung wakil rakyat tanpa memberi jalan mekanisme berbeda terhadap utusan golongan, khususnya dalam keanggotaan MPR— menyebabkan orang-orang yang kadar kualitasnya mendekati karakter filsuf (pejuang tanpa pamrih), baik dari kalangan agama (ulama khusus), tokoh adat, budayawan (bukan artis), orang-orang arif, kalangan cerdik pandai non politisi maupun tokoh masyarakat lainnya —yang sikap hidupnya terbebas dari bentuk-bentuk ambisi kekuasaan tapi keberadaanya sangat dibutuhkan atau bermanfaat bagi bangsa dan negara— tidak memperoleh ruang untuk turut serta menentukan arah dan kebijakan negara dari proses formal. Apabila diverifikasi secara jujur, barangkali hanya sedikit anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, yang benar-benar merepresentasikan karakter, pola pikir, kepribadian dan memahami aspek kejiwaan (keyakinan, budaya, cara pandang hidup) masyarakat daerah yang diwakilinya.
Akomodasi utusan golongan bukan saja dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang perspektif kalangan politisi —yang direkrut melalui pemilu bebas— akan tetapi juga merupakan bentuk pangayoman atau perlindungan terhadap multikulturalisme maupun aspirasi dan kompetensi unik yang ada dalam masyarakat nusantara dalam proses penyelenggaraan negara. Adanya utusan golongan dalam MPR memungkinkan semua komponen dalam masyarakat —TNI/tentara rakyat, intelektual dan pemuda, kelompok kultural: kelembagaan adat, kraton nusantara, budayawan (bukan hanya artis), pengusaha/ profesional/ pengendali sumberdaya ekonomi/ kuat secara ekonomi, Ulama)— memiliki saluran untuk turut serta menentukan arah dan kebijakan negara. Akomodasi kelompok-kelompok tersebut dalam penyelenggaraan negara dapat menumbuhkan sense of belonging bagi kelompoknya bahwa keberlangsungan eksistensinya dilindungi oleh negara.
Eksistensi GBHN bukan hanya terletak pada fungsinya sebagai road map pembangunan, yang bisa saja disediakan pemerintah. Eksistensi GBHN harus dilihat dari proses keterlibatan rakyat dalam perumusan arah dan kebijakan negara. Peran rakyat bukan hanya terletak pada perumusan kerangka umum penyelenggaraan negara (perubahan UUD oleh MPR dan fungsi legislasi DPR) akan tetapi juga dalam partisipasinya menentukan arah dan kebijakan negara, khususnya program-program prioritas pembangunan bangsa. Keberadaan DPR dan eksekutif dalam perumusan program pembangunan melalui penetapan APBN dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tidak cukup mewakili multikulturalisme aspirasi masyarakat Indonesia, karena pelakunya tidak mewakili multikulturalisme yang ada. Keberadaan UU (sebagai produk DPR-Pemerintah) juga selalu kalah cepat dalam menghadapi perkembangan situasi dan bahkan tidak jarang menjadi ajang transaksional kelompok ekonomi kuat sehingga keberadaanya tidak cukup mewakili dan melindungi kepentingan seluruh rakyat.
Tanpa disadari pelaku amandemen, implikasi penghapusan utusan golongan dan keterlibatan MPR dalam perumusan arah dan kebijakan negara (GBHN), dalam jangka panjang dapat menghapus eksistensi multikulturalisme Indonesia sebagaimana terhapusnya suku Indian di AS dan Aborigin di Australia. Kedua suku itu dipaksa untuk mengikuti sistem kompetisi yang tidak berimbang —dari segi kuantitas dan kompetensinya— sehingga lambat laun hanya tersisa sebagai monumen budaya dan tidak lagi memiliki ruang dalam turut serta menentukan arah dan kebijakan negara di tanah leluhurnya sendiri. Tanpa adanya Utusan Golongan, sebagaimana rumusan asli UUD 1945, suku-suku kecil di Indonesia, seperti contohnya saja suku Badui dan komunitas-komunitas adat kecil lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitas akan sulit dan bahkan mustahil bisa menyorongkan wakil-wakilnya dalam turut serta menentukan arah dan kebijakan negara melalui mekanisme pemilu terbuka.
Harus diakui rumusan partisipasi rakyat yang ada dalam UUD 1945 lebih modern dan demokratis —dari segi keterwakilan keragaman aspirasi kelompok-kelompok dan kompetensi unik masyarakat Nusantara— jika dibandingkan dengan UUD hasil amandemen. Untuk mencermati masalah tersebut kita perlu merenungkan pandangan Mr. Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa sesuai dengan budaya Nusantara, kepemimpinan harus memiliki ikatan batin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Jalannya kepemimpinan beserta kebijakan-kebijakannya juga harus merupakan hasil pemufakatan dengan rakyat sehingga mencerminkan suasana kebatinan dan rasa keadilan rakyat yang dipimpinnya[12].
Sebagai solusi atas keterlanjuran amandemen perlu dilakukan amandemen tahap berikutnya untuk mengembalikan eksistensi utusan golongan yang direkrut tanpa melalui pemilu dengan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, MPR terdiri dari DPR dan DPD yang direkrut melalui pemilu dan ditambah dengan utusan golongan yang direkrut dengan mekanisme tersendiri. Selain itu fungsi MPR dalam perumusan GBHN perlu dikembalikan sebagaimana tanggung jawab semula. Perubahan tersebut tidak harus merombak besar-besaran struktur ketatanegaraan sebagaimana yang telah dijalankan pada era reformasi.
Selain sebagai bentuk pengayoman terhadap multikulturalisme dan kemampuan unik anak bangsa, pengembalian utusan golongan dan fungsi MPR akan menghindarkan (meminimalisasi) penyelenggaraan negara dari otoritarianisme parpol. Era reformasi telah memberikan pelajaran berharga bahwa tingginya ongkos politik telah menjadikan proses penyelenggaraan negara terseret dalam bentuk-bentuk komplikasi politik parpol dan tidak jarang biayanya dibebankan kepada keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung (korupsi). Komplikasi parpol tidak jarang menjadikan kebijakan negara berada dalam penyanderaan kepentingan politik maupun pemodal kuat sehingga mengorbankan kepentingan rakyat banyak[13].
***
[1] Disarikan dari Buku Politik Kenusantaraan
[2] Rumusan tersebut tampaknya diambil dari salah satu ajaran Islam yang menyatakan “selesaikanlah permasalahan diantara kamu dengan cara musyawarah dengan bimbingan orang saleh”. Keterlibatan orang-orang yang memiliki kadar kearifan tinggi dalam proses permusyawaratan-pemufakatan diharapkan dapat menghasilkan output berupa arah dan kebijakan Negara yang berkualitas dengan tetap berpijak pada jiwa bangsa.
[3] Sebelum amandemen terhadap UUD 1945
[4] Pasal 7 UUD 1945
[5] Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang” dan tidak ada klausul tegas bahwa semua anggota DPR direkrut melalui pemilu. Keterbukaan dalam pasal tersebut memungkinkan Pemerintahan Presiden Seharto —dengan menggunakan undang-undang— mengangkat anggota TNI-Polri menjadi anggota DPR-DPRD tanpa melalui proses pemilu.
[6] Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
[7] Secara harafiah, utusan golongan seringkali diasumasikan sebagai perwakilan golongan, adat maupun agama. Sedangkan secara substansi, utusan golongan merupakan wadah orang-orang arif atau kader-kader terbaik bangsa yang karena keteguhannya memegang prinsip tidak menerjunkan diri dalam urusan dunia yang kotor (profane)misalnya perebutan jabatan walaupun keberadaanya diperlukan oleh negara. Seperti para ulama khusus, pilar-pilar kerajaan Nusantara, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dll. Selain peran penyeimbang, keberadaan mereka juga menjadi kanal (saluran) aspirasi bagi kelompok-kelompok yang tidak terwakili melalui rekruitmen politik formal.
[8] Politisi Parpol selalu dihadapkan pada dua kepentingan sekaligus, eksistensi politik kepartaiannya dan tanggungjawabnya turut serta merumuskan dan mengawal kebijakan negara sesuai philosophische grondslag. Keberadaanya rawan transaksional politis sehingga tanggungjawab utamanya merumuskan dan mengawal kebijakan negara sesuai philosophische grondslag seringkali tergadaikan.
[9] Pasal 3 UUD 1945 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara (GBHN)”. Keberadaan utusan golongan sangat strategis karena memiliki kesempatan turut serta menentukan arah dan kebijakan Negara.
[10] Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (amandemen keempat) menyatakan “Majelis Persmusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”
[11] Pasal 3 UUD 1945 (amandemen ketiga dan keempat) tidak memuat lagi adanya tugas MPR menetapkan GBHN.
[12] RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Badan Penerbiut FH UI, 2009), hlm 126. Soepomo menekankan paham integralistik, namun dalam rumusan UUD 1945 yang akhirnya disepakati bersama, adanya semangat gotong royong dalam kepemimpinan bangsa dihindarkan dari kemungkinannya terjebak dalam paham totaliter. Semangat gotong royong dimanifestasikan dengan adanya GBHN, sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam keikutsertaannya menentukan arah dan kebijakan bangsa yang akan dijadikan pedoman bagi eksekutif dalam melaksanakaan tugasnya.
[13] Sebagai contoh adalah tarik ulur pembuatan UU dimana keputusan DPR tidak jarang dikendalikan oleh transaksional ekonomis dengan kepentingan pemodal.